Distopia Bagi Kia
Bagian 7 Konsekuensi Sebuah Perbuatan

Keputusan nekat Kia untuk masuk ke dalam museum tanpa penjagaan dari pak Tejo ternyata berbuntut panjang. Papa sangat murka dan memecat supir Kia sejak kecil tersebut dengan emosi. Fakta ini baru diketahui Kia satu minggu kemudian, sewaktu ia merasa heran karena yang mengantarnya adalah pak Iman yang sehari-hari bertugas sebagai satpam rumahnya.
“Pak Tejo dipecat?” tanya Kia tanpa menyembunyikan ekspresi terkejutnya.
“Iya non, pak Tejo sekarang sedang berada di kamarnya, lagi siap-siap buat balik ke kampungnya. Kemarin malam, pak Labdajaya baru sempat telepon dia. Si Tejo juga dengan polosnya laporan apa adanya, cerita kalau dia nganter non Kia ke museum buat tugas sekolah. Sewaktu ditanya apakah pak Tejo ikut masuk ke dalam museum dan dia bilang enggak, wah tuan besar langsung marah besar non. Akhirnya pak Tejo dipecat deh.”
Kia begitu terperangah mendengar cerita pak Iman sehingga ia tidak bisa berkata-kata. Saat air matanya mulai menggenang, ia memutuskan untuk lari menuju ruangan pak Tejo yang terletak di bagian belakang rumahnya.
“Non, mau ke mana? Nanti telat sekolah lo.” ujar pak Iman berusaha mencegah Kia lari, yang tentu tidak dihiraukan oleh Kia. Di pikirannya, ia merasa begitu bersalah sehingga membuat supir yang selalu sabar menghadapinya diberhentikan secara buruk. Kia berlari sekencang mungkin, seolah takut pak Tejo tiba-tiba lenyap dari rumahnya.
Begitu sampai di depan kamar pak Tejo yang pintunya terbuka, Kia bisa melihat supirnya tersebut sedang memandangi sebuah foto tanpa pigura yang sedang ia genggam. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan raut wajah sedih, melainkan senyum getir yang bisa dirasakan oleh siapapun yang sedang melihat pak Tejo. Kia menjadi sedikit ragu untuk mengganggu momen pak Tejo. Terbesit di pikirannya untuk mengurungkan niatnya meminta maaf.
Untunglah pak Tejo menyadari bahwa ada orang yang sedang memperhatikannya. Ia memandang Kia dengan tatapan seperti biasanya ketika mereka akan berangkat dan pulang dari sekolah. Sama sekali tidak ada perasaan kesal ataupun dendam meskipun pemecatan yang diterimanya bisa dibilang berasal dari Kia.
“Eh non Kia, enggak berangkat? Hari ini yang nganter pak Iman ya, bapak udah enggak bisa nganter lagi.” kata pak Tejo diiringi dengan senyum tulusnya.
Pecahlah tangis Kia mendengar kalimat yang dilontarkan oleh pak Tejo. Ia terduduk sembari menutupi wajahnya. Pak Tejo langsung menghampiri Kia dan berusaha menenangkannya. Digiringnya Kia untuk duduk di sebuah kursi yang terletak di depan kamarnya. Kia terus menangis, tangisan penuh penyesalan. Seandainya saja ia tidak egois, seandainya saja ia mau menuruti permintaan pak Tejo, pasti hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Seandainya pak Tejo menemaninya ke dalam museum, mungkin saja Kia tidak perlu berurusan dengan kakek kurang waras yang ia temui tempo hari.
“Kenapa non kok nangis, sekarang udah hampir jam masuk sekolah lo, nanti nona telat enggak boleh masuk sekolah.” kata pak Tejo sembari menyodorkan segelas air putih ke Kia.
Butuh beberapa menit agar Kia bisa menghentikan tangisnya. Pak Iman dan beberapa pelayan rumahnya sudah berada di sekitarnya, memandangi Kia dengan wajah yang menunjukkan rasa penasaran yang besar. Tentu wajah pak Iman juga menunjukkan ekspresi khawatir karena bisa-bisa dia yang dipecat jika sampai Kia terlambat masuk sekolah.
Menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya, Kia akhirnya angkat suara.
“Hari ini Kia ijin enggak masuk sekolah aja, Kia ngerasa enggak enak badan. Tolong bilang ke pak Budi buat bikinkan surat ijin.” Pak Budi adalah kepala pelayan di rumah Kia, bertugas menyelesaikan berbagai urusan rumah, termasuk surat ijin apabila Kia tidak masuk sekolah.
Semua mengangguk-angguk, merasa maklum dengan apa yang sedang dirasakan oleh Kia sekarang. Satu per satu mereka meninggalkan Kia dan pak Tejo, kembali mengerjakan tanggungjawab mereka. Pak Tejo masih berdiri di samping Kia. Ia paham, anak majikannya tersebut memiliki sesuatu yang hendak disampaikan untuk dirinya. Sekarang, yang bisa ia lakukan adalah menunggu Kia tenang dengan sabar, sesuatu yang hampir setiap hari ia lakukan selama kurang lebih 10 tahun.
“Kia minta maaf pak, gara-gara Kia pak Tejo jadi dipecat. Pak Tejo jangan pergi dulu, nanti Kia akan berusaha mengubah pikiran papa. Mungkin papa ambil keputusan sambil emosi, jadinya enggak dipikir panjang.” Kia pada akhirnya mengeluarkan apa yang dari tadi hendak disampaikan sambil terisak.
“Enggak kok non, saya yang salah. Bagaimanapun, tuan sudah memberikan amanah ke saya buat menjaga nona, dan saya dianggap lalai dalam melaksanakan tugas. Nona Kia jangan merasa bersalah ya.”
“Tapi pak, Kia maunya diantar sama pak Tejo. Kia enggak mau diantar sama orang lain.”
“Saya paham sama perasaannya non, tapi perintah tuan enggak bisa dibantah. Saya sama sekali enggak jengkel ke nona kok. Saya yakin, semua peristiwa pasti ada hikmah di baliknya.”
Kia kembali terisak. Perasaannya terluka. Ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, menerima konsekuensi atas perbuatannya. Selama ini, ia tidak pernah membuat keputusan yang melawan keinginan orang tuanya. Kejadian di museum adalah pertama kalinya Kia memohon kepada orang lain agar mengabulkan keinginan egoisnya. Ia tak menyangka, keinginan tersebut menyebabkan kerugian untuk mereka berdua, Kia dan pak Tejo.
“Pak Tejo jangan pulang kampung dulu, Kia akan coba telepon papa. Mungkin papa bisa membatalkan keputusannya.” Kia masih berusaha mencegah kepergian pak Tejo.
“Enggak perlu non. Sejujurnya, saya juga sudah berencana untuk mengundurkan diri. Jadi, ya kebetulan kalau diberhentikan.”
“Kenapa pak? Apa pak Tejo udah enggak mau nganter Kia ke sekolah?”
“Bukan kok non, saya seneng selama jadi supirnya non.”
Pak Tejo menunjukkan sebuah foto seorang anak gadis kepada Kia, kira-kira masih duduk di bangku SMP. Kata pak Tejo, itu adalah foto anaknya di kampung. Di foto tersebut, ia tersenyum dengan manisnya, berdiri dengan posisi sedikit miring. Kia tidak pernah tahu bahwa pak Tejo memiliki anak perempuan. Bahkan, sebenarnya Kia tidak tahu apa-apa tentang pak Tejo.
“Saya merasa udah cukup lama merantau di ibukota, meninggalkan keluarga di kampung. Saya ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak saya lebih lama, walaupun penghasilan kerja di kampung tidak sebanding dengan gaji yang saya terima di sini. Jadi, saya harap nona bisa mengerti ya keputusan saya ini.”
Kia mengangguk kepala, walaupun sorot matanya masih mengandung penyesalan.
“Maaf kalau lancang, tapi nona sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Setiap pagi, setiap sore, saya merasa sedang mengantar anak saya sendiri. Karena itulah saya menikmati pekerjaan ini. Apalagi, nona tipe anak penurut yang enggak suka aneh-aneh. Pulang sekolah enggak pernah minta diantar ke tempat lain, kecuali kalau ada tugas kayak kemarin.”
Kia tidak membalas kalimat pak Tejo tersebut. Ia tidak pernah menganggap pak Tejo sebagai pengganti papanya, walaupun intensitas bertemunya dengan pak Tejo lebih panjang jika dibandingkan dengan papanya. Ia memutuskan untuk diam dan mendengarkan kalimat-kalimat selanjutnya dari pak Tejo.
“Saya berangkat satu jam lagi, dari sini naik bemo terus naik kereta. Kemarin si Budi sudah mengurus tiket pulang saya, jadi saya enggak perlu repot-repot beli tiket kereta. Nona baik-baik ya di sini, sementara Iman yang akan nganter nona sampai tuan menemukan supir baru buat nona.”
Sekali lagi, Kia menganggukkan kepalanya.
***
Setelah melihat kepergian pak Tejo dari balik jendela kamarnya, Kia memutuskan untuk mengurung diri di kamarnya. Ia berbaring di tempat tidurnya sambil memeluk guling, berharap guling tersebut bisa memeluknya balik untuk memberikan rasa tenang. Kejadian hari ini membuatnya sadar, bahwa dirinya tidak seacuh yang ia pikirkan. Dirinya masih memiliki kepedulian kepada orang lain, kepada pak Tejo, walaupun selama ini ia selalu bersikap dingin kepada beliau. Memang benar kata orang, kita baru merasa memiliki di saat kita kehilangan.
Walaupun pak Tejo bilang bahwa dirinya memang berencana pensiun sebagai supirnya, pasti tetap saja yang namanya dipecat secara tidak hormat terasa menyakitkan. Apalagi, sumber permasalahan tersebut berasal dari dirinya. Kia ingin menghukum dirinya sendiri, namun tak tahu harus berbuat apa. Menyayat tangannya sendiri dengan silet? Kia tidak berani melakukan hal-hal sadis seperti itu. Hatinya terlalu lemah hanya untuk sekedar memegang silet, apalagi mengiriskannya ke tangan.
Kia ingin mencurahkan apa sedang ia alami kepada seseorang, tapi siapa? Menelepon orangtuanya jelas bukan pilihan. Salah satu pelayan di rumahnya? Tidak mungkin, Kia tidak pernah dekat dengan mereka semua. Teman sekolah? Kia tidak punya yang namanya teman sekolah, walaupun hanya sekedar nomor ponselnya.
Berpikir tentang teman sekolah membuatnya teringat, tugas kelompok sejarah yang telah ia kerjakan sendirian masih ada di dirinya. Padahal, hari ini adalah hari pengumpulannya. Artinya, teman-temannya akan kena marah guru karena tidak bisa mengumpulkan tugas. Kia tidak terlalu mempedulikan hal itu, toh mereka sama sekali tidak membantu. Biarkan mereka menggunakan alasan absennya dirinya untuk mengelak dari teguran guru.
Kia beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan menuju meja riasnya. Selama ini, hanya bayangannya di cerminlah yang menjadi teman bicaranya di saat ia membutuhkan orang lain mendengarkan ceritanya. Walaupun tak pernah mendapatkan respon balik, Kia merasa bayangannya jauh lebih bisa mendengar daripada manusia betulan.
“Apakah memang lebih baik aku hanya diam dan menuruti segala perintah orang tuaku?”
Mungkin jawabannya adalah iya. Sekali ia mencoba untuk melawannya, ternyata berakibat fatal. Dampaknya memang tidak langsung ke dirinya, tapi ke orang lain. Ia begitu menyesali kepergian pak Tejo karena kesalahannya.
“Jika aku yang salah, mengapa papa tidak meneleponku dan memarahiku? Kenapa hanya marah ke pak Tejo?”
Mungkin karena aku memang sebegitu tidak pentingnya di mata papanya, jawab Kia dalam hati. Sebegitu tidak berharganya dirinya, sehingga ia tidak layak untuk dihubungi orang tuanya sendiri. Kia mulai menangis lagi di depan cermin. Entah mengapa akhir-akhir ini Kia begitu mudah mengeluarkan air mata. Padahal, sebelum ia berumur 17 tahun, bisa dibilang ia hampir tidak pernah menangis. Ia menjalani rutinitasnya tanpa membawa perasaan, membuatnya selalu terlihat tidak memiliki ekspresi.
“Kenapa aku harus hidup di lingkungan seperti ini?”
Seandainya saja kata-kata kakek tersebut benar, apakah ia akan bahagia? Seandainya saja kata-kata kakek tersebut bisa terjadi secara nyata, apakah ia akan memilih untuk memasuki dunia lain melalui cermin antik di museum itu? Apakah mungkin kejadian yang di luar logika seperti itu benar-benar bisa terjadi? Apakah kakek tersebut sungguh-sungguh bisa membawanya pergi ke dunia lain yang bisa memberikannya kehidupan yang lebih baik?
Kepala Kia terasa berat. Nampaknya hari ini ia benar-benar sakit. Mungkin itu hukuman dari Tuhan karena telah membolos untuk pertama kali seumur hidupnya, walaupun ia memiliki alasannya sendiri. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat tidurnya, mencoba terlelap agar beban-beban kehidupan yang sedang ia panggul bisa ia letakkan sejenak.
***
“Nanti malam kamu jadi terbang ke Singapura?” tanya pak Labdajaya ke istrinya.
“Jadi.” jawab bu Labdajaya tanpa menoleh ke arah suami.
“Kalau gitu, titip berkas ini untuk diserahkan ke George ya. Kita harus tuntut habis-habisan orang yang sudah menipu kita di Kalimantan.”
Bu Labdajaya menerima berkas tersebut dan memasukkannya ke dalam koper. George adalah salah satu pengacara andalan keluarga Labdajaya, dan ia bekerja di Singapura. Sudah satu minggu pasangan tersebut berada di Kalimantan, lebih lama dari yang direncanakan. Bagaimana tidak, proses jual beli tanah yang sudah disepakati ternyata bermasalah. Sertifikat yang mereka dapatkan ternyata palsu, ditiru dengan teknologi canggih sehingga begitu mirip dengan sertifikat aslinya. Selama seminggu terakhir, pak Labdajaya uring-uringan terus meskipun nilai kerugian yang mereka tanggung tidak seberapa jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Hanya saja, ditipu merupakan hal yang paling dibenci oleh pak Labdajaya. Kini, ia berusaha untuk mengejar sang penipu yang telah kabur membawa uangnya.
Kemarahan tersebut menjalar ke mana-mana, termasuk keputusan memecat pak Tejo karena melepas Kia tanpa pengawasan. Bu Labdajaya sudah berusaha untuk mengurungkan niat suaminya tersebut, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Keputusan telah diambil, pak Tejo telah pulang ke kampung halamannya karena satu kesalahan kecil. Padahal, dulu pak Labdajaya sendiri yang memilih pak Tejo untuk menjadi supir pribadi anaknya. Seluruh dedikasi yang telah diberikan pak Tejo luntur hanya karena satu peristiwa.
“Mungkin memang sebaiknya malam itu kami tidak perlu berangkat ke Kalimantan, dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama Kia.” gumam bu Labdajaya dalam hati.
Sebenarnya, ia ingin menghubungi anaknya. Akan tetapi, Kia sangat jarang mengecek ponselnya, bahkan seringkali dibiarkan mati selama beberapa hari. Bu Labdajaya khawatir, anak gadisnya tersebut sedang sedih karena harus berpisah dari supir pribadinya sejak kecil. Bagaimanapun, seorang ibu tentu memikirkan perasaan seorang anaknya, walaupun sang anak tidak bisa merasakannya.
Distopia Bagi Kia
Epilog: Sebuah Novel Untuknya

“Selamat ya, akhirnya novel perdanamu selesai.” kata Voni, salah seorang kenalan Rika di penerbit.
“Iya, terima kasih banyak ya buat bantuannya.” jawab Rika sambil tersenyum puas seolah sedang melihat anak pertamanya.
Rika menerima salah satu sampel novel yang sudah ditulisnya selama bertahun-tahun tersebut. Novel tersebut sudah ia tulis sejak ia duduk di kelas akselerasi dan mulai tinggal bersama Sarah. Karena berbagai hal, barulah novel ini jadi sekarang. Ia masih tak percaya bahwa akhirnya ia bisa mewujudkan impiannya sejak kecil, menulis sebuah novel dan menerbitkannya. Dulu ia sering diejek karena sering mencampuradukkan fantasi dan dunia nyata, namun lihatlah sekarang. Ia memberi judul novelnya Distopia Bagi Kia.
“Omong-omong, kenapa judulnya seperti itu? Jarang loh ada orang yang tahu apa arti distopia.” tanya Voni dengan penasaran.
“Hehehe, panjang deh ceritanya Von.”
Novel ini memang terinspirasi dari kisahnya sendiri yang memiliki masa lalu suram. Ia harus tinggal bersama orang yang sangat sering menyiksanya. Hal itu membuatnya merasa berada di sebuah distopia, di neraka dunia. Untunglah, ia bertemu dengan teman-teman yang baik, yang mau membantunya keluar dari permasalahan tersebut. Novel ini ia dedikasikan untuk teman-temannya.
Rika jadi teringat dengan Sarah. Awalnya, ia berniat untuk menggunakan kehidupannya sendiri sebagai latar belakang cerita. Akan tetapi setelah ditimbang-timbang, novelnya akan menjadi sangat suram. Ia pun mendapatkan ilham ketika mendengarkan cerita Sarah mengenai perasaan kesepiannya karena kesibukan orangtuanya. Maka, ia meminta izin ke saudara angkatnya tersebut untuk mengangkat kisahnya tersebut ke dalam novelnya. Sarah mengiyakannya tanpa perlu berpikir panjang. Setelah itu, imajinasi Rika lah yang menciptakan karakter-karakter lain, termasuk dunia cermin yang sangat berbau fantasi.
“Jadi, novel terbitan pertama ini mau kamu simpan sendiri atau mau kamu kasih ke seseorang spesial nih?” lagi-lagi Voni melontarkan pertanyaan.
“Aku udah janji ke seseorang buat ngasih buku perdanaku ke seseorang, jadi rasanya bakal aku kasih ke dia.”
“Cie, pacarmu ya?”
Rika hanya bisa tersenyum canggung. Tidak, ia tak pernah pacaran seumur hidupnya. Setidaknya, ia tak pernah peduli dengan hal tersebut. Baginya, ada orang yang mencintainya dengan sepenuh hati saja sudah lebih dari cukup. Kalau memang berjodoh, toh nantinya mereka akan berakhir di pelaminan. Rika sudah sering membayangkan hal tersebut, mengingat usianya sudah menginjak kepala dua. Akan tetapi, ia tak ingin terburu-buru. Biarlah ia menunggu sampai laki-laki tersebut melamarnya setelah menyelesaikan segala urusannya.
“Ya udah, aku balik dulu ya Von, sekali lagi terima kasih.” Rika memeluk temannya tersebut, lantas berbalik dan melangkah ke luar gedung.
Di luar sedikit gerimis, namun Rika membawa sebuah payung. Maka dengan perasaan riang gembira, ia melangkahkan kaki dengan ringan. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Selalu tampak ceria memang sudah menjadi sifatnya. Bedanya, ia tak pernah berpura-pura ceria untuk menutupi lukanya sekarang. Keceriaan yang ia tampakkan sekarang adalah keceriaan yang jujur.
“Leon, terima kasih untuk semuanya ya, novel pertamaku ini buat kamu.” gumam Rika kepada dirinya sendiri, sambil menatap langit yang kelabu.
TAMAT
Catatan dari Penulis
Penulis tersenyum lega setelah berhasil menyelesaikan novel Distopia Bagi Kia yang satu ini. Dibandingkan dengan novel Leon dan Kenji yang butuh bertahun-tahun, novel ini termasuk cepat proses penulisannya. Penulis memulai menggarap novel ini pada bulan Oktober tahun 2018, sehingga pengerjaan novel ini membutuhkan waktu satu tahun. Seperti yang sudah penulis sebutkan dulu sekali, novel ini terinspirasi dari imajinasi Ayu. Novel ini tidak akan lahir tanpa fantasinya yang luar biasa. Jadi, novel ini penulis dedikasikan untuknya.
Awalnya, penulis ingin rutin menulis setiap minggu satu bagian Distopia Bagi Kia dan satu bagian Leon dan Kenji (Buku 2). Setelah dijalani, ternyata berat sekali. Akhirnya, blog pun terpengaruh dan sering absen menulis. Akhirnya, penulis memutuskan untuk menunda dulu novel Leon dan Kenji dan berfokus untuk menamatkan novel ini terlebih dahulu.
Yang menyenangkan dari menulis novel ini adalah penggunaan sudut pandang ketiga yang membebaskan penulis. Alur cerita tidak terpatok hanya dari tokoh utama, kita juga bisa tahu bagaimana cerita berjalan dari karakter-karakter lain. Berbagai ide cerita juga muncul begitu saja ketika sedang mengetik di depan laptop.
Penulis juga belajar membangun karakter-karakter baru. Yang paling penulis dalami tentu saja karakter sang tokoh utama, Kia, yang sering menganggap dirinya merasa tidak berharga. Bisa jadi, ini merupakan jeritan hati penulis yang terkadang juga merasa seperti itu, hahaha.
Di dalam perjalanannya, penulis menonton beberapa anime yang karakternya seperti Kia. Sebut saja Sawako dari anime Kimi Ni Todoke atau Chiziru dari anime ReLife. Bayangan penulis tentang karakter Kia benar-benar tergambarkan oleh mereka. Bahkan, fisiknya yang berambut hitam panjang juga mirip. Padahal, penulis membuat karakter Kia jauh sebelum menonton anime-anime tersebut.
Karena bukan anak orang super kaya, penulis hanya bermodalkan ingatan kepada rumah-rumah orang kaya yang pernah muncul di televisi ataupun reality show. Bahkan, penulis menonton ulasan YouTube tentang mobil Mercedes yang ditumpangi oleh Kia untuk bisa benar-benar merasakan seperti apa berada di dalam mobil tersebut.
Ketika masuk ke dalam dunia cermin, penulis membayangkan lingkungan tempat Pak Kusno tinggal adalah desa tempat rewang penulis tinggal. Tentu, ada penambahan-penambahan tertentu seperti balai RW yang bisa menampung banyak orang dan kamar mandi umum yang digunakan bersama.
Pengalaman di Karang Taruna juga sedikit penulis sisipkan di sini. Alasannya, organisasi pemuda tersebut menjadi jalan termudah untuk Kia agar bisa merasakan yang namanya memiliki teman. Ketika berada di dunia tersebut, sangat sulit untuk membuat Kia bersekolah karena kondisi ekonomi Pak Kusno. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah lain agar Kia bisa berinteraksi dengan orang lain. Apalagi, di sana ia menemukan bakatnya: mengajar.
Klimaks dari novel ini adalah ketika ada pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Kia. Berbagai motif tersedia untuk mengusir Kia dari kampung dan mereka berhasil. Kia harus mengalami pengalaman pahit ketika harga dirinya hendak dijual, sebelum mengetahui bahwa itu semua merupakan rencana sang kakek untuk menyelamatkannya. Awalnya, penulis ingin mengakhiri novel ini di sini, namun penulis rasa apa yang Kia alami belum banyak membuatnya berubah.
Alhasil, ketika Kia kembali ke dunianya, ia menyadari bahwa hilangnya dirinya membawa dampak yang buruk. Mamanya meninggal dunia dan papanya kehilangan kewarasan. Ia yang tak tahu arah pun harus berakhir di panti asuhan. Di sana, ia baru menemukan betapa berharganya memiliki orangtua yang lengkap. Kia merenungi segala hal yang terjadi padanya dan berharap diberikan kesempatan kedua. Penulis mengabulkan keinginannya tersebut.
Dua bagian terakhir novel ini merupakan bagian yang membuat penulis sangat bersemangat. Kia memiliki kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat. Ia telah banyak berubah dan menjadi pribadi yang lebih hangat, berani mengungkapkan perasaan, dan menyadari apa yang ada di pikirannya selama ini tidak benar. Banyak orang yang menyayanginya.
Lantas, timejump pun terjadi dan Kia telah menjadi wanita dewasa. Melihat karakter yang dibuat sendiri telah berkembang sedemikian rupa bisa menimbulkan efek haru kepada penulis. Lucu memang, penulis akui hal tersebut.
Penulis membuat novel ini seolah-olah merupakan novel buatan Rika, salah satu karakter dari novel Leon dan Kenji. Alasannya, penulis ingin membuat semacam universe sendiri. Salah satu cara yang bisa penulis lakukan untuk menghubungkan novel ini dengan novel Leon dan Kenji adalah menjadikannya sebagai novel ciptaan Rika yang memang gemar menulis novel.
Setelah nanti novel Leon dan Kenji tamat, penulis sudah merencanakan untuk menulis dua atau tiga novel yang juga masih berkaitan dengan novel-novel yang sudah penulis tulis. Yang sudah ada konsep idenya adalah sebuah novel dengan Rika sebagai karakter utamanya. Sebelum itu, penulis harus segera menyelesaikan novel Leon dan Kenji (Buku 2). Jika tidak ada halangan dan tetap berisikan 50 chapter sesuai rencana, maka kemungkinan novel ini akan tamat pada lebaran tahun depan. Masih panjang memang, tapi penulis yakin bisa menyelesaikannya.
Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pembaca yang sudah menyempatkan diri untuk membaca novel buatan penulis yang satu ini. Tak peduli seberapa sedikitpun yang membaca, hal tersebut sudah cukup untuk penulis jadikan energi dalam menulis novel ini.
Distopia Bagi Kia
Bagian 30 10 Tahun Kemudian

“Aqila, tolong bantu ambilkan handphone kakak di kasur, dong.” ujar Kia yang sedang sibuk merias diri di depan cermin. Posisinya yang sedang menggambar alis membuatnya tak bisa beranjak dari tempat duduknya. Untunglah, adik angkatnya Aqila sedang berada di kamarnya.
“Ini kak, mau ke mana sih?” tanya Aqila sambil menyerakan ponsel kakaknya. Ia jarang melihat kakaknya merias diri di depan cermin. Artinya, kakaknya ini akan menghadiri sebuah acara penting bagi hidupnya.
“Mau meresmikan impian kakak semenjak sekolah. Mumpung sudah lulus kuliah, kakak punya sedikit waktu senggang sebelum masuk ke perusahaan papa. Kamu sih diajakin enggak mau.”
“Ih, Aqila kan ada les main biola. Bulan depan papa mau ada acara keluarga di sini, dan kakak tahu sendiri gimana papa. Selalu ingin membanggakan anak-anaknya.”
“Hehehe, gantian, dulu kakak juga sering banget les piano sampai jari-jarinya kakak keriting. Untung kamu punya bakat main biola, kalau enggak mungkin kamu disuruh mainin gendang!”
“Ih, kakak nakal!” kata Aqila sambil mencubit-cubit lengan Kia.
Kia tertawa ketika melihat ekspresi kesal yang ada di wajah Aqila. Adiknya ini telah menjadi gadis remaja cantik berusia 15 tahun. Dirinya sendiri telah berusia 27 tahun, telah menyandang gelar PHD bidang manajemen bisnis di salah satu kampus terbaik dunia untuk bidang tersebut. Dengan kemampuan otaknya yang cerdas, Kia bisa menembus ketatnya persaingan di sana, melawan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia yang juga mengincar gelar serupa.
Setelah lulus dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan teman-teman kuliahnya, ia memutuskan untuk pulang agar bisa membantu papanya yang sudah menunjukkan isyarat akan segera pensiun. Dulu, tak pernah terbayang ia akan masuk ke dalam perusahaan papanya. Di dalam benaknya, hal tersebut merupakan neraka tambahan baginya. Namun sekarang pikirang tersebut sudah bisa ia enyahkan. Dengan senang hati ia akan meneruskan pekerjaan papanya, dimulai dari tingkat bawah dan mempelajari semua yang bisa dipelajari.
Meskipun begitu, Kia memiliki impian yang sudah lama ingin ia realisasikan. Baru sekarang lah ia memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian tersebut. Ia begitu bahagia dengan semua yang ia alami ini.
Kia mengecek ponselnya dan memeriksa pesan yang masuk. Lima belas menit lagi ia akan datang menjemput dan mengantarnya pergi ke acara penting tersebut.
***
Selesai berdandan, ia segera mencari mamanya yang biasanya sibuk di dapur. Semenjak pensiun dari dunia kerja, Bu Labdajaya sering melakukan eksperimen makanan dan banyak berhasil. Malah, Bu Labdajaya membuka sebuah restoran baru dan laris manis hingga membuka cabang di luar negeri. Bu Labdajaya hanya berperan sebagai pemilik, sehingga tidak terlalu sering meninggalkan rumah. Memang kalau otaknya sudah otak bisnis, apapun bisa menjadi lahan pemasukan.
“Ma, Kia berangkat dulu, ya.” kata Kia ketika menemukan mamanya sedang memegang senampan kue yang baru dikeluarkan dari oven.
“Sarapan dulu, nanti asam lambungmu naik lagi, loh.”
“Udah kok tadi, tenang aja aku bawa obat maag.”
“Dasar kamu, ya. Tapi kamu keliatan cantik banget hari ini.”
“Kan Kia mau ada acara penting.”
“Ada acara penting apa karena mau dijemput sama calon suami?”
Mendengar ucapan mamanya tersebut, Kia langsung tersipu malu. Dirinya belum pernah membicarakan masalah tersebut dengan laki-laki itu, walaupun beberapa kali sudah membayangkan. Di usianya yang sekarang ini, menikah adalah hal yang lumrah. Apalagi, mereka berdua berasal dari keluarga yang mapan sehingga tidak alasan untuk menunda pernikahan.
“Ih mama selalu gitu, Kia kan jadi malu.”
“Ya udah kamu hati-hati. Bilang sama Yoga, jangan mentang-mentang mobilnya canggih terus jadi seenaknya sendiri.”
“Tenang ma, Yoga kalau nyetir pelaaaaaan banget. Kalau ada semut lewat aja dia pasti berhenti dulu, nunggu semutnya lewat.”
“Kamu sayang ya sama Yoga?”
Sekali lagi pertanyaan mendadak dari mamanya membuat Kia merasa serba salah. Meskipun dirinya telah bisa bergaul dengan orang secara lebih baik, ia merasa tetap malu jika ditanya masalah cinta. Ia tak terlalu mengerti hal tersebut dan tak terlalu pandai mengekspresikannya. Wajar jika mamanya sering menggoda Kia.
“Ih mama, Kia enggak suka digoda kayak gitu.”
“Aduh, mama udah ingin gendong cucu nih, Aqila masih 15 tahun lagi, gimana ya caranya biar bisa dapat cucu.” Bu Labdajaya justru semakin menjadi-jadi dalam menggoda Kia.
Tidak ingin digoda lebih lanjut, Kia segera menyalami tangan mamanya yang masih menggunakan sarung tangan masak. Meskipun teknologi dapur sudah semakin canggih, Bu Labdajaya masih lebih suka menggunakan cara-cara tradisional. Katanya, kue dan masakan lebih enak jika prosesnya seperti ini.
Ketika Kia sudah berada di beranda rumah, terlihat Yoga dengan mobil elektriknya telah tiba, nyaris tanpa suara. Yoga memang seseorang yang sangat peduli dengan lingkungan. Ia sering melakukan aksi-aksi sosial untuk mengurangi polusi dan penggunakan bahan bakar fosil. Bahkan, ia sudah memiliki perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.
“Pagi Kia, cantik banget hari ini.” sapa Yoga ketika ia keluar dari mobilnya. Semenjak hubungan mereka makin dekat, Yoga tak pernah lagi menggunakan lo gue ketika berbicara dengan Kia.
“Pagi-pagi udah gombal kamu, ya. Ayo deh kita langsung berangkat.”
“Cie cie, pagi-pagi udah pacaran aja.” teriak Aqila dari jendela lantai atas. Seruannya tersebut membuat beberapa orang yang kebetulan sedang berada di dekat sana tertawa kecil.
“Aqilaaa!!!!” Kia berteriak untuk membuat adiknya bungkam, yang justru semakin membuat Aqila tertawa terbahak-bahak.
“Adikmu yang satu itu memang sangat jahil, ya.” celoteh Yoga, sedikit tersipu mendengar teriakan tadi.
“Ya begitulah, padahal waktu pertama kali kenal dulu pendiam.”
“Iya, aku kan kenal lebih dulu dari kamu, pasti tahulah. Syukurlah, nampaknya ia bahagia semenjak tinggal di sini.”
“Iya. Omong-omong, bagaimana kabar Lia?” Kia menanyakan tentang mantan teman sekamarnya di panti asuhan tersebut, meskipun Lia tak ingat pernah tinggal sekamar dengan dirinya.
“Baik kok, dia sudah jadi pengajar di panti, walaupun cara ngajarnya agak nyeleneh.”
“Yah, dari dulu ia memang begitu kok. Tapi Lia baik dan cerdas kok.”
“Kalau enggak gitu ya mana mungkin ia diangkat jadi pengajar. Ya udah, berangkat yuk, takut keburu macet.”
Maka mereka berdua pun melintasi jalanan Jakarta yang sebenarnya sudah tidak terlalu ramai. Selain karena ibu kota telah dipindah, jenis transportasi umum yang tersedia pun makin beragam. Kesadaran masyarakat juga semakin tinggi. Kota ini, kota yang dulu tidak disukai oleh Kia, telah bertransformasi menjadi kota yang begitu ramah lingkungan.
“Pulangnya, mampir ke Kota Tua ya.” kata Kia tiba-tiba.
“Ada apa emangnya?”
“Enggak apa-apa, pengen aja. Emang enggak boleh?”
“Boleh kok, iya nanti kita ke sana.”
Setelah 30 menit perjalanan, Kia dan Yoga telah sampai di tempat tujuan. Sebuah gedung berlantai tiga terlihat baru saja diselesaikan pembangunannya. Kia akan memberikan nama tempat ini Ruang Belajar, sama seperti nama kegiatan mengajarnya ketika berada di dunia cermin tersebut. Bangunan ini akan menyediakan fasilitas gratis bagi siapapun yang ingin belajar, selama menunjukkan keinginan yang kuat. Harta keluarganya lebih dari cukup untuk membuat tempat ini, dan hari inilah peresmiannya.
Kia menjalani beberapa prosesi acara dengan baik, hingga puncak acaranya pemotongan pita. Beberapa orang sejak pagi telah mengantri untuk melakukan pendaftaran. Kia melihat orang-orang yang melakukan pendaftaran tidak sebatas anak-anak usia sekolah. Banyak orang dewasa yang juga ikut mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini.
Kia yang sedang mengamati para calon peserta tiba-tiba terdiam ketika melihat sepasang suami istri sedang ikut berbaris. Kia segera menghampiri mereka untuk memastikan ia tidak salah melihat.
“Pak Kusno dan Bu Imah?” tanya Kia dengan suara yang sedikit bergetar.
“Iya, mbak kok tahu nama kami?” jawab Pak Kusno dengan perasaan sedikit takut karena takut dirinya sudah melakukan hal yang salah.
Kia tak bisa membendung air matanya ketika melihat mereka berdua, meskipun ia tahu Pak Kusno dan Bu Imah tak pernah melihat dirinya. Ia tiba-tiba memeluk mereka berdua dan membuatnya menjadi tontonan orang-orang. Yang dipeluk bingung harus berbuat apa.
“Maaf maaf, bapak dan ibu mirip dengan kenalan saya, kebetulan namanya sama. Bapak dan ibu mau mendaftar di sini, kan? Silakan, semoga kami bisa membantu bapak dan ibu.”
Setelah berkata seperti itu, Kia meninggalkan mereka berdua yang nampak kebingungan. Yoga melihat hal ini dan bertanya kepada Kia apa yang terjadi.
“Enggak apa-apa kok, aku cuma kaget aja waktu lihat mereka. Aku harus pastikan mereka berdua mendapatkan apa yang dibutuhkan selama belajar di sini.” jawab Kia dengan mata yang masih berkaca-kaca.
***
Yoga menepati janjinya dengan mengantar Kia pergi ke Kota Tua seusai acara. Kia sendiri tidak tahu mengapa dirinya ingin pergi ke sana. Perasaannya yang menuntun dirinya pergi ke tempat yang sudah memberikannya banyak hal ketika ia masih gadis berusia 17 tahun. Mungkin, ia ingin berterima kasih kepada tempat tersebut, terutama cermin yang ada di museum tersebut.
Setelah menemukan tempat parkir, Yoga dan Kia berjalan bersama untuk masuk ke dalam Museum Sejarah Jakarta. Ketika berada di lantai dua, Kia segera mencari cermin raksasa yang membuat dirinya bisa masuk ke dunia lain. Anehnya, ia tidak berhasil menemukan cermin tersebut, bahkan setelah mengitari tempat tersebut berkali-kali.
“Yoga, kamu pernah tahu ada cermin antik yang ukurannya besar di museum ini, enggak?” tanya Kia kepada Yoga yang sudah memasang wajah kebingungan.
“Cermin? Seingatku enggak ada deh. Emang kapan kamu terakhir lihat?”
“Sepuluh tahun lalu, sewaktu kita masih SMA. Dulu ada cermin besar gitu, yang bikin…” Kia tak melanjutkan kalimatnya. Hingga hari ini, belum ada yang tahu kisahnya di dunia cermin. Mamanya pernah mendengar cerita tersebut, namun Kia mengatakannya sebagai mimpi.
“Mungkin sudah dipindah? Coba aku tanyain ke petugas museum.”
Yoga pun segera menghampiri salah satu petugas museum yang ada di dekat mereka. Sang petugas segera menjawab pertanyaan tersebut.
“Selama dua puluh tahun kerja di sini, enggak pernah ada cermin neng di sini. Yang ada paling ya lemari, meja, kursi, tapi enggak ada cermin.”
“Tuh Kia, enggak pernah ada cermin di sini.” ujar Yoga menambahkan.
Kia merasa bingung dengan kejadian ini, tapi memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Mungkin, sang kakek tua itulah yang telah membawa cermin itu ke mari, dan sang kakek pula yang membawa cermin itu keluar. Kia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum beranjak pergi, ia berkata lirih yang ditujukan kepada museum.
“Terima kasih, karena telah mengeluarkanku dari distopia.”
***
Di belahan dunia lain yang tak seorang pun tahu di mana berada, seorang kakek tua sedang memegang tongkat pancingnya dengan sabar. Tak ada tanda-tanda ikan mau menggigit umpannya. Di sebelahnya, terdapat sebuah cermin ajaib yang mampu berubah wujud dan mengabulkan keinginan pemiliknya. Hanya aja, cermin tersebut hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berhati tulus dan tidak memiliki niatan jahat sama sekali. Tugas sang kakek adalah mencari orang yang membutuhkan bantuannya.
Untuk kasus Kia, perjalanan yang ia lalui memang harus panjang. Keinginannya sederhana, namun Kia tidak menyadari bahwa semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia harus mengalami berbagai peristiwa agar dirinya sadar dan permintaannya untuk hidup dengan penuh kasih sayang terkabulkan.
Tali pancing sang kakek tiba-tiba bergetar. Itu merupakan tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkannya.
“Ah, kali ini siapa yang akan membutuhkan bantuan cermin ini?”
Distopia Bagi Kia
Bagian 29 Awal yang Baru

Kia terbangun pada pagi hari itu dengan kepala yang sedikit sakit. Tidurnya terasa sama sekali tidak nyenyak. Ia tidak begitu ingat mimpi apa ia semalam, kecuali dirinya seolah sedang tersedot lubang hitam dan menyeretnya dengan kecepatan cahaya. Anehnya, tubuhnya tidak hancur meskipun mendapatkan tekanan yang secara logika akan dengan mudah meluluhlantakkan tubuhnya.
Ketika kesadarannya mulai pulih dan matanya mulai menangkap cahaya yang masuk, Kia baru menyadari keanehan yang terjadi. Ia tidak sedang berada di dalam kamar panti bersama Lia, melainkan di sebuah kamar mewah dengan perabotan yang lengkap. Sepiring makanan lengkap dengan segelas air putih telah tersaji di samping tempat tidurnya.
“I…ini di mana?” tanya Kia kebingungan sembari menoleh ke kanan dan ke kiri.
Beberapa detik kemudian, barulah Kia sadar bahwa dirinya tengah berada di kamarnya sendiri, di rumah keluarga Labdajaya. Kia terkena serangan panik ringan sehingga berusaha mencari pegangan untuk menjaga agar tubuhnya tetap tenang. Tak ada kalimat yang meluncur dari mulutnya. Ia benar-benar bingung dengan apa yang tengah terjadi pada dirinya.
“Apa aku sudah mati?” tanya Kia dalam hati.
Setahu Kia ketika seseorang mati, ia akan mengalami masa penghakiman terlebih dahulu sebelum Tuhan menentukan dirinya masuk neraka atau surga. Akan tetapi, semua ini terasa begitu nyata. Apakah ini mimpi dalam bentuk lain? Apakah sebenarnya masih belum terbangun dari tidurnya?
Kia mencoba untuk mencubit pipinya keras-keras, dan ia sedikit mengaduh karena kesakitan. Ternyata ini bukan mimpi, ini semua kenyataan. Tapi, bagaimana bisa? Jelas-jelas semalam setelah berbicara dengan Aqila, dirinya beranjak ke tempat tidur dan merenungkan banyak hal. Ia bahkan berharap bahwa dirinya diberikan kesempatan ulang untuk memulai semuanya dari awal.
Ataukah harapannya tersebut benar-benar terkabul?
Hal pertama yang melintas di pikiran Kia adalah mencari orang-orang rumah, para pelayan rumah yang selama ini telah setia mengabdi untuk keluarga Labdajaya. Setelah menenggak air putih yang ada di sebelahnya, ia segera keluar dari kamar tersebut dan mencari orang yang bisa ditanya.
“Halo, apakah ada orang di sini? Halooo!” jerit Kia ke sana ke mari, mencari siapapun yang mendengar suaranya. Tak lama kemudian, muncullah pak Budi, kepala rumah tangga keluarga Labdajaya.
“Non Kia? Ada apa pagi-pagi teriak-teriak? Nona sakit?” tanya Pak Budi dengan khawatir. Bagaimana tidak, jika sampai Kia sakit, ia yang harus bertanggung jawab.
“Pak Budi, sekarang tanggal berapa?” tanya Kia kepada Pak Budi dengan tergesa-gesa. Sejak dulu, Kia tidak pernah dekat dengan Pak Budi sehingga pertemuannya ini terasa biasa saja.
Pak Budi pun menyebutkan sebuah tanggal yang ternyata persis hari ulang tahun Kia satu tahun yang lalu, sebelum Kia memutuskan untuk pergi ke dunia cermin. Kia terkejut mendengar hal ini hingga ia terjatuh dalam posisi duduk.
“Non Kia! Pusing, ya? Saya antar ke kamar, ya. Setelah ini, saya panggilkan dokter Andreas langganan kita.” kata Pak Budi sembari berusaha membantu Kia berdiri kembali.
“Enggak apa-apa pak, saya enggak apa-apa. Saya cuma kaget.”
Kia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu, ke masa ketika semua masih baik-baik saja, ke masa ketika dirinya belum bertemu dengan kakek tua dan masuk ke dalam dunia cermin. Apakah ia bisa kembali ke sini karena bantuan sang kakek? Di mana ia bisa bertemu dengan kakek tersebut sekarang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum menemukan jawaban tersebut, Kia tahu harus berbuat apa sekarang.
“Maaf Pak Budi, saya kembali ke kamar dulu, ya. Terima kasih.”
Dengan sedikit berlari, Kia segera masuk ke kamar dan mencari ponselnya. Setelah itu, ia mencari nomor mamanya dan segera menghubunginya. Mamanya bisa aja sedang berada di luar negeri atau sedang rapat penting, sehingga ia tidak berharap telepon darinya langsung diangkat.
Namun Kia keliru. Mamanya menjawab telepon tersebut.
“Halo sayang, ada apa? Tumben telepon jam segini? Di sana masih pagi, kan?”
Mendengar suara mamanya, Kia langsung menangis keras-keras. Mamanya pun terdengar kebingungan karena tidak bisa melihat wajah Kia secara langsung.
“Kia sayang, kamu kenapa? Mama video call, ya.”
Jantung Kia berdebar dengan begitu kencangnya. Ia belum siap bertatap muka dengan mamanya. Akan tetapi, ia tidak bisa mengabaikan panggilan video call yang sedang berdering. Ketika ia mengangkat panggilan tersebut, terlihat wajah mamanya yang terlihat khawatir.
“Kenapa sayang, kamu ada masalah? Mama masih di California nemenin papamu, tapi besok lusa mampir Jakarta, kok.”
Kia belum bisa berhenti menangis. Bu Labdajaya juga nampak sabar menunggu Kia bisa bicara dengan baik. Beberapa orang rumah sedang berdiri di ambang kamar pintu, mengamati Kia dari kejauhan. Mereka tidak pernah melihat Kia seemosional ini. Selama ini, kapan pun dalam peristiwa apapun, Kia selalu terlihat memasang wajah datar tanpa ekspresi.
“Ki…Kia kangen sama mama, Kia ingin ketemu sama mama.” ujar Kia setelah bisa menghentikan tangisnya untuk sesaat.
“Iya, mama juga kangen, besok lusa kita ketemu, ya.”
“Kia mau tinggal sama mama, Kia enggak mau ditinggal lagi sama mama.”
Bu Labdajaya tercenung mendengar perkataan Kia ini. Selama ini, Kia tidak pernah protes walaupun harus selalu ditinggal oleh kedua orangtuanya sehingga tidak pernah menyadari perasaan Kia yang seperti ini. Melihat anak semata wayangnya berada dalam kondisi merana, ia pun meneteskan air mata karena merasa bersalah.
“Maaf ya Kia, maafin mama udah terlalu sibuk buat kamu. Nanti mama bicarakan sama papa dulu, ya. Enggak mungkin mama tiba-tiba pensiun dari dunia kerja. Kamu yang sabar, ya. Mama usahakan untuk pulang duluan.”
Kia menganggukkan kepala, lantas mematikan video call tersebut. Setelah itu, ia naik ke atas tempat tidurnya dan kembali menangis. Dari percakapan barusan, Kia bisa melihat apa yang selama ini tidak terlihat: kasih sayang mamanya. Selama ini ia dibutakan oleh pikirannya sendiri sehingga tidak bisa melihat hal tersebut. Jika keajaiban ini tidak pernah terjadi, mungkin untuk selamanya Kia tidak akan mengerti.
***
Keesokan harinya, Kia memutuskan untuk tidak masuk sekolah terlebih dahulu. Ia masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Selain itu, ia juga belum tahu harus berbuat apa ketika bertemu dengan teman-teman kelasnya nanti. Ia harus bertemu dengan orangtuanya terlebih dahulu agar bisa merasa lebih tenang. Mamanya kemarin malam sempat menelepon bahwa ia telah membeli tiket pulang ke Jakarta, sedangkan papa masih harus tinggal sebentar di Amerika. Sesuai jadwal, harusnya sore ini Bu Labdajaya sudah tiba di Jakarta.
Kia gelisah seharian menanti kedatangan orangtuanya. Apa yang ada di dalam hati Kia sekarang adalah perpaduan antara rasa rindu dan bersalah. Ia tidak tahu harus berbuat apa ketika bertemu dengan mereka. Bagi dirinya, ia telah satu tahun lebih tidak bertemu dengan orangtuanya. Walaupun begitu, seharusnya dirinya di masa ini tidak pernah menghilang, sehingga orangtuanya juga tidak pernah merasa kehilangan dirinya.
Detik demi detik rasanya sangat lama bagi Kia. Tidak pernah rasanya ia menantikan sesuatu seperti sekarang. Sejak pagi, ia sudah berada di beranda rumah dengan cemas. Pak Tejo, supir Kia, melihat anak majikannya tersebut dan berinisiatif untuk mendekatinya.
“Non enggak sabar buat ketemu mama, ya?” tanya pak Tejo dengan nada yang hangat.
“Iya pak, rasanya kayak udah enggak ketemu setahun.”
Kemarin, Kia sempat bertemu dengan Pak Tejo dan kembali menangis. Ia teringat kesalahannya dulu yang membuat pak Tejo dipecat oleh papanya. Kia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dirinya tidak akan pernah berbuat hal-hal yang aneh dan membuat Pak Tejo diberhentikan dari pekerjaannya.
“Non mulai kemarin agak beda dari biasanya. Ada apa?” tanya Pak Tejo mencoba membuka pembicaraan.
“Enggak ada apa-apa kok, pak. Kia cuma baru menyadari betapa besar cinta orangtua Kia selama ini, meskipun mereka enggak punya waktu untuk Kia.”
“Begitu, ya sudah non sabar ya, sebentar lagi mama datang kok.” kata Pak Tejo sembari meninggalkankan Kia duduk sendirian.
Kia tersenyum manis ke Pak Tejo. Seharusnya, ia dari dulu harus lebih banyak bersyukur karena telah dikelilingi oleh orang-orang yang peduli kepadanya.
***
Apa yang dinanti oleh Kia akhirnya datang juga. Sebuah mobil Mercedez-Benz masuk ke dalam pekarangan. Kia tahu, ada mamanya di dalam. Begitu berhenti di depan rumah, keluarlah Bu Labdajaya dengan anggunnya. Kia yang melihat mamanya langsung berlari dan memeluknya dengan erat sambil menangis. Bu Labdajaya hampir saja terhuyung jatuh jika tidak berhasil menjaga keseimbangan.
“Sudah sudah, yuk kita masuk dulu, kita ngobrol di dalam.” kata Bu Labdajaya sembari mengelus rambut Kia yang terurai panjang.
Mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang keluarga. Bu Labdajaya dengan sabar berusaha menenangkan Kia yang terus memegangi mamanya sambil menangis. Butuh waktu yang cukup lama hingga Kia mampu bersuara dengan normal.
“Sebenarnya kamu kenapa, nak? Baru kali ini mama lihat kamu seperti ini.” tanya Bu Labdajaya sambil menghapus air mata yang masih mengalir di pipi Kia.
“Kia kangen sama mama, Kia mau minta maaf sama mama karena udah jadi anak yang buruk.” tangis Kia kembali tumpah.
“Kata siapa kamu anak yang buruk? Mama sama papa itu bangga sama kamu. Mungkin papa kalau di depan kamu terlihat tegas dan galak, padahal kalau sedang ngobrol sama teman-temannya, pasti yang dibicarakan itu kamu. Papa kayak gitu itu karena enggak bisa berekspresi aja, apalagi orangnya agak jaim.”
“Kia kemarin malam mimpi buruk, ma. Itu yang bikin Kia kangen sama mama.”
“Memang mimpi apa?”
Maka Kia pun menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir, mulai dari masuk ke dunia cermin hingga kembali lagi ke dunia ini dan menemukan mamanya telah meninggal. Ketika bercerita bagian ini, Kia kembali menangis lagi.
“Mimpimu panjang juga ya, sayang. Pantas kamu sampai khawatir gini.”
“Mama jangan tinggalin Kia lagi, Kia ingin mama ada di rumah.”
“Omong-omong soal itu, sebenarnya mama juga udah lama kepikiran buat pensiun dini. Kemarin juga udah ngobrol sama papa, dan papa setuju. Hanya saja, mungkin mama baru bisa berhenti total dua bulan lagi. Kia mau kan menunggu mama sampai saat itu?”
Kia menganggukkan kepala. Asalkan ia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan orangtuanya, itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak akan merasa kesepian lagi. Tiba-tiba, Kia teringat sesuatu.
“Ma, Kia boleh adopsi adik dari panti asuhan?”
Bu Labdajaya terkejut mendengar perkataan Kia. Ia sama sekali tak menyangka pertanyaan tersebut akan keluar dari anaknya.
“Boleh saja, tapi harus izin papa dulu ya. Selain itu, harus dari panti asuhan yang mama kelola, ya.”
“Mama punya panti asuhan?”
“Bukan punya, cuma mama sering bantu ngurus. Nama panti asuhannya…”
“Harapan Bunda.” potong Kia secara mendadak.
“Kok kamu tahu? Padahal selama ini mama merahasiakannya, loh.”
“Aku tahu aja ma, lupa dari mana.”
“Mama juga punya teman yang sama-sama jadi pengelola. Dia juga punya anak yang satu sekolah sama kamu, nama anaknya siapa ya, laki-laki gitu.”
“Yoga.”
“Iya, kalau enggak salah, kamu kenal?”
“Belum.”
“Belum?”
“Kia belum kenal sama dia, tapi Kia satu kelas kok sama dia.” kata Kia sambil tersenyum manis kepada mamanya. Berkat percakapan ini, ia ingin segera masuk sekolah keesokan harinya.
***
Setelah diantar oleh Pak Tejo seperti biasa, Kia merasa bersemangat ketika melihat pintu depan sekolahnya. Ia tak pernah merasa sesemangat ini ketika datang ke sekolah. Kiia bertekad, untuk memulai kehidupan baru di sekolahnya dan mencari lebih banyak teman, sesulit apapun. Ia bisa memulainya dengan Yoga.
Sebelum memasuki kelas, Kia menarik napas dalam-dalam. Ia mengumpulkan keberanian untuk bisa tampil lebih hangat dan bersemangat. Pengalamannya di dunia cermin menumbuhkan keberanian di dalam dirinya.
“Selamat pagi semua!” kata Kia dengan berusaha seceria mungkin ketika masuk ke dalam kelas. Teman-teman kelasnya pada terkejut ketika melihat Kia yang selama ini selalu murung bisa menyapa mereka dengan penuh energi.
“Pagi, Yoga.” sapa Kia kepada teman sebangkunya itu.
“Eh, pagi Kia. Tumben banget lo sesemangat ini? Baru kali ini lo nyapa gue. Gara-gara sakit kemarin, ya?” tanya Yoga dengan tatapan penuh selidik.
“Enggak kok, lagi seneng aja. Maaf ya, setelah ini aku bakal lebih baik lagi dalam berteman kok!”
Ketika guru telah datang memanggil nama murid satu per satu, Kia berusaha menghafal nama mereka semua. Setidaknya, Kia harus bisa menjalin hubungan baik dengan teman-temannya yang ada di kelas ini. Mungkin, kecuali dengan Melissa dan gerombolannya.
“Yoga, besok ada tugas kelompok sejarah, aku satu kelompok dengan kamu, ya.” kata Kia ketika jam istirahat telah masuk.
“Kok lo tahu besok bakalan ada tugas sejarah?”
“Emmm, feeling aja mungkin? Boleh, ya?”
“Boleh aja sih, tapi biasanya lo sama golongannya Melissa, ya?”
“Iya sih, tapi mereka enggak pernah mau kerja tugas. Aku doang yang kerja.”
“Lagi ngomongin gue, nih?” tiba-tiba Melissa datang ke bangku Kia dan Yoga. Ternyata, dari tadi ia menguping pembicaraan mereka berdua. Anehnya, Kia sama sekali tidak merasa gentar.
“Iya.” kata Kia dengan tersenyum.
“Maksud lo ngomong gitu apaan? Lo merasa kepinteran gitu?”
“Aku enggak mau lagi jadi budak kalian, yang cuma nunggu tugas selesai tanpa pernah mau membantu.”
“Sok banget sih lo, mau gue gampar?”
“Eh Mel, sekali lo berani ngapain-ngapain Kia, gue yang ngadepin lo.” kata Yoga dengan nada tinggi, membuat teman-teman kelas lain ikut menoleh.
Melissa yang terkejut melihat hal ini memutuskan untuk mundur dan pergi keluar kelas. Kia merasa senang karena Yoga membelanya dengan begitu gagah.
“Makasi Yoga.”
“Sama-sama. Gue paling gak suka sama cewek kayak gitu.”
“Tapi Kia tadi berani banget, gue sampai kaget.” Tessa, teman Kia yang duduk di depannya, memberikan apresiasi tinggi kepada Kia.
“Makasi Tessa, aku cuma berusaha membela diri.”
“Tapi enggak nyangka ya Kia yang selama ini terkenal pendiam bisa kayak gitu. Gue salut sama lo.” kali ini Ryan, teman sekelas yang duduk di depan Yoga, yang berbicara.
“Tenang Kia, kita semua pada enggak suka kok sama Melissa karena kesombongannya. Kalau sampai lo kenapa-napa, pasti kita belain.” ujar Tessa lagi.
Kia, yang melihat teman-temannya berbicara dengan dirinya, merasa begitu senang hingga dirinya menitikan air mata. Ternyata, semua masalah yang terjadi selama ini adalah karena dirinya sendiri yang tertutup. Teman-teman kelasnya ternyata baik-baik dan terbuka. Hanya satu perubahan kecil saja, ia telah berhasil mengobrol dengan mereka secara alami. Kia benar-benar bersyukur telah diberikan kesempatan untuk memulai lagi semuanya dari awal.
-

 Permainan5 bulan ago
Permainan5 bulan agoKoleksi Board Game #20: Modern Art
-
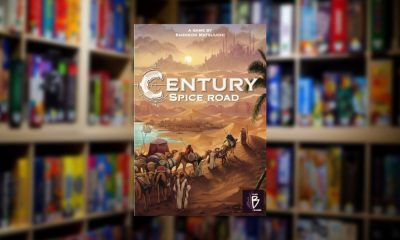
 Permainan5 bulan ago
Permainan5 bulan agoKoleksi Board Game #21: Century: Spice Road
-

 Musik5 bulan ago
Musik5 bulan agoI AM: IVE
-

 Anime & Komik4 bulan ago
Anime & Komik4 bulan agoYu-Gi-Oh!: Komik, Duel Kartu, dan Nostalgianya
-

 Musik5 bulan ago
Musik5 bulan agoTier List Lagu-Lagu Linkin Park Versi Saya
-

 Non-Fiksi5 bulan ago
Non-Fiksi5 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Orang Makan Orang
-
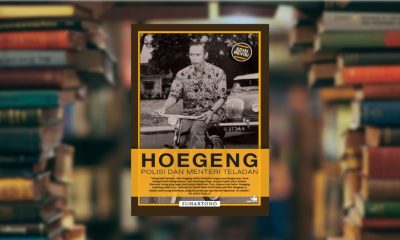
 Non-Fiksi5 bulan ago
Non-Fiksi5 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan
-

 Politik & Negara5 bulan ago
Politik & Negara5 bulan agoPusat Data Nasional kok Bisa-Bisanya Dirasuki Ransomware…

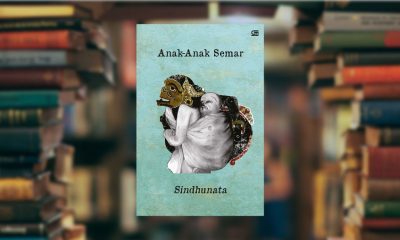

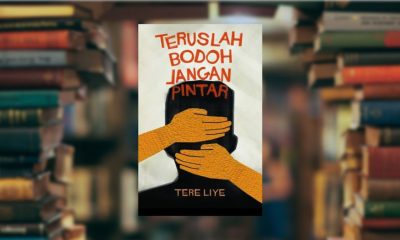







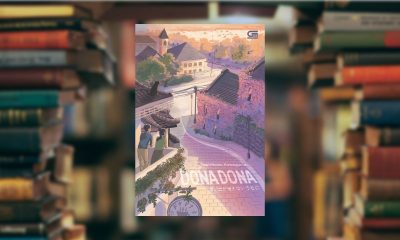









You must be logged in to post a comment Login