Sosial Budaya
Benarkah Era Toko Buku akan Segera Berakhir?

Beberapa waktu lalu, toko buku Gunung Agung yang legendaris resmi tutup. Penulis sendiri hanya pernah sekali berkunjung ke toko yang ada di daerah Kwitang. Tampaknya, memang toko buku yang satu ini harus mengakui kekalahannya melawan zaman.
Merasa penasaran dengan kasus ini, Penulis pun menonton video dari Dr. Indrawan Nugroho yang berjudul “Kiamat Toko Buku”. Secara logika, tentu hal ini masuk akal mengingat kita memang tengah berada di era digital, sehingga keberadaan buku fisik terasa tak relevan lagi.
Pada tulisan kali ini, Penulis ingin membahas mengenai toko buku dan bagaimana zaman makin mendorongnya ke pinggir dari perspektif pribadi, mengingat Penulis adalah orang yang cukup rajin untuk mampir ke toko buku.

Pada Dasarnya, Tingkat Literasi Kita Sudah Rendah

Mungkin para pembaca sudah tahu kalau negara kita tercinta memiliki tingkat literasi yang rendah. Berdasarkan data dari Program for International Student Assessment (PISA) di tahun 2019, Indonesia hanya menempati peringkat 62 dari 70 negara.
Data lain dari UNESCO menunjukan bahwa persentase orang Indonesia yang suka membaca adalah 0,0001% atau 1:1000. Jadi, dari 273 juta penduduk Indonesia, yang gemar membaca sekitar 273 ribu orang saja.
Kalau mau menggunakan logika kasar, dengan rendahnya tingkat literasi, maka tingkat daya beli masyarakat terhadap buku tentu akan ikut rendah. Setidaknya, masih ada sarana yang menyediakan buku gratis seperti perpustakaan.
Jika melihat sekitar, Penulis juga jarang menemukan teman atau kenalan yang juga memiliki hobi membaca, dan lebih jarang lagi yang membeli buku. Maka dari itu, tak heran jika banyak teman yang meminjam ke Penulis jika sedang ingin membaca sesuatu.
Apalagi, kita sudah dibuat tergantung sedemikian besar dengan gawai, sehingga keberadaan buku semakin terasa tidak diperlukan. Ketika buku terasa tidak dibutuhkan, toko buku pun perlahan akan terus ditinggalkan, hingga akhirnya harus menyerah dan tutup.
Apakah Toko Buku Sudah Kehilangan Relevansinya?

Dulu ketika masih kuliah, dalam satu bulan setidaknya Penulis bisa ke toko buku hingga dua kali. Kadang beli, kadang cuma lihat-lihat. Bagi Penulis, toko buku seolah memiliki suasana magis yang membuat kita merasa berada di alam yang berbeda.
Belakangan ini, Penulis semakin jarang ke toko buku karena beberapa alasan. Selain karena merasa bukunya sudah terlalu banyak, Penulis juga sudah tidak membaca sebanyak dulu. Sekarang, paling hanya 15-30 menit per hari, bahkan sering tidak membaca sama sekali.
Apakah ini menjadi semacam pembenaran kalau toko buku memang sudah kehilangan relevansinya? Tentu tidak, karena ini hanya contoh dari satu individu. Penulis yakin toko buku akan tetap ada, terutama yang mampu menyesuaikan diri dengan zaman.
Memang, sekarang kita dimudahkan dengan adanya marketplace atau toko buku online. Namun, bagi Penulis pribadi, keberadaan toko buku fisik rasanya tidak akan tergantikan begitu saja. Mungkin akan ada yang tutup, tapi pasti ada yang berhasil bertahan.
“Kenikmatan” ketika mata memperhatikan buku demi buku, rak demi rak, tak bisa digantikan dengan scroll di marketplace. Apalagi, di toko buku kita bisa membaca sekilas apa isi buku tersebut, sehingga bisa menambah keyakinan untuk membeli suatu buku.
Apa yang Harus Dilakukan oleh Toko Buku agar Bertahan?

Berdasarkan video yang dibuat oleh Dr. Indrawan Nugraha, ada banyak cara yang bisa dilakukan toko buku agar bisa bertahan. Salah satunya adalah menjadikan toko buku bukan sekadar jualan buku, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas.
Jika selama ini toko buku terkesan individual karena orang-orang hanya membeli buku yang diinginkan, maka di masa depan toko buku justru harus terbuka dan menyediakan tempat nongkrong atau berdiskusi. Beberapa toko buku di Indonesia sudah menerapkan hal tersebut.
Bahkan, tak jarang toko buku sekarang menggandeng brand F&B atau bahkan membuka brand mereka sendiri. Jadi, setelah berbelanja buku, pengunjung dapat bersantai menikmati kopi sembari membaca buku yang baru saja dibeli.
Selain itu, sekarang rasanya jarang toko buku hanya menjual buku. Gramedia misalnya, terkenal karena juga menjual alat tulis, alat olahraga, pernak-pernik, dekorasi, mainan, dan lain sebagainya. Ini bisa menarik pengunjung yang tidak suka buku.
Tentu masih ada cara lain yang telah atau akan dilakukan oleh toko buku. Dengan jatuhnya Gunung Agung bukan berarti toko buku yang lain akan mengikuti jejaknya. Pada akhirnya, semua dituntut untuk sekreatif mungkin agar bisa bertahan di era modern ini.
Lawang, 26 Juni 2023, terinspirasi setelah menonton video Dr. Indrawan Nurgroho yang membahas mengenai kiamat toko buku
Foto Featured Image: Abby Chung
Sumber Artikel:
Sosial Budaya
Ketika Kebenaran Relatif Dianggap Sebagai Kebenaran Absolut

Sebagai orang yang bekerja secara remote, salah satu keistimewaan yang Penulis rasakan adalah bisa bekerja di mana saja. Nah, kalau sedang bosan bekerja dari rumah, biasanya Penulis memilih untuk bekerja di kafe, entah itu sendirian ataupun bersama teman.
Nah, salah satu teman Penulis yang sering work from cafe (WFC) bersama adalah Dio, teman sejak semester satu kuliah yang sekarang menjadi dosen Binus Malang. Kami berdua sering bertukar pikiran di sela-sela menyelesaikan pekerjaan masing-masing.
Belum lama ini, kami berdua WFC di salah satu kafe Malang yang sudah menjadi langganan. Pada saat itu, Dio share bahwa dirinya baru menonton video dari Rumah Editor di YouTube tentang seorang matematikawan bernama Kurt Gödel.

Gödel terkenal karena berusaha membuktikan keberadaan Tuhan dengan menggunakan logika dan matematika. Namun, bukan pembahasan mengenai keberadaan Tuhan yang akan menjadi inti tulisan kali ini.
Yang ingin Penulis bahas adalah topik lain tentang Necessary Truth vs. Contingent Truth, yang juga dibahas dalam video tersebut. Jika penasaran, pembaca bisa menonton video selengkapnya melalui tautan berikut ini.
Kebenaran Absolut vs Kebenaran Relatif

Secara sederhana (oversimplified), Necessary Truth adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak mungkin salah. Contoh mudahnya adalah perhitungan 1 + 1 pasti 2, mau di multiverse mana pun pasti jawabannya 2.
Contoh lain, semua segitiga pasti memiliki tiga sisi. Tidak mungkin sebuah segitiga memiliki empat sisi, karena namanya akan berubah menjadi segiempat. Nah, keberadaan Tuhan menurut Gödel juga termasuk Neccesarry Truth.
Di sisi lain, Contingent Truth adalah kebenaran yang bisa saja berubah. Contoh, untuk saat ini ibu kota Indonesia masih Jakarta. Akan tetapi, bisa saja tahun 2029 nanti akan diresmikan kalau ibu kota Indonesia adalah IKN. Siapa yang tahu, kan?
Contoh lain, kita menganggap kalau tokoh A adalah orang jahat karena kita mengetahui rekam jejaknya di masa llau. Namun, bisa saja besok dia tobat dan benar-benar berubah menjadi lebih baik.
Nah, di tulisan ini, Penulis akan menerjemahkan secara bebas Necessary Truth menjadi Kebenaran Absolut dan Contingent Truth menjadi Kebenaran Relatif untuk memudahkan penulisan. Penulis hanya meminjam istilah di atas untuk membahas topik yang kemarin Penulis singgung: polarisasi.
Alasan Mengapa Kita Mudah Diadu Domba

They’ll conquer us if we divide
Mereka akan menaklukkan kita kalau kita terpecah belah
Delusion:All by ONE OKE ROCK
Ketika kita masih di bangku sekolah, tentu kita familier dengan istilah devide at impera atau yang sering disebut juga sebagai politik adu domba. Intinya adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa dibuat justru saling memusuhi satu sama lain, bukannya bersatu.
Seperti penggalan lirik lagu “Delusion:All” dari ONE OK ROCK di atas, ketika kita terpecah belah, maka “mereka” akan dengan mudah menakhlukkan kita. Musuh tahu, kita akan sulit untuk dikalahkan apabila bersatu.
Meskipun kita sudah merdeka selama 80 tahun, rasanya strategi politik zaman kolonial ini masih terasa hingga sekarang. Bukan oleh bangsa Belanda maupun bangsa lain, tapi oleh bangsa kita sendiri dan membuat kita terpolarisasi dengan mudahnya.
Contoh yang masih hangat tentu saja polemik Brave Pink Green Hero yang diributkan oleh netizen. Bukannya mempersatukan, simbol tersebut justru semakin memperparah polarisasi masyarakat yang semakin parah selama 10 tahun terakhir ini.
Nah, menurut Penuis, salah satu alasan mengapa kita begitu mudah terpolarisasi yang berujung mudah diadu domba adalah karena kita menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut.

Contohnya begini. Anggaplah Pihak A menganggap kinerja Presiden Prabowo Subianto sangat buruk dan banyak catatan negatif tentangnya. Ditambah dengan algoritma media sosial yang cenderung hanya menampilkan apa yang kita suka, kita semakin menganggap hal tersebut sebagai Kebenaran Absolut.
Karena menganggap apa yang ia yakini sebagai Kebenaran Absolut, maka ia tidak peduli jika ada data yang membantah kalau kinerja Prabowo 100% buruk. Mau ada data penangkapan para koruptor, mau ada data terbongkarnya kasus oplosan, Prabowo tetap jelek.
Sebaliknya juga begitu, ada Pihak B yang menganggap kalau presiden pilihannya 100% baik, tidak mungkin salah. Mau dikasih bukti beberapa hal buruk tentangnya pun, Prabowo tetap yang terbaik, titik.
Mau Prabowo memilih wakil presiden yang mengacak-acak konstitusi, mau Prabowo mengeluarkan pernyataan yang tone deaf, mau Prabowo mengeluarkan kebijakan yang dirasa banyak ahli kurang tepat, Prabowo tetap baik. Keyakinannya telah berubah menjadi Kebenaran Absolut.
Padahal, Prabowo itu baik maupun Prabowo itu buruk sama-sama merupakan Kebenaran Relatif. Prabowo bisa baik dan buruk secara bersamaan, mong namanya juga manusia, bukan nabi. Kebenaran tentang Prabowo bisa berubah, tergantung konteksnya.
Namun, kebencian dan fanatisme berlebih memang bisa membutakan manusia. Kalau sudah benci, benci sekali. Kalau sudah suka, suka sekali. Alhasil, kita pun jadi mudah terpolarisasi dan sering berdebat tak penting di media sosial tanpa ada yang mau merasa kalah.
***
Kalau kita sudah bersikeras menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut, ya susah. Semua yang bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran dianggap salah. Alhasil, diskusi yang sehat pun mustahil tercipta karena kita jadi menutup persepsi lain.
Manusia memang cenderung hanya ingin melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar. Jika terus begini, maka kita akan terus mudah terpolarisasi dan diadu domba. Pertanyaannya, mau sampai kapan seperti ini?
Lawang, 10 September 2025, terinspirasi setelah teringat dengan pembicaraan bersama seorang teman tentang teori yang dikemukakan oleh Kurt Gödel
Sumber Featured Image: Andrea Piacquadio
Sosial Budaya
Polemik Brave Pink Hero Green: Mengapa Kita Mudah Terpolarisasi

Salah satu “buah” yang dihasilkan dari panasnya akhir bulan Agustus hingga awal September adalah munculnya gerakan 17+8, yang intinya adalah tuntutan-tuntutan untuk Presiden, DPR, Kepolisian, dan pihak-pihak lainnya.
Sebanyak 17 tuntutan diberi deadline hingga tanggal 5 September kemarin, yang tentu saja pada akhirnya mayoritas yang belum dipenuhi. 8 sisanya diberi deadline satu tahun atau “dikumpulkan” pada bulan September 2026.
Gerakan tersebut diprakarsai oleh banyak tokoh anak muda seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, Andhyta ‘Afu’ Utami, Salsa Erwina, dan Abigail Limuria. Isi tuntutannya pun macam-macam, yang intinya merangkum apa yang selama ini menjadi keresahan masyrakat.
Bersamaan dengan adanya tuntutan tersebut, muncul gerakan Brave Pink Green Hero sebagai bentuk dukungan dan solidaritas atas tuntutan tersebut. Banyak netizen berlomba-lomba untuk ikut mengubah foto profilnya menjadi duo-tone kombinasi kedua warna tersebut, termasuk Penulis.
Munculnya Gerakan Brave Pink Green Hero

Brave Pink dipilih karena keberanian yang ditunjukkan oleh Ibu Ana, yang sempat terpotret berani menghadapi barisan kepolisian sendirian hanya dengan membawa bendera. Sementara itu, Green Hero dipilih untuk mengenang almarhum Affan Kurniawan.
Masalahnya, pemilihan warna tersebut ternyata justru diributkan oleh netizen. Pasalnya, beredar video Ibu Ana yang berteriak secara kasar “Prabowo Anjing, Prabowo Turun, Ganti Anies,” yang diteriakkan di tengah-tengah aksi.
Gara-gara hal tersebut, banyak yang menolak untuk ikut mengganti foto profilnya. Ada yang karena tidak ingin orang bermulut kasar menjadi simbol, ada yang menilai pemilihan warna tersebut bersifat politis, dan lain sebagainya.
Yang membela Ibu Ana pun tak sedikit. Ada yang bilang pemilihan warna pink tersebut karena keberanian yang ditunjukkan Ibu Ana, bukan mewakili pendapat pribadinya. Ada yang bilang pemilihan warna tersebut melambangkan woman empowerment secara keseluruhan.
Penulis menemukan analogi yang menarik di X, di mana ada yang mengomparasi Brave Pink ini dengan slogan “Just Do It” dari Nike dan V Sign sebagai tanda damai. Inspirasi dari keduanya juga berasal dari hal yang tidak 100% baik, bahkan cenderung kontroversi.
Selain itu, ada yang membuat analisis kalau video yang beredar tersebut sebenarnya buatan AI. Banyak kejanggalan yang ditemukan pada foto tersebut, yang sering menjadi ciri video buatan AI. Penulis tidak akan mendebat hal tersebut, karena tidak punya kapabilitas juga untuk menilai.
Terlepas dari pro kontra pemilihan Brave Pink Green Hero ini, Penulis justru merasa ini menjadi bukti lain betapa kita mudah terpolarisasi, yang ujungnya membuat kita mudah diadu domba dan melupakan hal yang substansial.
Mengapa Kita Mudah Terpolarisasi dan Melupakan Hal yang Substansi?

Secara umum, orang mengganti foto profilnya dengan duo-tone tersebut adalah bentuk dukungan dan solidaritas terhadap gerakan 17+8, yang bisa dianggap sebagai aksi nyata dari kita sebagai masyarakat kepada para pemangku kekuasaan yang mengatur negara ini.
Akan tetapi, sebenarnya yang mendukung 17+8 tapi menolak mengganti foto profil juga ada. Yang cuma FOMO ikut mengganti foto padahal tidak mendukung 17+8 juga ada. Yang tidak mendukung 17+8 dan tidak FOMO pun juga ada.
Menariknya, Anies Baswedan yang namanya terseret karena disebut Ibu Ana pun tidak ikut-ikutan mengganti foto profilnya. Mantan capres lainnya, Ganjar Pranowo, juga mengambil langkah yang sama. Tampaknya mereka tidak ingin disangkutpautkan dengan isu ini.
Sebenarnya silakan saja mau memilih yang mana, toh itu hak masing-masing individu. Yang membuat Penulis geram adalah ketika ada pihak yang merasa lebih baik dari pihak lain karena pilihannya. Mereka menyalahkan pihak yang berseberangan dengan berbagai alasan.
Kalau memang tidak srek dengan pemilihan Brave Pink karena sosok Ibu Ana, ya enggak perlu ikut ganti foto profil. Masalahnya, ada saja pihak-pihak ini yang menggiring opini kalau orang-orang yang mengganti foto profilnya adalah A B C D blablabla.
Yang memilih untuk mengganti foto profil juga begitu. Jangan mentang-mentang ganti foto profil, terus jadi merasa yang paling nasionalis dan menghakimi yang tidak melakukannya. Jangan-jangan yang ganti foto profil tidak pernah ikut aksi secara langsung, cuma koar-koar di media sosial (seperti Penulis misalnya).
Salah satu alasan utama mengapa kita begitu mudah terpolarisasi adalah karena terkadang kita menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut. Penulis akan menjabarkan hal ini lebih detail di tulisan besok.
Lebih parahnya lagi, polarisasi yang terjadi ini justru membuat kita melupakan substansinya, yakni tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Harusnya kita sebagai sesama rakyat harus bekerja sama untuk memantau agar tuntutan yang telah diajukan telah terlaksana.
Terserah mau pakai warna pink, hijau, biru, cokelat, merah, nggak pakai warna karena buta warna, bebas. Yang penting, di momen-momen penting seperti saat ini kita harus saling jaga agar suara kita didengar oleh mereka.
***
Jujur, Penulis geram karena ada saja yang meributkan Brave Pink Green Hero ini. Kenapa justru menyorot Ibu Ana-nya, bukan inti dari gerakannya. Ibarat meributkan klub sepak bola bukan karena performa atau permainannya, tapi dari logo klubnya.
Selain itu, Penulis juga merasa heran karena ketika pemimpin negara yang berkata kasar, hal tersebut justru berusaha dinormalisasi. Ketika pemimpin negara mengacak-acak konstitusi agar bisa ikut pemilu, eh malah dipilih. Double standard-nya kok agak kebangetan.
Terlepas dari itu semua, Penulis berharap kejadian yang berlangsung sejak akhir Agustus bisa menjadi momentum kita sebagai bangsa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kita lihat saja tahun depan, apakah tuntutan yang ada di dalam 17+8 ada yang berhasil dikerjakan atau tidak.
Lawang, 9 September 2025, terinspirasi dari netizen yang meributkan masalah brave pink hero green
Foto Featured Image: Tribun
Sosial Budaya
Beda Artis Korea Selatan dan Indonesia Ketika Pemilu

Beberapa waktu lalu, ada fenomena yang menarik perhatian Penulis dari dunia per-K-Pop-an. Karina, salah satu member dari aespo aespa mengunggah sebuah foto di Instagram di mana dia berpose peace.
Sebagaimana simbol peace pada umumnya, tentu Karina membentuk tanda V dengan kedua jarinya. Masalahnya, banyak yang menganggap kalau pos tersebut merupakan bentuk dukungan Karina terhadap salah satu calon presiden di Korea Selatan, yang memang sedang menjalani masa pemilu setelah presidennya dimakzulkan akhir tahun lalu.
Hal ini makin diperparah karena Karina menggunakan jaket dengan tulisan angka 2 dan berwarna merah, warna yang identik dengan partai pengusung calon kandidat nomor 2. Netizen pun langsung heboh dengan pos tersebut.
Tak lama setelah itu, Karina menghapus pos tersebut dan merilis permintaan maaf. SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Karina juga merilis klarifikasi. Sejak itu, banyak sekali public figure di Korea yang berhati-hati dalam menunjukkan gestur angka.
Salah satu yang sempat Penulis lihat adalah Hearts2Hearts, yang merupakan adik dari aespo aespa. Dalam salah satu live-nya, beberapa member-nya tanpa sengaja menunjukkan gestur angka yang langsung menimbulkan kepanikan dan segera meralat gesturnya.
Lantas, apakah memang ada aturan public figure yang memiliki basis penggemar besar dilarang menunjukkan dukungan politiknya? Sebenarnya tidak ada peraturan resmi yang melarang, hanya saja hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Istilahnya, “No Color, No Gesture“.
Kok, yang jelas-jelas mendukung. Yang dianggap “tersirat” seperti Karina saja langsung mendapatkan kecaman dari masyarakat Korea Selatan. Bahkan, sampai ada yang mengatakan “mereka sudah tamat.” Mungkin ini yang komentar memang hater-nya aespo aespa saja.
Membandingkan Fenomena Ini dengan Negara Sendiri
Nah, melihat fenomena seperti ini, tentu Penulis jadi membandingkan dengan negaranya sendiri. Kalau di sini, mengapa para artis justru menjadi daya tarik utama untuk mendulang suara? Para artis bisa dengan bebas menunjukkan dukungannya kepada salah satu calon.
Menariknya, para artis pendukung ini bisa mendapatkan posisi-posisi di pemerintahan apabila calon yang didukung berhasil menang. Bayangkan saja Karina tiba-tiba menjadi staf khusus Presiden Korea Selatan. Sulit dibayangkan, bukan? Itulah bedanya.
Ada dua perspektif berbeda yang bisa dikulik dari sini. Pertama, masyarakat Korea Selatan memiliki standar tinggi dalam hal netralitas dan menghindari polarisasi. Siapa yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok politik tertentu lebih baik diam.
Seperti yang sudah Penulis singgung di atas, public figure di Korea Selatan (terlebih idol K-Pop) memiliki basis penggemar yang sangat besar. Jika mereka sudah menunjukkan dukungan kepada salah satu calon, besar kemungkinan penggemar akan ikut pilihan mereka.
Jika hal tersebut benar-benar terjadi, akibatnya adalah pemilihan berdasarkan apa kata idola mereka, bukan karena murni pilihan pribadi atau preferensi politik mereka. Yang terpilih pun bisa dibilang karena populer, bukan visi misi yang dimiliki (salah satu penyakit tulen demokrasi).
Dari perspektif lain, masyarakat Korea Selatan saja yang terlalu kaku dan tidak menerapkan demokrasi secara utuh. Toh, di negara yang katanya paling demokrasi (baca: Amerika Serikat), para artisnya juga gencar mengampanyekan jagoannya secara blak-blakan.
Artis atau public figure juga memiliki hak suara dan punya hak untuk ikut mengampanyekan calon yang mereka dukung, apa pun alasannya. Bisa karena satu ideologi, bisa karena dibayar. Yang jelas, mereka siap dicap netizen sebagai buzzer.
Lantas, bagaimana dengan penggemar mereka yang memilih karena pilihan para public figure ini? Ya, salah mereka sendiri, kenapa tidak punya pendirian. Mereka harusnya menyadari bahwa sosok idola dan pilihan politik seharusnya dipisahkan.
Kalau yang ekstrem, mungkin mereka akan berhenti mengidolakan seseorang apabila pilihan politiknya berbeda. Dari yang dulu memuja-muja dan like semua pos di media sosial, berbalik menjadi penghujat nomor satu.
Terlepas dari kedua perspektif di atas, ini adalah kali kedua Penulis secara pribadi membandingkan artis Korea Selatan dan Indonesia. Sebelumnya, Penulis sering membandingkan perbedaan gaya hidup mereka, tapi rasanya itu bisa dibahas di tulisan lain.
***
Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Apakah Korea Selatan yang kaku atau Indonesia yang selow? Menurut Penulis, tidak ada yang salah atau benar. Toh, masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda, sehingga masing-masing tahu mana yang terbaik untuknya.
Mungkin artis Korea Selatan memang harus ekstra hati-hati karena masyarakatnya cukup sensitif dengan masalah politik. Bayangkan saja, Rei dari IVE saja sampai takut ketika disuruh melakukan aegyo dengan menunjuk pipinya menggunakan telunjuk. Padahal ia dari Jepang, yang artinya tidak punya hak pilih.
Sebaliknya, masyarakat Indonesia tampaknya cukup selow ketika melihat para artisnya menjadi tim kampanye calon presiden tertentu. Tentu ada saling hujat di sana-sini, tapi rasanya tidak seekstrem masyarakat Korea Selatan. Paling dicap buzzer aja, apalagi yang sampai dapat jabatan di pemerintahan terpilih.
Lawang, 8 Juni 2025, terinspirasi setelah melihat bagaimana takutnya para idol K-Pop menunjukkan gestur angka ketika masa jelang pemilu presiden Korea Selatan
Sumber Artikel:
-
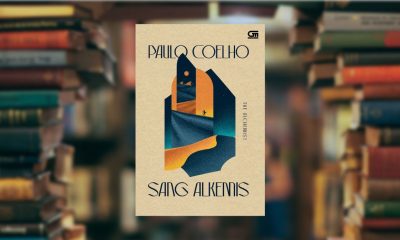
 Fiksi11 bulan ago
Fiksi11 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Sang Alkemis
-

 Permainan11 bulan ago
Permainan11 bulan agoKoleksi Board Game #29: Blokus Shuffle: UNO Edition
-

 Olahraga12 bulan ago
Olahraga12 bulan agoSaya Memutuskan Puasa Nonton MU di Bulan Puasa
-

 Olahraga12 bulan ago
Olahraga12 bulan agoTergelincirnya Para Rookie F1 di Balapan Debut Mereka
-

 Musik9 bulan ago
Musik9 bulan agoMari Kita Bicarakan Carmen dan Hearts2Hearts
-

 Politik & Negara12 bulan ago
Politik & Negara12 bulan agoMau Sampai Kapan Kita Dibuat Pusing oleh Negara?
-

 Politik & Negara9 bulan ago
Politik & Negara9 bulan agoPemerintah Selalu Benar, yang Salah Selalu Rakyat
-

 Pengalaman9 bulan ago
Pengalaman9 bulan agoKetika Hobi Menulis Blog Justru Terasa Menjadi Beban





















You must be logged in to post a comment Login