Sosial Budaya
Dilema (Media) Sosial Kita

Pada beberapa kesempatan, Penulis kerap menuliskan keresahannya tentang betapa adiktifnya media sosial sekarang. Semua platform seolah berlomba-lomba untuk menjadi yang paling lama digunakan.
Beberapa jam tak terasa bergulir begitu saja ketika jari kita asyik melakukan scrolling tanpa batas. Ada saja hal baru dan menarik yang bisa kita lihat.
Bermain media sosial tidak ada salahnya. Selain menjadi sumber inspirasi, media sosial juga membuat kita bisa terkoneksi dengan teman maupun keluarga kita.
Media sosial menjadi salah jika sudah berubah menjadi candu yang membuat kita tidak tahu harus melakukan apa ketika ponsel tidak sedang berada di jangkauan kita.
Hipnotis Media Sosial

Seolah Menghipnotis (The Verge)
Ketika menulis artikel Untuk Apa Belajar Sejarah, Penulis jadi memiliki pemikiran kalau salah satu alasan mengapa mayoritas generasi sekarang cenderung apatis dan kurang kritis adalah karena kurang banyak membaca sejarah.
Penulis pun mendiskusikannya dengan seorang kawan (sebut saja Pentol). Ia memiliki pendapat lain. Menurutnya, itu lebih dikarenakan dampak media sosial.
Jika kita perhatikan, sekarang ada banyak sekali hal sepele yang bisa menjadi trending dan viral dengan begitu cepatnya. Kita seolah mudah untuk terbawa apa yang sedang ramai dibicarakan.
Menurutnya lagi, kita ini seolah sedang dihipnotis dan jadi mudah digiring oleh sesuatu. Apa yang dulu tidak kita sukai, bisa jadi kita sukai sekarang.
Contoh mudahnya adalah aplikasi TikTok. Dulu aplikasi ini dihujat dan dianggap sebagai aplikasi goblok. Sekarang? Hampir semua orang mengunduhnya bahkan membuat konten di dalamnya.
Terdengar seperti teori konspirasi? Bisa jadi. Tapi fenomena ini ada dan kita patut waspada.
Algoritma Candu
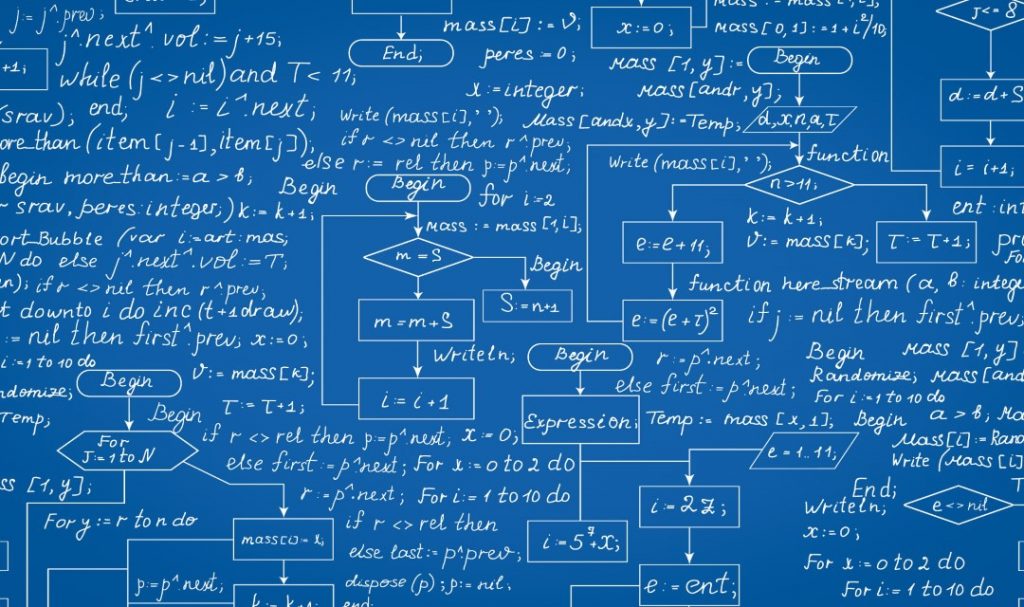
Algoritma Candu (Evatronix)
Kenapa semua platform seolah tahu apa yang kita sukai berdasarkan apa yang kita like? Karena mereka memiliki algoritma yang dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama di depan layar.
Tidak hanya dari rekomendasi yang muncul dari beranda, algoritma ini bisa memunculkan push notification yang membuat kita akan tertarik untuk mengecek ponsel pintar kita.
Algoritma ini dapat mempelajari behaviour dan kebiasaan kita dalam menggunakan media sosial untuk memberikan rekomendasi terbaik untuk kita. Hasilnya? Terdapat gudang data yang bisa saja disalahgunakan.
Tidak percaya? Tengok saja skandal Cambridge Analytica yang menyeret Facebook ke ranah hukum. Mereka dianggap terlibat penjualan data demi pemenangan Donald Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat.
Teori kami berdua ini terbukti ketika Penulis menonton sebuah film dokumenter yang berjudul The Social Dilemma. Di sana, ada banyak kesaksian dari orang-orang yang terlibat dalam pembuatan media sosial yang khawatir akan ciptaannya sendiri.
Kita Ini Produk

Kita Ini Dijual! (Priscilla Du Preez)
Ketika menggunakan layanan-layanan seperti Google, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ataupun YouTube, apakah kita mengeluarkan uang untuk menggunakannya? Tentu tidak.
Jika kita tidak mengeluarkan uang untuk suatu produk, artinya kitalah produknya!
Kenyataan yang cukup mengerikan ini Penulis ketahui setelah menonton The Social Dilemma. Secara tidak sadar, kita telah dijadikan komoditas oleh layanan-layanan yang kita gunakan setiap hari.
Bagaimana caranya? Penulis telah menyinggung bahwa ada penjualan data kita ke pihak ketiga. Dijual ke siapa? Ke pihak pengiklan yang ingin memasarkan produknya.
Kenapa membutuhkan data kita? Yang namanya pengiklan tentu ingin audience yang tepat sasaran. Melalui algoritma yang dimiliki, layanan-layanan tersebut bisa tahu siapa yang cocok untuk melihat iklan tertentu.
Apakah hal tersebut tidak melanggar privasi? Tidak, semua tercantum di Terms & Condition yang biasanya kita abaikan begitu saja. Kita telah menyetujui kalau aktivitas kita akan direkam demi kebutuhan mereka.
Kita sudah masuk ke dalam bagian dari model bisnis raksasa ini. Semakin lama kita menggunakan media sosial, semakin banyak uang yang akan mengalir ke korporat-korporat besar tersebut.
Mungkin kita tidak terlalu peduli jika dijadikan sebagai produk karena merasa tidak dirugikan apa-apa. Hanya saja, ada permasalahan yang jauh lebih berbahaya, di mana generasi muda yang menjadi sasarannya.
Generasi Rapuh

Generasi Rapuh (PNGio.com)
Dari buku Strawberry Generation karya Rhenald Khasali, generasi muda sekarang adalah generasi yang penuh gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati.
Di film The Social Dilemma, Generasi Z (lahir di atas tahun 1996) dianggap sebagai generasi yang lebih mudah cemas, rapuh, dan tertekan. Bisa dilihat ada persamaan pendapat, generasi sekarang adalah generasi yang rapuh.
Apa penyebabnya? Salah satunya adalah karena kehadiran media sosial. Penulis mungkin baru aktif menggunakan media sosial ketika kuliah. Mereka? Rata-rata mulai SMP, bahkan ada yang SD.
Apa yang mereka lakukan sepulang sekolah? Istirahat sambil cek media sosial. Apa yang mereka lakukan sebelum tidur? Main media sosial. Apa yang mereka cek pertama kali ketika bangun? Media sosial.
Rutinitas ini membuat menjadi bukti kalau media sosial sudah menjadi candu untuk mereka. Algoritma yang dirancang oleh layanan-layanan tersebut ternyata berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.
Penulis melihat fenomena ini secara langsung karena dekat dengan adik-adik Karang Tarunanya. Jika ditanya apa yang mereka akan lakukan tanpa ponsel pintarnya, mereka akan kebingungan menjawabnya.
Tak jarang media sosial membuat mereka menjadi mager dan melalaikan aktivitas lainnya. Tak jarang yang menjadikan media sosial sebagai pelampiasan atas apa yang terjadi dalam kehidupan nyatanya.
Jika mau percaya teori konspirasi, ada sebuah grand system yang ingin menjadikan generasi muda sebagai generasi yang apatis, egosentris, dan kurang kritis agar mereka mudah dikendalikan sesuai keinginan pihak tertentu.
Jika mereka telah mudah dikendalikan, maka bisa terjadi sesuatu yang tak kalah seram.
Polarisasi Masyarakat

Berpotensi Konflik (AP News)
Penelitian menunjukkan semenjak media sosial menjamur dan diminati oleh hampir semua orang, polarisasi masyarakat meningkat pesat. Contohnya adalah pemilihan presiden 2019 kemarin, bisa dilihat dua kubu saling adu mulut dan jari, bahkan secara kurang sehat.
Dengan menggunakan algortima candu yang dimiliki, kita akan terus melihat apa yang kita sukai. Jika kita menjadi pendukung Semar, maka berita maupun feed yang muncul akan terus berputar di sekitar Semar.
Tak jarang pula kita akan melihat feed yang mengolok-olok lawan dari Semar, sebut saja Togog. Akhirnya, kita akan menjadi fanatik ke Semar dan menjadi haters-nya Togog.
Contoh lain terkait Corona. Ada polarisasi di sini, antara yang percaya dan yang tidak. Mereka saling merasa paling benar dan menertawakan kubu lain.
Di dalam film The Social Dilemma, salah satu narasumber mengatakan bahwa kekhawatirannya terbesar dari adanya algoritma ini adalah civil war. Perang saudara.
Dramatisasi? Bisa jadi, tapi kemungkinan itu ada. Lihat saja bagaimana seringnya netizen yang beda kubu beradu argumen yang kurang bermanfaat. Bukan tidak mungkin pertikaian tersebut berujung kekerasan.
Penutup
Penulis bukan ingin merasa sok suci seolah tak kecanduan media sosial. Penulis pun masih sering seperti itu. Sudah sering Penulis menceritakan bagaimana dirinya merasa kecanduan ponsel hingga akhirnya memutuskan untuk detox media sosial.
Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecanduan ini. Yang ekstrem, hapus aplikasi. Yang lebih ringan, batasi penggunaan, matikan notifikasi dan sistem rekomendasi, jauhkan ponsel pintar ketika hendak tidur maupun akan melakukan aktivitas lain.
Kalau enggak main media sosial, terus kita ngapain? Memang harus ada aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian kita, entah baca buku, kumpul dengan teman, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya.
Kita harus menyadari kalau media sosial hanyalah alat yang membantu kita untuk terhubung dengan orang lain, menampilkan karya kita, ataupun mendapatkan informasi.
Jangan sampai terbalik, kita yang digunakan oleh media sosial sebagai sapi perah di dalam sistem bisnis raksasa mereka.
Lawang, 25 September 2020, terinspirasi setelah berdiskusi dengan seorang kawan dan menonton The Social Dillema
Foto: camilo jimenez on Unsplash
Sumber Artikel: The Social Dilemma, Mojok 1, Mojok 2
Sosial Budaya
Apakah Mesin Pencari akan Tergantikan oleh Media Sosial?

Ada hal menarik ketika Penulis berinteraksi dengan para Gen Z di sekitar Penulis. Kebetulan, sewaktu mengisi webinar yang diadakan minggu kemarin, pertanyaan yang menjadi judul artikel ini juga sempat ditanyakan ke Penulis.
Penulis sebagai generasi Milenial terbiasa menggunakan Google dalam mencari informasi apapun, bahkan hingga muncul istilah Mbah Google dan term googling. Alasannya jelas, Google menyediakan hampir semua informasi yang kita butuhkan.
Namun, bagi Gen Z, ternyata pamor Google sebagai mesin pencari mulai pudar dan dikalahkan oleh media sosial seperti TikTok. Fenomena ini pun menimbulkan satu pertanyaan: apakah mesin pencari akan tergantikan oleh media sosial?

Beda Mencari di Mesin Pencari dan Media Sosial
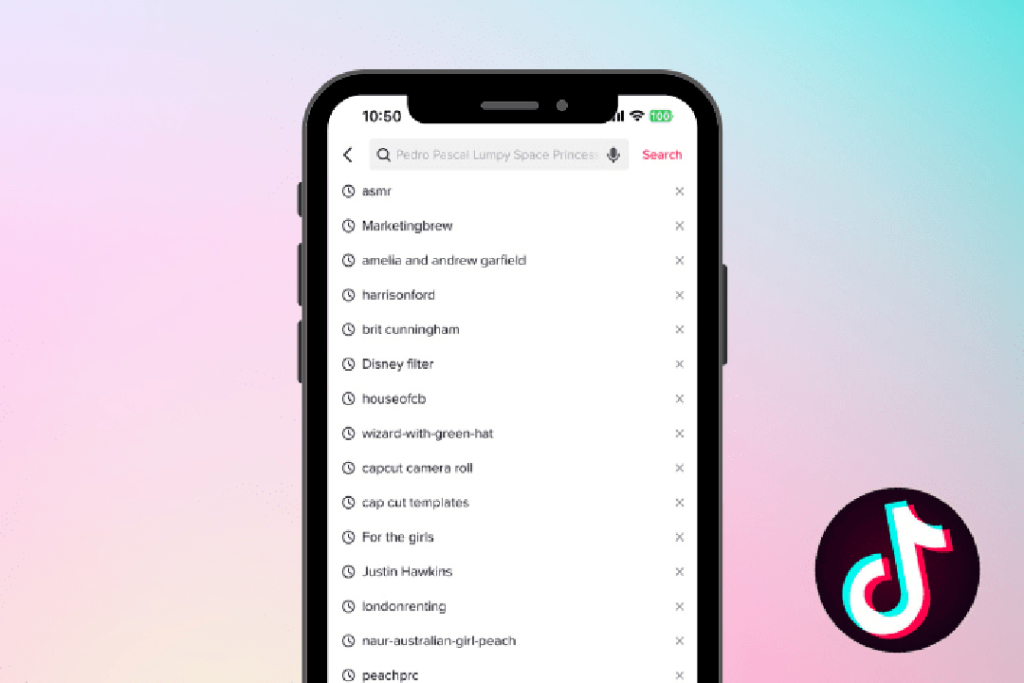
Disrupsi adalah hal yang biasa di dunia ini. Hampir tidak ada benda yang benar-bentar tak tergantikan. Selalu ada terobosan dan inovasi baru yang lebih efektif dan efisien, sehingga orang pun jadi beralih dan meninggalkan yang lama dan kuno.
Jauh sebelum Google muncul, mungkin orang mengandalkan buku, toko buku, atau perpustakaan untuk mencari informasi. Nah, kini Google (dan mesin pencari lainnya seperti Bing) pun menghadapi ancaman yang sama.
Misal Penulis dan circle-nya ingin mencari rekomendasi kafe di Malang. Kalau Penulis akan mencari artikelnya di Google. Namun, teman Penulis yang Gen Z lebih memilih TikTok karena ditampilkan dalam bentuk audiovisual yang lebih menarik.
Tentu artikel dan konten video memiliki plus minusnya masing-masing. Google misalnya, bisa menjelaskan secara detail rekomendasi kafe yang diberikan lengkap beserta map-nya. Apalagi, ada banyak artikel yang akan disajikan oleh Google, sehingga kita akan mendapat banyak variasi.
Media sosial pun bisa memberikan informasi secara langsung yang dilengkapi dengan ulasan dari kreator kontennya. Dalam waktu sekian detik, kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa rekomendasi tempat yang diberikan kepada kita.
Penulis sendiri sejujurnya tidak nyaman menggunakan media sosial sebagai pengganti Google, terutama TikTok. Alasannya, kadang informasi yang diberikan ngaco sehingga menimbulkan trust issue.
Contoh, Penulis pernah dikirimi sebuah video TikTok yang memberi info kalau di Surabaya sedang ada pameran buku. Di video tersebut, promo dan buku yang ada terlihat banyak dan menarik. Namun, setelah ke sana, ternyata zonk dan mengecewakan.
Lantas, Apakah Mesin Pencari Memang akan Tergantikan oleh Media Sosial?

Tren memang bergeser di mana media sosial pun kerap digunakan sebagai sumber informasi. Namun, selama mesin pencari dan media sosial menyediakan hasil dengan format dan akurasi yang berbeda, rasanya media sosial terutama Google tidak akan tergeser semudah itu.
Sebagai orang yang bekerja di bidang Search Engine Optimization (SEO), Penulis melihat masih ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan di mesin pencari (atau lebih tepatnya artikel website) yang belum bisa dilakukan oleh media sosial.
Contohnya, artikel bisa memberikan info yang lebih lengkap dan detail. Artikel juga memberikan kendali kepada pembacanya untuk memilih poin-poin mana saja yang ingin dibaca, berbeda dengan konten video yang kendalinya ada di konten kreatornya.
Lalu, sumber di artikel lebih bisa dipercaya dibandingkan media sosial. Seperti yang kita tahu, di media sosial kerap menjadi ladang hoaks yang tak terkontrol. Memang artikel tak sepenuhnya bebas dari hoaks, tapi jelas kredibilitasnya lebih terjamin dari media sosial.
Selain itu, jumlah pencarian (atau search volume) di Google juga masih cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari Google Trends. Contoh ketika Genshin Impact merilis update terbaru, maka banyak hal-hal seputar update tersebut akan muncul di Trending.
Hal tersebut membuktikan kalau masih banyak orang yang mengandalkan mesin pencari untuk mendapatkan informasi. Memang di media sosial banyak guide atau build karakter tertentu, tapi rasanya artikel yang mampu memberikan panduan paling detail.
Keberadaan AI juga menjadi penting karena mampu merangkumkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu cepat. Misal kita ingin tahu berapa tinggi Erling Haaland, maka Google akan langsung memberi jawabannya sehingga kita tak perlu membuka artikel tertentu.
Selain itu, AI Google akan tetap menyarankan artikel-artikel tertentu jika pengguna membutuhkan info yang lebih lengkap. Jadi, meskipun ada AI yang telah merangkumkan jawaban, artikel di website tetap akan diberdayakan oleh Google.
***
Karena beberapa poin tersebut, Penulis menyimpulkan kalau media sosial belum akan menggantikan peran mesin pencari, setidaknya dalam waktu dekat. Sebagai alternatif mungkin iya, karena media sosial pun memiliki kelebihannya sendiri, tapi bukan sebagai pengganti.
Tentu opini di atas murni pendapat Penulis pribadi, yang artinya bisa benar, bisa salah, bisa juga di tengah-tengahnya. Mari kita lihat saja bagaimana perkembangan mesin pencari di media sosial.
Lawang, 11 September 2024, terinspirasi setelah menyadari kalau media sosial mulai menggantikan peran mesin pencari
Sumber Featured Image: Sanket Mishra
Sosial Budaya
Hati-Hati Jejak Digitalmu, Siapa Tahu Nanti Jadi Pejabat Publik

Dalam beberapa minggu terakhir, “jejak digital” menjadi isu yang hangat untuk dibahas, terutama di ranah politik. Pasalnya, ada banyak pejabat publik yang “kebakaran jenggot” karena jejak digitalnya di masa lalu dibongkar oleh netizen.
Contoh pihak yang jejak digitalnya terbongkar adalah Ridwan Kamil dan Pramono Anung, dua calon gubernur Jakarta. Singkat cerita, banyak twit candaan bernada seksis. Ridwan Kamil bahkan pernah mengolok-olok orang Jakarta.
Yang paling parah tentu saja kasus yang menimpa wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming. Akun Kaskus bernama @fufufafa diduga menjadi miliknya dengan sederet bukti yang berhasil dikumpulkan oleh netizen. Parahnya, akun tersebut kerap menghina presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Apa Itu Jejak Digital?

Jejak digital adalah apapun yang kita “tinggalkan” di media sosial dan bisa diakses oleh banyak orang, baik pos, twit, foto, video, dan lain sebagainya. Ini adalah definisi menurut Penulis, silakan koreksi apabila definisi tersebut kurang tepat.
Di zaman dulu, kasus skandal di masa lalu atau aib yang telah lama berusaha untuk ditutupi menjadi momok yang mengerikan. Namun, itu pun yang membongkar orang lain berdasarkan hasil investigasi, pengakuan orang, atau bahkan sekadar fitnah.
Nah, kalau di era media sosial seperti sekarang, kita sebagai manusia justru terobsesi untuk membagikan banyak hal kepada publik, bahkan secara berlebihan. Entah itu opini, foto liburan, ungkapan kekesalan, umpatan, pamer kekayaan, dan masih banyak lagi lainnya.
Kalau kita bukan siapa-siapa, mungkin unggahan-unggahan tersebut tidak akan berarti banyak. Namun, beda cerita kalau ternyata kita ditakdirkan untuk menjadi public figure yang gerak-geriknya sering disorot oleh masyarakat umum.
Hal ini sudah terlihat pada kasus yang menimpa pada pejabat-pejabat publik yang telah disebutkan di atas. Entah siapa yang mem-blow up pertama, tapi yang jelas hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya dengan tujuan menjatuhkan.
Di sisi lain, jejak digital juga bisa digunakan untuk menaikkan citra diri. Contohnya adalah Anies Baswedan, di mana pada periode yang sama dengan Ridwan Kamil ketika ia bercanda dengan nada seksis, ia justru sibuk dengan gerakan Indonesia Mengajar.
Jika dulu ada istilah “Mulutmu, Harimaumu,” maka sekarang ada “Jempolmu, Harimaumu.” Zaman memang selalu memiliki caranya sendiri untuk berevolusi.
Berhati-hati Dalam Meninggalkan Jejak Digital

Kasus-kasus membongkar jejak digital para public figure di atas seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk kita agar lebih bijaksana dalam meninggalkan jejak digital di media sosial. Jangan sampai hal tersebut justru menjadi bumerang yang merugikan kita.
Kita semua pernah mengalami berbagai fase pendewasaan diri. Ada masa di mana kita menjadi alay dan haus perhatian, sehingga merasa perlu membagikan berbagai macam hal kepada publik, yang sebenarnya juga tidak peduli-peduli amat dengan kehidupan kita.
Penulis pun yakin kalau jejak digitalnya di media sosial banyak yang memalukan. Mungkin tidak sampai membuat Penulis gagal maju sebagai caleg (seandainya menyalonkan diri), tapi cukup untuk membuat Penulis merasa malu.
Ada satu peristiwa kecil yang teringat ketika membahas hal ini. Ada teman Penulis yang hobi screenshot Story, terutama kalau dianggap Story tersebut bisa menjadi bahan ledekan. Beberapa minggu yang lalu, Story-Story lama tersebut dibongkar di depan yang bersangkutan dan kami semua tertawa terbahak-bahak.
Tujuan membongkar jejak digital di atas dilakukan sebagai bahan-bahan ceng-cengan saja di kalangan circle. Nah, kalau yang membongkar publik yang tidak suka dengan sosok tertentu, jadinya berbahaya, bukan? Elektabilitas orang yang dibongkar bisa langsung terjun bebas.
Oleh karena itu, kalau Pembaca sekalian ada yang berniat untuk menjadi pejabat publik, coba dicek akun media sosialnya apakah ada jejak digital yang berbahaya. Jangan sampai ada jejak digital berbahaya yang tertinggal.
Lawang, 9 September 2024, terinspirasi setelah dalam beberapa waktu terakhir banyak pejabat publik yang terungkap jejak digital di masa lalunya
Sumber Featured Image: LinkedIn
Sosial Budaya
Ketika Pengakuan Sosial Menjadi Kebutuhan Pokok

Jika menengok ke beberapa peristiwa yang sempat menjadi perbincangan netizen, Penulis menemukan sebuah pola di mana hidup di era sekarang terkesan membutuhkan pengakuan sosial sebanyak mungkin.
Bahkan, banyak hal yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan pengakukan sosial tersebut, termasuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Kebutuhan untuk diakui dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain seolah mengalahkan kebutuhan hidup lainnya.
Fenomena ini pun berhasil menarik perhatian Penulis. Berhubung banyak momen yang berhubungan dengan hal ini belum pernah Penulis bahas, Penulis ingin merangkum semuanya di sini.
Berbagai Cara untuk Dapatkan Pengakuan Sosial

Hal yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu adalah adanya joki Strava. Awalnya, Penulis tidak mengetahui apa itu Strava, hingga akhirnya menemukan fakta kalau itu merupakan sebuah aplikasi yang akan melacak aktivitas olahraga kita seperti lari atau bersepeda.
Tampaknya Strava ini menjadi gaya hidup yang sedang hype, di mana pengguna akan membagikan hasil olahraganya ke media sosial. Masalahnya ada saja orang yang enggan berolahraga, tapi tidak ingin ketinggalan dengan tren ini.
Alhasil, muncullah joki Strava. Mereka akan beraktivitas sesuai permintaan, lantas melakukan screenshot ke aplikasi Strava untuk dikirimkan ke klien. Nanti, klien bisa mengunggahnya ke media sosial seolah ia yang telah melakukannya.
Jika mundur lagi ke belakang, salah satu hal yang ramai dibicarakan ketika bulan puasa adalah adanya jasa sewa lanyard untuk digunakan ketika ikut buka puasa bersama (bukber). Lanyard tersebut seolah menjadi semacam medali yang bisa dibanggakan kepada teman-temannya, walau kenyataannya ia berbohong (di bulan puasa lagi).
Bicara tentang sewa, ada juga jasa sewa iPhone. Ponsel buatan Apple ini memang seolah telah beralih fungsi menjadi penanda status sosial. Bahkan, katanya kalau tidak menggunakan iPhone, maka kita tidak akan bisa masuk ke circle pertemanan!
Masih ada banyak contoh bagaimana kita seolah haus akan pengakuan sosial, termasuk memaksa orang lain memanggil kita haji. Namun, rasanya contoh-contoh di atas sudah cukup untuk menggambarkan fenomena ini.
Mengapa Kita Begitu Haus dengan Pengakuan Sosial?

Rasanya manusiawi jika kita merasa insecure dengan orang lain, apalagi jika kita merasa belum bisa sesukses orang lain. Namun, hal tersebut menjadi masalah apabila kita menggunakan jalan pintas untuk menutupi rasa insecure tersebut.
Dari contoh yang sudah Penulis sebutkan, kita rela mengeluarkan uang (yang Penulis yakin tidak sedikit) untuk membohongi orang lain. Padahal tidak olahraga, update Strava. Tidak kerja di BUMN, pakai lanyard BUMN. Punyanya ponsel Android murah, malah sewa iPhone.
Tidak hanya membohongi orang lain, hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai membohongi diri sendiri. Hanya demi pengakuan sosial dan tidak direndahkan oleh orang lain, kita rela untuk melakukan hal-hal semu tersebut.
Penulis pernah mendapatkan cerita dari adik tentang temannya yang dari luar terlihat hidup glamor. Pakaiannya modish, ponselnya iPhone, dan lain sebagainya. Kenyataannya, ia hidup dengan meminjam uang dari teman-temannya demi memenuhi gaya hidupnya tersebut.
Kita menemukan satu alasan untuk mengapa kita rela membohongi dirinya sendiri: demi menuruti gengsi dan gaya hidup. Demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, utang ke banyak orang hingga tidak punya teman pun akan dilakukan.
Cerita lain adalah bagaimana adik Penulis, yang ponselnya hanya Samsung biasa, seolah mendapatkan diskriminasi dari teman-temannya yang pada menggunakan iPhone. Ribet karena tidak bisa AirDrop, kata mereka.
Cerita-cerita tersebut menjelaskan alasan lain mengapa orang rela membohongi dirinya sendiri: karena terkadang lingkungan yang menuntut mereka seperti itu. Kondisi ini diperparah dengan media sosial yang kerap menunjukkan gaya hidup konsuntif.
Padahal, sebenarnya orang lain tidak peduli-peduli amat sama kita. Lantas, mengapa kita menjadi begitu bingung agar dipedulikan oleh mereka? Mengapa harus membohongi diri sendiri dan orang lain untuk itu? Penulis masih tidak habis pikir hingga sekarang.
Penutup
Bertahun-tahun yang lalu, ayah Penulis memberikan nasehat kalau kita sebagai manusia tidak membutuhkan pengakuan orang lain. Siapa yang menyangka, nasehat tersebut masih sangat relevan hingga sekarang, bahkan terlalu relevan.
Terkadang kita memang membutuhkan validasi dari orang lain, terutama saat kita sedang down. Namun, validasi yang paling penting datang dari diri sendiri. Mau siapa pun memberi validasi, kalau kita tidak mampu memvalidasi diri sendiri, ya percuma.
Jadi, menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan validasi dari orang lain ya percuma, karena di lubuk hati terdalam kita tahu kalau kita sedang membohongi diri kita sendiri. Jalan pintas tersebut cuma menjadi topeng demi menutupi kenyataan hidup yang ada.
Daripada terus membohongi diri sendiri dan orang lain demi pengakuan sosial, lebih baik kita fokuskan diri untuk berbenah. Daripada terus mencari pengakukan sosial, lebih baik kita terus memperbaiki diri agar kita bisa mendapatkan pengakuan dari diri sendiri.
Tingkatkan skill dan value diri agar bisa beneran kerja di kantor yang prestise dan bisa beli ponsel impian. Lawan rasa malas dan mulai berolahraga. Itu memang pilihan yang lebih sulit, tapi itu merupakan jalan benar, bukan jalan pintas yang sesat.
Lawang, 21 Juli 2024, terinspirasi setelah melihat fenomena joki strava dan kejadian-kejadian lainnya
Foto Featured Image: SIROKO
-

 Tentang Rasa5 bulan ago
Tentang Rasa5 bulan agoKetika Mencari Pasangan Menggunakan Standar TikTok
-
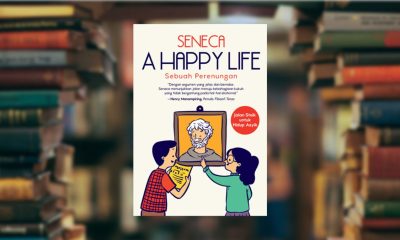
 Buku5 bulan ago
Buku5 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca A Happy Life: Sebuah Perenungan
-

 Politik & Negara5 bulan ago
Politik & Negara5 bulan agoMenyorot Kebijakan Pemerintah yang Makin ke Sini Makin ke Sana
-

 Permainan5 bulan ago
Permainan5 bulan agoKoleksi Board Game #17: Unstable Unicorns
-

 Anime & Komik4 bulan ago
Anime & Komik4 bulan agoKarakter Paling Sial di Dragon Ball adalah Future Trunks
-

 Olahraga5 bulan ago
Olahraga5 bulan agoKado Manis untuk Kroos, Kado Pahit untuk Reus
-

 Buku5 bulan ago
Buku5 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca The Devotion of Suspect X
-

 Anime & Komik4 bulan ago
Anime & Komik4 bulan agoVegeta adalah Karakter Dragon Ball dengan Pengembangan Terbaik

























You must be logged in to post a comment Login