Renungan
Apa yang Saya Pelajar dari Video Asumsi Mengenai Bantar Gebang

Kemarin siang ketika selesai makan siang, tanpa sengaja Penulis mendengarkan sebuah video YouTube dari TV yang sedang ditonton oleh ibu. Hanya sepintas, tapi entah mengapa langsung tertangkap oleh telinga Penulis.
Video tersebut merupakan sebuah video dari Asumsi yang sedang mewawancarai orang-orang di Bantar Gebang, sebuah tempat di Bekasi yang terkenal sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Istilah kerennya, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Salah satu narasumber di video tersebut mengatakan kalau ternyata penghasilan pemulung di sana lumayan mencukupi. Bahkan, ada yang berhasil membangun rumah hingga membeli mobil.
Karena merasa penasaran, malamnya Penulis pun memutuskan untuk menonton video lengkapnya. Dari sana, ternyata Penulis merasa mendapatkan banyak hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup ini.
Bantar Gebang, Tempat Sampah dengan Tumpukan Makna
Penulis mengetahui nama Bantar Gebang pertama kali melalui novel Aroma Karsa karya Dee Lestari. Tokoh utama di novel tersebut digambarkan tinggal di sana dan dianugerahi dengan indra penciuman yang tajam.
Selain itu, Dee Lestari juga membahas mengenai tempat tersebut lebih detail melalui bukunya yang lain berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Di buku ini, Dee menceritakan perjalanan risetnya ke Bantar Gebang untuk lebih mendalami penceritaannya.
Berbekal kedua buku tersebut, Penulis pun berasumsi kalau Bantar Gebang adalah tempat pembuangan sampah raksasa. Sudah, hanya sebatas itu. Tidak ada yang menarik dari sebuah tempat sampah.
Pendapat tersebut ternyata berubah setelah Penulis menonton video dari Asumsi yang melakukan dokumentasi ke sana. Ada beberapa poin yang Penulis catat sebagai pelajaran untuk dirinya sendiri, dan semoga juga bisa menginspirasi para Pembaca sekalian.
Bagi Kita Sampah, Bagi Mereka Harta Karun
Dalam salah satu komik Doraemon, ada alat yang membuat semacam lubang dimensi. Nobita dengan otak bisnisnya pun membuka jasa bagi orang-orang yang ingin membuang sampahnya. Apesnya, Doraemon tersedot masuk dan terbawa ke masa lampau.
Barang-barang yang dianggap sebagai sampah orang modern ternyata bermanfaat untuk orang zaman dulu, bahkan sampai menjadi “inspirasi” untuk cerita rakyat. Setelah berhasil kembali ke zaman sekarang, Doraemon pun menjadi selektif dalam membuang sampah.
Nah, itulah yang benar-benar terjadi bagi orang-orang yang tinggal di Bantar Gebang. Barang yang sudah kita anggap sebagai sampah ternyata bisa menjadi semacam harta karun untuk mereka. Bagi kita bukit sampah, bagi mereka bukit emas.
Para pemulung bisa menemukan barang-barang bagus yang bisa dijual ke penadah dan mendapatkan pemasukan dari sana. Tak jarang, mereka menemukan makanan dan minuman sisa yang sudah dibuang untuk dikonsumsi!
Kemampuan Adaptasi Manusia yang Luar Biasa
Orang gila yang makan dari sampah mungkin sudah biasa, tapi bagaimana dengan orang waras yang melakukan itu? Penulis baru menyadari kalau ternyata ada banyak yang melakukan hal tersebut. Pemulung di Bantar Gebang melakukan hal-hal tersebut.
Mungkin, itu adalah salah satu upaya survive mereka dari kerasnya kehidupan di sana. Meskipun katanya mereka bisa membangun rumah dengan memulung, mungkin mereka sudah terbiasa makan dari sampah demi mengirit pengeluaran.
Penulis merasa heran atas kemampuan adaptasi tubuh orang-orang di Bantar Gebang. Secara logika, makanan yang sudah menjadi sampah tentu penuh dengan kuman dan penyakit, tapi mengapa mereka terlihat sehat-sehat saja dan jarang sakit?
Tak salah lagi, keadaan telah memaksa tubuh mereka melakukan adaptasi yang luar biasa. Demi bisa bertahan hidup, tubuh pun harus menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bahaya yang masuk dari makanan-makanan sisa tersebut.
Terlihat Hina, Padahal Berkecukupan
Penulis benar-benar kaget ketika mendengar pengakuan narasumber di video tersebut (seorang penadah) yang mengatakan kalau anak buahnya yang pemulung ternyata bisa membangun rumah di kampungnya, yang dianggapnya lebih bagus dari rumahnya sendiri.
Tidak cukup sampai di situ, ada banyak pemulung yang berhasil mencicil motor hingga mobil. Jujur, logika Penulis tidak sampai ke sana bagaimana mereka bisa mengelola uangnya dengan begitu baik.
Bagi orang di luar Bantar Gebang, mungkin pekerjaan sebagai pemulung adalah pekerjaan yang hina dan kotor. Namun, nyatanya mereka bisa hidup bahagia dan mampu memiliki berbagai aset.
Ini berkebalikan dengan beberapa orang di kota besar, di mana dari luar keliatan borjuis dan bergaya hidup mewah, padahal barangnya banyak yang kredit, bahkan ada yang hanya pinjaman. Semua demi menjaga gengsi semata. Pertanyaannya, mana yang lebih hina?
Mereka Belajar Finance dari Mana?
Si penadah yang sudah Penulis sebutkan di atas ternyata menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk beternak kambing. Katanya, seandainya ada hal buruk terjadi seperti pandemi kemarin, setidaknya ia punya sesuatu untuk dijual demi menyambung hidup.
Selain itu, ada juga seorang penjaja warung di Bantar Gebang. Ia memiliki semacam lapak di atas tumpukan sampah. Menurut pengakuannya, ia bisa mendapatkan penghasilan dalam sehari antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam sehari.
Ia mengatakan kalau separuh dari pemasukan tersebut ia tabung. Hasilnya, ia pun sudah bisa punya rumah sendiri. Kenyataan ini benar-benar menampar Penulis: Mereka tidak pernah belajar tentang finance, tapi pengelolaan uangnya sangat baik!
Penulis merasa dirinya cukup banyak membaca posting atau menonton video seputar finance, tapi belum bisa di level mereka. Memang ada banyak faktor lain yang memengaruhi ini seperti gaya hidup, tapi Penulis ingin fokus dengan kehebatan mereka dalam mengelola uang.
Nikmat Mana Lagi yang Aku Dustakan?
“Tidak ada orang yang susah, adanya orang yang malas,” tutur penjaja warung di video tersebut. Satu kalimat sederhana yang keluar dari orang biasa, tetapi mampu membuat Penulis merasa malu.
Dibandingkan mereka, Penulis tentu merasa memiliki banyak privilege dalam hidupnya. Penulis jadi merasa bertanggung jawab untuk bisa memanfaatkan privilege tersebut untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Selain itu, Penulis juga sadar kalau selama ini dirinya selama ini terlalu banyak mengeluh. Iya memang kemampuan orang dalam menghadapi masalah beda-beda, tetapi Penulis tidak ingin menjadikan hal tersebut sebagai pembenaran untuk mengeluh.
Penulis jadi banyak-banyak bersyukur karena tidak perlu menjalani kehidupan berat seperti mereka yang setiap hari harus bekerja dengan risiko tinggi. Di TPST seperti itu, terlindas buldoser atau terpapar cairan kimia berbahaya bisa terjadi.
Penulis juga jadi lebih mensyukuri setiap makanan yang disantapnya, bersyukur bisa bekerja di tempat yang nyaman, dan lain sebagainya. Sesungguhnya Penulis jadi sadar, betapa banyak nikmat yang telah Penulis dustakan selama ini.
Penutup
Ketika membaca kolom komentar, mayoritas memuji Asumsi karena “berani” dan totalitas dalam menyusun video tersebut. Bagaimana tidak, sang host sampai nekat untuk memakan makanan bekas!
Bagi Penulis, melihat sisi kehidupan lain yang selama ini tak terpikirkan memang menarik. Penulis jadi mengetahui ada kehidupan seperti di Bantar Gebang yang begitu unik dan berwarna. Kondisi yang memaksa memunculkan celah untuk bertahan hidup.
Mungkin ke depannya Penulis akan lebih sering menonton video-video dokumenter seperti ini agar Penulis bisa mengerti bagaimana kehidupan di luar sana dan membantu Penulis untuk bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur.
Lawang, 11 Oktober 2022, terinspirasi setelah menonton video Asumsi mengenai Bantar Gebang di YouTube
Foto: Detik
Renungan
Jika Kita Ada di Kursi Mereka, Apakah Kita akan Tetap Berisik?

Ini adalah tulisan keempat secara beruntun yang membahas tentang isu masyarakat vs pemerintah yang memanas dalam beberapa minggu terakhir. Mungkin ini akan jadi penutup, sehingga akan Penulis gunakan sebagai bahan renungan bersama.
Meskipun masih terpolarisasi karena hal yang remeh, Penulis melihat kita sebagai rakyat cukup bersatu dalam aksi sepanjang akhir Agustus hingga awal September kemarin. Pasti ada yang masih pro pemerintah, tapi rasanya kali ini mereka minoritas, atau memang enggak kelihatan aja.
Kita bisa bersatu seperti itu karena kita merasa punya “musuh” yang sama, di mana di sini adalah pemerintah terutama DPR yang jadi sasaran utama, maupun pihak pengamanan yang dinilai terlalu brutal hingga ada yang tewas.
Bisa dibilang, saat ini kita sama-sama sedang “menggonggong” untuk menuntut keadilan, apalagi setelah melihat angka fantastis yang diterima oleh para pejabat di saat kehidupan masyarakat sedang sulit, di saat PHK di mana-mana dan ekonomi terasa berat.
Namun, di satu sisi, Penulis jadi merenungkan satu pertanyaan: jika kita berada di dalam menjadi bagian dari pemerintah, apakah kita akan tetap berisik seperti sekarang atau justru diam-diam saja sembari menikmati segala fasilitas dan tunjangan yang diberikan?
Katanya, Pemerintah Itu Cerminan Rakyatnya

Ada yang bilang, pemerintah itu cerminan rakyatnya. Pemerintah itu rata-rata masyarakatnya. Jadi, jangan-jangan alasan kita mendapatkan kualitas pemerintah yang seperti itu, ya karena kita seperti itu, hanya saja belum mendapatkan kesempatan seperti mereka saja.
Hal ini langsung dicontohkan dari kasus penjarahan yang terjadi pada rumah beberapa anggota DPR, yang dijadikan sebagai sasaran karena pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut mereka.
Di satu sisi, Penulis menganggap kejadian tersebut adalah konsekuensi dari apa yang sudah dikatakan atau dilakukan. Namun, di sisi lain, aktivitas penjarahan juga tidak bisa dibenarkan karena mengambil apa yang bukan hak kita.
Ada yang membalas bahwa pemerintah selama ini juga menjarah rakyat, bahkan alam Indonesia pun ikut dijarah. Namun, membandingkan dua hal yang buruk tidak membuat salah satunya menjadi baik. Membandingkan dua hal haram, tidak membuat salah satunya menjadi halal.
Banyak orang di pemerintahan yang korupsi, mungkin di keseharian kita pun masih melakukan korupsi kecil-kecilan, baik disadari maupun tidak. Anggota dewan tidur ketika kerja, mungkin kita di kantor pun terkadang curi-curi waktu untuk tidur siang.
Intinya, kita boleh dan bahkan harus bersuara apabila melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Kita harus tetap “menggonggong” dan mengawasi kerja pemerintah, yang gaji dan tunjangannya berasal dari pajak yang kita bayarkan.
Kalau kita diam saja dan memilih apatis, maka pemerintah bisa makin “sesuka hati” dalam membuat kebijakan. Tentu kita tidak lupa, bagaimana ada beberapa kebijakan yang dibuat dalam waktu kilat jika itu menguntungkan pihak tertentu.
Namun, jangan lupa untuk menengok ke dalam juga, tanyakan kepada diri sendiri apakah kita sudah benar-benar “bersih” dan tidak melakukan hal buruk yang dilakukan oleh pemerintah. Tanyakan kepada diri sendiri, jika kita di dalam, apakah kita akan tetap berisik seperti ketika di luar?
Meskipun kita memiliki banyak kekecewaan atau kekesalan terhadap pemerintah, jangan sampai membuat diri kita merasa paling suci atau lebih baik dari mereka. Daripada seperti itu, alangkah lebih baik kalau kita melihat ke dalam diri sendiri.
Memosisikan Diri Sebagai Kontrol Pemerintah

Ketika membaca kolom komentar untuk konten yang bermuatan politik, Penulis sering menemukan komentar senada yang berbunyi, “jangan ngomong doang, coba buktiin kalau lu lebih bagus dari yang lu kritik!”
Menurut Penulis, komentar seperti ini cukup sesat. Kita mengkritik sebagai rakyat, mengkritik pemerintah (entah eksekutif maupun legislatif) yang memang pekerjaannya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang ada di negara ini.
Nah, mereka kan udah dibayar nih buat jadi pejabat, masa iya kita juga yang menyediakan solusinya? Kita ini memang berfungsi sebagai pengawas agar pemerintah bisa terkontrol dan tidak seenaknya sendiri, lha kok malah ditambahi kerjaan sebagai penyedia solusi.
Mungkin akan ada komentar juga yang intinya menyuruh kita masuk ke dalam pemerintahan dan ubah dari dalam. Ini ada benarnya, tapi kalau sistemnya sudah rusak, bisa-bisa kita yang akhirnya malah terbawa arus. Mau seidealis seperti apa pun, pasti sulit.
Bahkan, komika Pandji Pragiwaksono dalam sebuah acara di Metro TV sempat berujar yang intinya “kalau semua yang berisik masuk, ntar nggak ada yang mengonggong dari luar, dong?” Buktinya banyak aktivis ’98 yang sekarang di kursi pemerintahan, eh ya udah berubah tuh.
Jadi, mungkin bukan pilihan yang salah jika kita memilih untuk tetap di luar tanpa berniat masuk ke dalam. Jika di luar, kita akan lebih bebas bersuara untuk diri sendiri dan masyarakat, bukan bersuara untuk partai yang telah mengusung kita.
Lawang, 11 September 2025, terinspirasi setelah Penulis merasa selama ini lebih banyak melihat sisi buruk pemerintahan Prabowo Subiyanto dan jarang mengulik “prestasinya”
Foto Featured Image: Detik
Renungan
Merenungi Manusia Primitif yang Masih Hidup di Era Modern

Dalam tulisan “Manusia adalah Makhluk Paling Berbahaya di Dunia Ini”, Penulis sudah menjabarkan tentang bagaimana kita ini adalah ancaman paling nyata, baik bagi makhluk hidup lain maupun sesama manusia.
Pada salah satu poin, Penulis juga menjelaskan bagaimana manusia tanpa segan menghabisi manusia lain dengan berbagai alasan, walau ketamakan jelas jadi salah satu faktor utamanya. Alhasil, bangsa-bangsa yang kalah harus menepi demi keselamatannya.
Menariknya, mereka ini terus bisa mempertahankan peradabannya walau terisolasi dari dunia lain. Melalui kacamata kita, mereka terlihat sebagai bangsa primitif yang hidup di era modern yang serba canggih. Keberadaan mereka ini membuat Penulis jadi merenung.

Bagaimana Kehidupan “Manusia Primitif” Terputus dari Kehidupan Modern

Melalui video dokumenter yang sama dari artikel “Manusia adalah Makhluk Paling Berbahaya di Dunia Ini”, Penulis jadi menyadari bahwa di dalam hutan Amazon, masih ada banyak native tribe yang seolah mencerminkan kehidupan beribu-ribu tahun yang lalu.
Penulis juga menemukan fakta tentang Man in Hole. Singkat cerita, ia adalah orang terakhir dari salah satu suku yang menghuni hutan Amazon, setelah anggota sukunya yang lain telah tewas terbunuh akibat konflik agraria yang terjadi di Brazil.
Hidupnya yang nomaden seumur hidupnya terpaksa ia lakukan demi bertahan hidup. Ketika mengetahui fakta ini, Penulis jadi berempati dengannya dan tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jadi “orang terakhir” dari sukunya sebelum akhirnya ia juga meninggal.
Keberadaan mereka, yang pernah (dan mungkin masih) terancam karena peradaban manusia yang lebih modern, terlihat seolah timeline mereka tidak pernah maju dan memutus kehidupan mereka dengan dunia luar. Teknologi yang mengubah peradaban manusia tak pernah menyentuh mereka.
Sebenarnya tak perlu jauh-jauh ke Brazil yang berada di belahan bumi lain. Di Indonesia pun, yang terdiri dari banyak sekali suku, masih banyak yang menjalani kehidupan primitif dan tinggal di dalam hutan, jauh dari peradaban modern.
Secara manusiawi, kita pasti merasa “kasihan” dengan kehidupan yang seperti itu. Namun, pantaskan mereka dikasihani? Atau justru sebenarnya kita yang patut dikasihani?
Apakah Kita Lebih Bahagia dari Manusia Primitif?

Mungkin Mereka Lebih Bahagia dari Kita (Scientific American)
Belum lama ini, Penulis juga membuat artikel berjudul “Bagaimana Manusia Diperbudak oleh Ciptaannya Sendiri”. Teknologi dan berbagai ciptaan kita memang sangat membantu memajukan peradaban, tapi di sisi lain memiliki efek negatif karena mengakibatkan ketergantungan.
Kita akan kesulitan hidup tanpa smartphone, internet, listrik, dan lain sebagainya. Mati listrik beberapa jam saja sudah menderita setengah mati, seolah tidak ada aktivitas offline yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu sembari menunggu listrik kembali nyala.
Nah, tentu “penderitaan” seperti ini tidak pernah dialami oleh manusia primitif. Mereka telah terbiasa hidup berpijak tanah dan beratapkan langit. Mereka tak pernah berjumpa dengan listrik, apalagi internet, dan hidup mereka bisa baik-baik saja dari generasi ke generasi.
Kita dalam peradaban modern kerap dibuat stres dengan berbagai tekanan, yang bisa berupa tuntutan pekerjaan, kewajiban mencari uang untuk melanjutkan hidup, tarikan pajak yang tak masuk akal dari pemerintah, dan lain sebagainya.
Sekali lagi, tekanan seperti ini rasanya tidak dialami oleh manusia primitif. Mereka tidak mengenal adanya KPI, kalau lapar ya langsung berburu atau berkebun. Mereka tidak dibingungkan dengan tatanan dunia yang makin ke sini makin uangsentris.
Para manusia primitif tampaknya juga tak pernah memikirkan gengsi seperti manusia modern, yang kerap ditampilkan melalui gaya hidup mereka. Tanpa pakai baju pun, mereka tetap sehat-sehat saja, walau manusia terutama di barat juga semakin jarang menggunakan baju.
Dengan beberapa contoh tersebut, apakah kita masih bisa berpikir kalau kehidupan kita lebih baik dari kehidupan mereka?
Penutup
Lantas, apakah renungan di atas membuat Penulis ingin hidup seperti manusia primitif? Tentu tidak. Penulis besar dengan kehidupan modern, sehingga penyesuaian untuk hidup seperti mereka akan menjadi penderitaan yang luar biasa.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan insight bahwa di kehidupan modern yang serba digital ini, masih ada kehidupan terbelakang di sudut-sudut dunia ini. Walaupun begitu, belum tentu kita lebih bahagia dibandingkan mereka. Bisa jadi, mereka jauh lebih bahagia dengan kehidupannya.
Penulis merasa bersyukur dengan kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada dirinya, walau terkadang masih ada perasaan iri kepada manusia primitif yang tampaknya bisa hidup lebih tenang dibandingkan kebanyakan manusia modern.
Lawang, 1 Desember 2024, terinspirasi setelah menonton video dokumenter tentang hutan Amazon yang menjadi rumah bagi penduduk asli Amerika
Foto Featured Image: AP News
Sumber Artikel:
Renungan
Bagaimana Manusia Diperbudak oleh Ciptaannya Sendiri
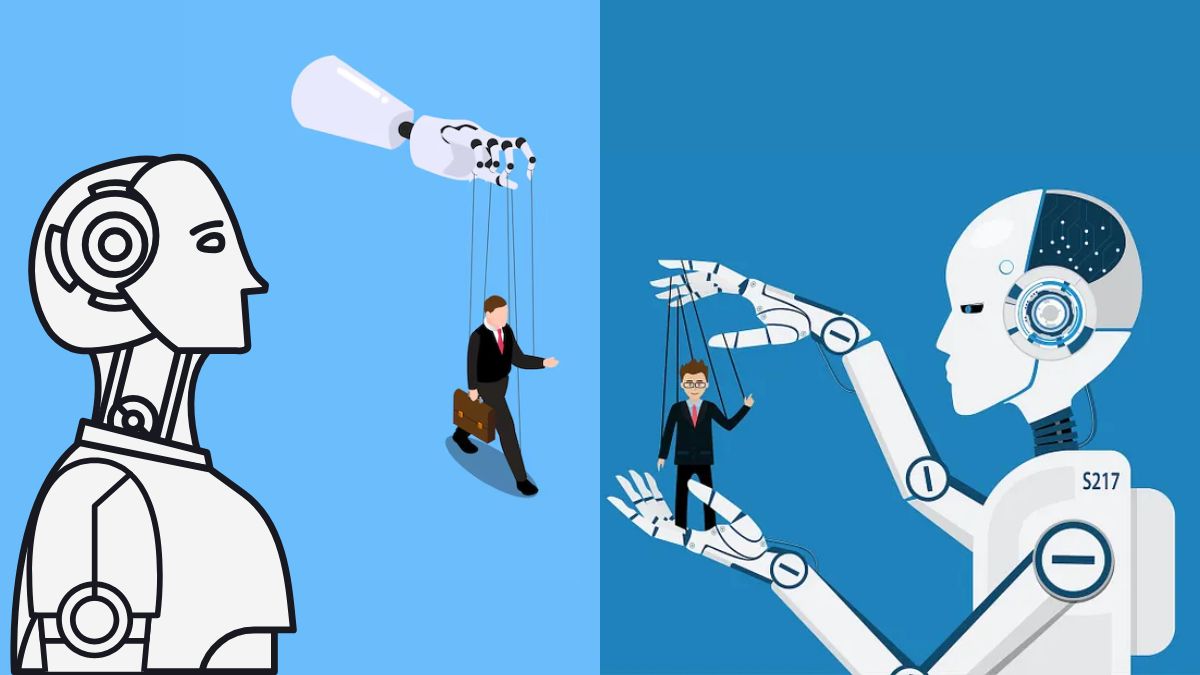
Saat ini, Penulis sedang membaca buku Filsafat Moral karya Fahruddin Faiz, setelah sebelumnya menyelesaikan buku Filsafat Kebahagiaan (ulasan menyusul). Nah, ketika membaca bagian Hans Jonas, Penulis menemukan sesuatu yang menarik.
Dalam salah satu subbabnya, Faiz menjabarkan “Situasi Apokaliptik Teknologi” yang pernah disinggung oleh Jonas. Intinya, teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia berpotensi mengakibatkan kiamat bagi peradaban manusia.
Menurut Jonas, semakin manusia mengembangkan teknologi, mereka semakin tidak mampu menguasai teknologi yang mereka ciptakan (hal. 79). Tanda-tandanya makin ke sini makin terlihat, di mana manusia semakin diperbudak oleh teknologi buatannya sendiri.
Bagaimana Manusia Diperbudak oleh Ciptaannya Sendiri

Diperbudak oleh Ciptaan Sendiri (cottonbro studio)
Ketika menuliskan opening di atas, teknologi apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Mungkin mayoritas jawabannya adalah smartphone, internet, hingga media sosial. Jawaban itu benar, tapi yang memperbudak kita jauh lebih banyak dari itu.
Ketiga hal yang Penulis sebut di atas jelas telah menjadi keseharian kita. Pernah terbayang satu hari tanpa ketiganya? Rasanya kita sudah begitu tergantung kepadanya sehingga rasanya tak mungkin hidup tanpa ketiganya.
Sekarang bayangkan seandainya dunia tiba-tiba mengalami Internet Apocalypse, di mana tiba-tiba tidak ada lagi internet di dunia. Selain smarpthone kita menjadi nottoosmartphone, media sosial pun tak bakal bisa akses.
Lebih gawatnya lagi, kalau yang bekerja remote seperti Penulis, jelas kehilangan pekerjaan akan terjadi. Semua harus kembali manual seperti puluhan tahun yang lalu, dunia di mana belum ada internet.
Namun, sebenarnya ciptaan kita yang memperbudak tak hanya sebatas itu. Internet hanyalah sebagian kecil saja. Contoh lain yang tak kalah menyusahkan seandainya tiba-tiba lenyap adalah listrik. Seandainya internet tak hilang pun, akan percuma jika tidak ada listrik.
Bayangkan, tak ada tempat untuk menyimpan makan seperti kulkas, tak ada lampu untuk penerangan di malam hari, tak ada mesin cuci untuk membersihkan pakaian, tak ada komputer untuk bekerja, dan masih banyak lagi hal yang tak akan bisa kita lakukan.
Contoh lain, bayangkan dunia tanpa bensin. Kendaraan semewah Ferrari atau Lamborghini pun akan menjadi mesin yang tidak bisa melakukan apa-apa. Manusia diberi pilihan mau mengendarai kuda atau sepeda untuk bisa mencapai tujuan dengan cepat.
Jangan lupa, uang yang merupakan alat ciptaan manusia untuk mempermudah transaksi pun juga telah memperbudak kita sejak lama. Tentu Pembaca sudah bosan mendengar berita tentang bagaimana serakahnya manusia demi mendapatkan uang.
Manusia rela melakukan banyak hal tercela untuk bisa mendapatkan uang, yang ia gunakan untuk memenuhi hawa nafsunya yang tak berbatas. Kalau perlu menyengsarakan manusia satu negara, mereka akan melakukannya tanpa peduli sama sekali.
Contoh-contoh di atas rasanya sudah cukup memberikan gambaran bagaimana kita manusia sudah diperbudak dan dibuat ketergantungan dengan ciptaan kita sendiri. Apalagi, kita baru akan memasuki era AI yang tampaknya akan dengan mudah membuat kita ketergantungan.
Lantas, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Apa Kita Siap Hidup Tanpa Internet? (YouTube)
Kita sekarang mengetahui bahwa manusia diperbudak oleh ciptaannya sendiri? Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia agar tidak diperbudak oleh ciptaannya sendiri? Apakah kita harus kembali hidup ala zaman batu ketika kita belum menemukan apa-apa?
Kalau Penulis, rasanya sekarang kita berada di situasi yang hampir tidak memungkinkan untuk lepas seutuhnya segala hal yang telah kita ciptakan. Tak mungkin juga kita mengambil langkah ekstrem dan meninggalkan semua teknologi yang ada.
Menurut Penulis, apa yang dimaksud dari peringatan Hans adalah bagaimana kita sebagai manusia harus selalu ingat kalau teknologi yang kita buat adalah alat yang harus kita kendalikan, bukan kita yang justru oleh dikendalikan.
Sesederhana contoh media sosial, jangan mau kita terus diperbudak dengan terus melakukan scrolling tanpa batas dan membuat diri kita menjadi komoditas platform untuk dijual ke pengiklan. Kita harus bisa mengontrol durasi penggunaan media sosial kita.
Penggunaan listrik pun ada baiknya kita kontrol dengan bijaksana. Jangan di siang hari kita menyalakan semua lampu padahal ruangan cukup terang. Jangan mentang-mentang kita bisa bayar, lantas membuang-buang energi seperti itu.
Para ilmuwan atau siapapun itu yang telah menciptakan berbagai hal memang membuatnya untuk mempermudah kehidupan kita sebagai manusia. Kita harus berterima kasih kepada mereka karena hidup kita menjadi lebih mudah karena ciptaan-ciptaan mereka.
Selain itu, jangan sampai kita sebagai manusia justru akan dimusnahkan oleh ciptaan kita sendiri. Kepandaian manusia justru digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal. Namun, itulah realita yang sedang terjadi saat ini.
Kutipan yang diucapkan oleh Jonas juga bisa diartikan bahwa ada masanya manusia akan membuat senjata yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Contoh mudahnya, lihat saja Ultron yang dihadapi oleh para Avengers.
Semoga saja hal tersebut tidak pernah terjadi, baik di masa kini maupun di masa depan. Semoga manusia cukup bijak untuk memanfaatkan ciptaan-ciptaannya. Jangan sampai kehidupan di bumi ini rusak hanya karena kita tidak mampu mengendalikan apa yang kita ciptakan.
***
Lawang, 29 November 2024, terinspirasi ketika membaca buku Filsafat Moral karya Fahruddin Faiz
-
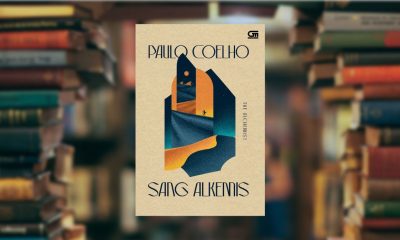
 Fiksi9 bulan ago
Fiksi9 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Sang Alkemis
-

 Permainan9 bulan ago
Permainan9 bulan agoKoleksi Board Game #29: Blokus Shuffle: UNO Edition
-

 Olahraga11 bulan ago
Olahraga11 bulan agoSaya Memutuskan Puasa Nonton MU di Bulan Puasa
-

 Olahraga10 bulan ago
Olahraga10 bulan agoTergelincirnya Para Rookie F1 di Balapan Debut Mereka
-

 Politik & Negara11 bulan ago
Politik & Negara11 bulan agoMau Sampai Kapan Kita Dibuat Pusing oleh Negara?
-

 Musik7 bulan ago
Musik7 bulan agoMari Kita Bicarakan Carmen dan Hearts2Hearts
-

 Pengalaman11 bulan ago
Pengalaman11 bulan agoIni adalah Tulisan Pertama Whathefan di 2025
-

 Politik & Negara7 bulan ago
Politik & Negara7 bulan agoPemerintah Selalu Benar, yang Salah Selalu Rakyat





















You must be logged in to post a comment Login