Leon dan Kenji (Buku 2)
Chapter 71 Telepon dari Rika
Published
4 tahun agoon
By
Fanandi
Tak lama berselang setelah kesehatanku pulih, aku segera memberi kabar kepada paman. Aku yakin, ia pasti khawatir sekali karena meninggalkan aku dengan kondisi yang kacau. Entah bagaimana ceritanya ia dan ayah pada akhirnya memutuskan untuk pergi ketika itu. Melalui telepon, Paman memberitahu bahwa ia baru bisa datang berkunjung dua minggu lagi karena telah membuat janji terlebih dahulu dengan rekan bisnisnya. Aku bisa memaklumi hal tersebut dan mengatakan akan menunggu kedatangannya.
Bukan hanya menunggu paman, aku juga menunggu ayah. Walaupun paman tidak mengatakan apapun, aku yakin ia akan membawa laki-laki itu bersamanya. Aku tak tahu apakah laki-laki tersebut peduli dengan kondisiku, yang jelas aku masih punya segudang pertanyaan yang harus dijawabnya. Secara perlahan, aku akan menguak semua misteri yang telah mengekangku sejak lama, bahkan sejak aku belum dilahirkan ke dunia ini.
Semenjak mendengar cerita tentang ibu -kedua ibuku- dan perlawanan mereka melawan rezim, aku jadi giat membaca buku tentang sejarah terutama yang terkait dengan Orde Baru. Tidak hanya buku dari perpustakaan sekolah, buku koleksi Kenji pun aku pinjam. Pada dasarnya aku tidak terlalu tertarik dengan sejarah, karena bagiku belajar masa lalu tidak terlalu berguna. Dengan terkuaknya masa lalu keluargaku, mau tidak mau aku harus banyak membaca literasi agar lebih memahami bagaimana suasana, kebijakan politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya di saat itu. Aku yakin hal-hal tersebut akan banyak membantuku.
“Aku masih ada kumpulan kliping koran, seandainya kamu ingin baca-baca Leon,” kata Kenji sewaktu aku kembali mampir ke rumahnya untuk kembali meminjam buku.
“Simpan itu untuk nanti, aku perlu memahami hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu. Kau tahu, aku tidak terlalu tertarik dengan sejarah sehingga banyak yang harus kupelajari.”
“Baik Le, akan kusimpan itu untukmu. Omong-omong, apa kamu enggak ngerasa kalau kamu terlalu banyak mengalokasikan waktu buat baca-baca sejarah?”
Pertanyaan dari Kenji membuatku yang sedang sibuk memilah buku menoleh ke arahnya. Aku melemparkan pandangan yang kebingungan ke arahnya.
“Maksudmu?”
Kenji, tetap dengan wajahnya yang senantiasa meneduhkan, berusaha menjelaskan maksudnya tanpa perlu menyakiti perasaanku.
“Kalau aku perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering melamun ketika guru sedang menerangkan di kelas. Ketika punya waktu kosong, kamu lebih memilih untuk membaca buku-buku sejarah hingga mengabaikan teman-teman yang lain. Bahkan Rika sampai mengkhawatirkanmu, loh.”
Tak satu kata pun yang meluncur keluar dari bibirku. Aku segera kembali menyibukkan diri dengan menelusuri buku-buku milik Kenji. Memang benar, aku sering melamun akhir-akhir ini baik ketika di kelas ataupun di rumah. Walaupun tak bermaksud seperti itu, pikiranku selalu melayang ke berbagai teori seputar misteri yang ada di hadapanku saat ini. Aku tahu aku telah berjanji ke Kenji untuk fokus ke Ujian Nasional yang tinggal beberapa bulan lagi, namun terkadang otak kita mengkhianati pemiliknya. Aku menyadari kesalahan ini, namun belum tahu bagaimana cara mengatasinya.
“Percaya sama aku Le, setelah kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai pelajar, kita akan bongkar tuntas misteri yang menyangkut orangtua kita. Kamu kira aku enggak penasaran? Aku juga sering kepikiran, Le, biasanya sebelum tidur aku akan merenungkannya sejenak. Akan tetapi, aku masih bisa mengendalikan diriku agar tidak terlalu larut dan mengabaikan hal penting lain dalam hidup ini,” tambah Kenji setelah menyadari bahwa aku tak tertarik untuk membalas perkataannya. Setelah memutuskan untuk meminjam beberapa buku, aku pamit untuk pulang ke rumah.
***
Sehari sebelum bertemu dengan paman dan ayah, hatiku tiba-tiba merasa gelisah. Ada kekhawatiran kalau aku kembali kesulitan mengendalikan emosi seperti kemarin. Memang aku sudah meminta Kenji untuk sekali lagi menemaniku, namun tetap saja rasa cemas tersebut menggantung begitu saja. Gisel menyadari hal ini dan berusaha untuk meyakinkan aku kalau semua baik-baik saja. Aku pun berusaha menenangkan adikku dengan mengusap kepalanya seperti biasa, walaupun di dalam hatiku sendiri belum ada ketenangan.
Akibatnya, aku kesulitan untuk tidur. Sudah sekitar satu jam aku mengguling-gulingkan badanku ke berbagai arah. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil ponselku dan mencari kontak Rika. Aku mengiriminya pesan singkat yang menanyakan apa ia sudah tidur. Tak lama berselang, ponselku bunyi memecah heningnya malam karena Rika tiba-tiba menelepon.
“Halo Leon, kamu pasti lagi kepikiran sesuatu kan makanya sampai chat aku malam-malam?” sapa Rika sewaktu aku mengangkat telepon.
“Hehe, iya Rika, kau benar. Aku sudah satu jam baring di kasur tanpa bisa terlelap sedikit pun. Kau sendiri belum tidur?”
“Belum nih, tadi lagi dapet ide buat bikin cerita baru. Eh, keterusan sampai sekarang.”
“Oh iya? Cerita tentang apa?”
“Rahasia, hehehe. Kayaknya ini bakal jadi cerita terpanjangku yang pertama deh, Le. Biasanya kan aku cuma bikin cerita pendek yang cuma beberapa lembar.”
“Tentang dunia sihir milik Pangeran Kegelapan?” kataku sedikit menggodanya, mengingat ia sering memanggiku dengan sebutan itu.
“Hehehe, bukan kok. Yah, walaupun ada unsur fantasinya, novel ini bercerita tentang kehidupan seorang gadis yang ingin kabur dari kehidupannya.”
“Tuh, kau kelepasan.”
“Eh, iya. Aduh, jadi enggak surprise dong!”
“Enggak apa-apa Rika, toh aku juga belum tahu kelanjutan ceritanya seperti apa.”
“Iya sih, kamu bener juga. Sekalian deh, aku lagi bingung sama nama karakter utamanya. Kamu ada usul enggak?”
“Perempuan, ya? Sebentar coba aku pikir. Dia seperti apa?”
“Yang jelas dia anak kaya raya yang kesepian karena orangtuanya sibuk bekerja. Ia tipikal gadis yang memendam semuanya begitu saja. Ia juga pinter banget karena papanya menuntut seperti itu.”
“Jadi kayak ada kesan misteriusnya gitu, ya.”
“Iya, Le. Aku udah kepikiran judulnya nanti akan berawalan kata distopia.”
“Distopia?”
“Iya, kebalikan dari utopia. Artinya kurang lebih seperti tempat yang kacau kayak neraka dunia gitu, lah.”
“Kalau gitu, nama belakangnya juga pakai kata ‘ia’ aja Rika. Mungkin Lia atau Tia gitu.”
“Bagus juga usulmu Le, tapi yang kamu sebutkan terlalu pasaran. Coba aku tulis satu persatu kali ya, dari A sampai Z.”
Rika pun meletakkan ponselnya, mungkin untuk mengambil catatan dan bolpoin. Sembari menunggu, aku pun mencoba untuk mengurutkannya dan mencari mana yang paling cocok untuk nama karakter dari novel Rika.
“Aia, Bia, Cia, Dia, Eia, Fia, hmm Fia lumayan menarik kayaknya. Gia, Hia, Iia, Jia, Kia, wah Kia juga bagus, terdengar anggun. Lia…,” Rika nampak bergumam sendiri di telepon, membuatku ingin memotong kesenangannya.
“Halo Rika?”
“Eh, maaf Leon aku malah jadi sibuk sendiri, ehehe. Nanti aku lanjutin aja, kan tadi kamu bilang lagi ada pikiran, eh malah aku yang ngomongnya ke mana-mana. Maaf ya, kebiasaan burukku ya gini ini Leon kalau udah asyik sama cerita sendiri.”
“Enggak apa-apa kok, aku cuma mau bilang kayaknya Kia yang paling cocok. Aku tadi udah ngurutin dari A sampai Z, itu yang paling cocok.”
“Gitu ya menurutmu? Aku juga setuju sih. Tapi kalau Kia aja kurang deh kayaknya.”
“Gimana kalau Zaskia?”
“Kamu jenius, Le! Aku langsung sreg denger nama itu dari kamu.”
“Terima kasih Rika.”
“Oke, berarti nama karakter utamanya Zaskia, panggilannya Kia. Udah, nanti aku lanjutin lagi. Sekarang kamu yang cerita ke aku.”
Aku pun menarik napas panjang sebelum memulai cerita ke Rika.
“Besok aku akan bertemu dengan ayah lagi.”
“Oh begitu. Terus terus?”
“Gimana ya, aku khawatir akan lepas kendali lagi. Ketika berhadapan dengan laki-laki itu, aku kesulitan untuk mengendalikan emosiku. Selalu terbayang betapa buruk perlakukannya kepadaku di masa kecil.”
“Iya, aku paham Leon. Kamu sudah mengalami masa kecil yang cukup sulit.”
“Di sisi lain, aku merasa butuh bertemu dengannya untuk mendapatkan jawaban. Ada banyak sekali pertanyaan yang menggantung di pikiranku akhir-akhir ini.”
“Makanya kamu sering ngelamun ya akhir-akhir ini.”
Aku mengambil jenak sejenak sebelum mengiyakan pernyataan yang dilontarkan Rika. Jika sampai dua orang terdekatku mengatakan sesuatu yang sama, artinya aku memang sedang tidak baik-baik saja.
“Gini ya Leon,” kata Rika setelah aku cukup lama diam, “kamu kemarin dengan berani sudah memutuskan cerita tentang kehidupanmu ke teman-teman. Salah satu tujuanmu adalah untuk berdamai dengan masa lalumu sendiri, bukan? Bertemu dengan ayahmu bahkan memaafkannya adalah salah satu cara lain yang harus lakukan.”
“Iya Rika, kau benar.”
“Percaya sama aku, semuanya akan baik-baik aja. Aku yakin banget kamu bisa ngendaliin emosimu kali ini. Mungkin masih akan ada fakta-fakta lain yang mengejutkan, tapi aku yakin kamu akan lebih siap kali ini.”
“Begitu ya, Rik.”
“Bahkan kalau perlu, aku akan ikut ke rumahmu besok agar Kenji enggak sendirian seandainya kamu kembali mengamuk. Tapi aku yakin kalau kejadian seperti itu enggak akan terulang lagi. Aku percaya sama kamu, Le.”
Kata-kata yang kudengar dari Rika, entah bagaimana caranya, bisa membuatku lebih tenang dan merasa yakin. Semua yang ia katakan masuk akal dan begitu mencerahkan, mungkin karena ia pun pernah mengalami permasalahan yang serupa. Siapa yang menyangka, gadis yang seolah hidup di dunia fantasi ini bisa memiliki pemikiran sedewasa ini.
“Terima kasih Rika, aku benar-benar bersyukur bisa kenal dan dekat denganmu.”
“Ih, Leon malem-malem nggodain. Genit amat, mas?”
“Bu…bukan seperti itu maksudku, Rik. Aku…aku cuma menyampaikan apa yang kurasakan,” timpalku dengan sedikit gagap, merasa perkataanku barusan sedikit kurang ajar kepada lawan jenis.
“Hahaha, kamu ini lucu ya, Le, gemes banget deh. Aku bercanda kok Leon, jangan dianggap serius.”
“Oh, begitu, baiklah.”
“Iya iya, aku juga bersyukur udah kenal sama kamu. Makasi ya udah betah sama aku yang aneh ini.”
“Aku tak pernah menganggapmu aneh, Rika.”
Maka pembicaraan kami pun berlanjut membahas hal-hal lain yang tidak begitu penting. Mungkin ada satu jam kami saling bertukar cerita melalui telepon, dan ini menjadi durasi terlamaku. Selalu menyenangkan untuk ngobrol dengan Rika, ia selalu punya cara untuk membuat pembicaraan tidak membosankan. Apalagi, aku termasuk tipe orang yang gampang kehabisan topik pembicaraan.
Ketika jam dinding menunjukkan pukul sebelas malam, barulah kami mengakhiri percakapan kami dan saling memberi ucapan selamat tidur. Setelah meletakkan handphone di meja, aku berbaring di kasur orangtuaku. Karena kamarku belum juga direnovasi, beberapa hari ini aku tidur di sini walaupun kadang lebih memilih untuk tidur di ruang tamu ataupun ruang tengah. Tidur di sini selalu membuat pikiranku mengembara tanpa arah yang jelas. Samar-samar terkadang aku mencium aroma ibu -ibu angkatku-, walau aku yakin itu hanya buah imajinasiku semata. Tapi jika memang benar, mungkin ia sedang mengamati anaknya yang sedang gamang karena memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada orangtuanya.
Sekitar 45 menit aku melamun, mataku akhirnya terlelap tanpa tahu apa yang akan menanti keesokan harinya.
You may like
-


Bagaimana Caranya agar Semangat Membaca Buku?
-


Saya Membaca Buku untuk Mengurangi Candu Media Sosial
-


[REVIEW] Setelah Membaca The Devotion of Suspect X
-


[REVIEW] Setelah Membaca Twenty-Four Eyes: Dua Belas Pasang Mata
-


[REVIEW] Setelah Membaca Keajaiban Toko Kelontong Namiya
-
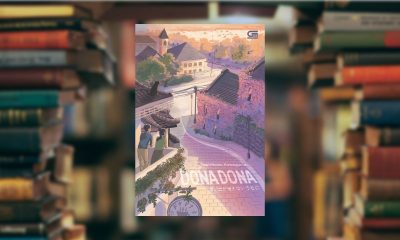

[REVIEW] Setelah Membaca Dona Dona
Leon dan Kenji (Buku 2)
Epilog: Setelah Kematian Wijaya
Published
4 tahun agoon
9 Januari 2021By
Fanandi
Kantor polisi terasa lengang, hanya ada suara angin dari AC. Peran komputer telah digantikan oleh sebuah mesin kotak canggih yang mampu merekam apapun kesaksianku dengan baik, termasuk ekspresi terkecil wajahku. Sudah satu jam aku berada di entah ruangan apa ini, menanti ketidakpastian. Yang jelas, hanya ada satu kalimat yang menggantung di pikiranku: hidupku akan berakhir di penjara. Petugas kepolisian yang ada di hadapanku mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya.
“Dokter Leon, saya ulangi sekali lagi, Anda ke sini untuk menyerahkan diri?” tanya petugas tersebut.
“Benar.”
“Dengan alasan pembunuhan berencana?”
“Benar.”
“Korban adalah Wijaya Hardikusuma, mantan konglomerat yang sudah berusia lanjut?”
“Benar.”
“Pembunuhan dilakukan dengan alasan balas dendam karena korban merupakan pelaku pembunuhan ibu dan beberapa kerabat Anda?”
“Benar.”
“Dan metode pembunuhannya, eh, dengan ancaman?”
“Benar.”
Petugas tersebut menggaruk-garuk lagi kepalanya. Nampaknya baru kali ini ia menemukan kasus sejanggal ini. Pembunuh yang menyerahkan diri karena merasa bersalah memang banyak, tapi pembunuh yang mengakui pembunuhannya hanya dengan bersenjatakan ancaman? Rasanya baru kali ini petugas itu mengalaminya.
“Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal karena komplikasi penyakit yang telah lama dideritanya. Tidak ditemukan adanya unsur kekerasan ataupun racun pada tubuhnya. Bahkan yang saya dengar dari salah satu perawat, Anda berusaha memberikan pertolongan pertama begitu korban mengalami tanda-tanda kejang, benar seperti itu?”
“Benar, saya memberikan pertolongan karena telah mengurungkan niat untuk membunuh. Tapi tetap saja, saya menyadari bahwa ancaman saya di awal lah yang memicu penyakitnya. Seandainya saya tidak memberikan ancaman, mungkin Wijaya masih hidup sekarang.”
Sekali lagi si petugas menggaruk kepalanya. Nampaknya ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara meladeniku. Pasal apa yang bisa menjeratku? Apakah sekadar ancaman sudah merupakan tindak pidana? Berapa lama masa hukuman yang akan menantiku?
“Sepengetahuan saya, tidak ada pasal yang bisa menjerat Anda untuk masuk sel. Niat selama hanya berada di kepala tidak akan membahayakan pihak lain. Mesin AI yang ada di depan Anda ini rasanya juga akan menyimpulkan hal yang sama.”
“Tapi tetap saja…” aku menggantungkan kalimatku karena bingung harus berkata apa lagi. Mungkin kedatanganku ke kantor polisi setelah proses otopsi Wijaya hanya merupakan tindakan spontanku yang masih terkejut atas apa yang baru saja terjadi.
“Jadi, bapak ingin tetap membawa kasus ini ke pengadilan?”
“Benar.”
“Ada pihak pengacara?”
“Ada.”
Jawaban tersebut buat keluar dari mulutku, melainkan dari laki-laki yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Ketika menolehkan wajahku, aku melihat sosok Zane Trunajaya yang sudah semakin menua. Lihat saja, rambut dan jenggotnya sudah dipenuhi oleh uban. Padahal usianya tak terlalu jauh dariku.
“Selamat malam pak, saya Zane Trunajaya yang akan menjadi pengacara saudara Alexander Napoleon Caesar atas dugaan kasus pembunuhan berencana. Tapi sebelumnya, saya mohon izin dulu untuk bicara empat mata dengannya.”
“Ya ya ya, silakan,” kata petugas tersebut dengan pasrah. Nampaknya ia mulai mencurigai kalau kedatanganku ke kantor polisi hanya untuk sekadar mencari sensasi. Namaku cukup terkenal, aku melihat ada beberapa wartawan membuntuti mobil listrikku sewaktu perjalanan dari rumah sakit ke sini. Mungkin Zane mengetahui posisiku juga dari berita daring yang bisa diakses secara kilat, terlalu kilat bahkan.
“Leon, astaga, kerasukan apa dirimu?” tanya Zane sewaktu kami berdua menemukan tempat yang cukup sepi.
“Aku melakukan hal yang menurutku benar, Zane. Lagipula, dari mana kau tahu aku di sini? Aku tidak bercerita ke siapapun, termasuk keluarga.”
“Kamu enggak lihat wartawan di depan pada heboh? Dokter yang namanya terkenal hingga banyak orang yang menginginkannya menjadi Menteri Kesehatan, tiba-tiba ngebut ke kantor polisi setelah pertama kali gagal menyelamatkan pasiennya. Semua orang pasti akan klik judul berita yang dibuat oleh para wartawan itu. Dengan teknologi sekarang, mereka bisa membuatnya hanya dalam hitungan menit.”
Dugaanku terbukti benar, Zane tahu aku dari sini dari berita.
“Adikmu sampai menghubungiku, khawatir kakaknya tidak bisa ditelepon setelah baca berita kegagalan perdanamu. Astaga Leon, apa yang ada di pikiranmu? Kenapa bertindak gegabah seperti ini?”
Aku diam saja dicecar pertanyaan-pertanyaan tersebut dari Zane. Entah mengapa aku tak berani memandang kedua matanya.
“Pasienmu Wijaya, kan? Tidak ada pasien lain yang akan memicumu bertindak seperti ini selain dia.”
Meskipun sudah dipenuhi uban, kecerdasan Zane belum sama sekali hilang. Kecerdasannya mengingatkanku pada…
“Aku bisa bicara dengan petugas untuk meluruskan apa yang tengah terjadi. Tidak ada tindakanmu yang berbau pidana, kamu enggak akan bisa dipenjara hanya karena memiliki niat yang tidak jadi dilakukan. Kalau semua bisa dihukum hanya karena niat, penjara enggak akan muat nampungnya.”
“Ini beda Zane,” aku akhirnya buka suara, “Wijaya terkena serangan jantung setelah aku mengungkapkan siapa aku dan mengungkapkan keinginanku untuk balas dendam. Seandainya aku tidak berbuat seperti itu, mungkin dia masih hidup.”
“Para wartawan itu telah mewawancarai keluarga Wijaya. Katanya, itu bukan pertama kali Wijaya terkena serangan jantung. Entah sudah berapa ring yang ada di pembuluh darahnya. Sejak awal, mereka tidak berharap banyak, Wijaya memang sudah terlalu tua dan mungkin memang sudah ditakdirkan meninggal setelah bertemu dengan korbannya.”
Zane mengendurkan ekspresi wajahnya, memandangku dengan rasa simpati.
“Seandainya Wijaya masih hidup, kita akan memprosesnya lewat hukum atas kejahatan di masa lalunya. Orang yang selama ini kita cari akhirnya ketemu dalam kondisi tidak berdaya. Hanya saja, itu akan membuatnya makin menderita. Biarlah dia diadili di akhirat karena kita tidak bisa menjeratnya di dunia,” tambahnya lagi.
Kepalaku sudah mulai berpikir jernih. Benar yang dikatakan Zane, ini semua sudah ditakdirkan.
“Waktu aku memandangi Wijaya dengan penuh dendam, aku merasa tiba-tiba ada tepukan halus pada bahuku. Ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan dendamku mendadak lenyap begitu saja. Kemudian, aku melihat Wijaya mulai kesulitan bernapas dan aku langsung memberikan pertolongan pertama.”
“Nah, sekarang otakmu yang cemerlang itu mulai bisa digunakan dengan normal, kan? Sudahlah, kamu hanya terguncang karena baru saja bertemu dengan orang yang selama ini membuatmu menderita. Kamu memang salah karena berniat membunuh orang, tapi niat tersebut tidak jadi kamu lakukan.”
“Iya Zane, terima kasih karena sudah datang kemari.”
“Tenang saja, lagipula sebentar lagi kamu akan jadi adik iparku. Tunggu di sini, aku akan bicara dengan petugas di dalam. Nanti kita makan malam bareng.”
Begitu Zane berjalan ke dalam kantor polisi, aku segera mengaktifkan ponselku yang dari tadi mati. Aku langsung menghubungi satu nomor yang pasti sudah mencemaskanku.
“Halo Gisel?”
“KAKAK DARI MANA? KAKAK ENGGAK TAHU DARI TADI GISEL TELEPON ENGGAK ADA NADA SAMBUNGNYA? KAKAK MASUK BERITA TAHU, DAN UNTUK PERTAMA KALINYA BUKAN BERITA BAGUS!!! MALAH UDAH ADA YANG BIKIN BERITA SKANDAL YANG ENGGAK BENER!!! KAKAK ITU KEBIASAAN KALAU ADA MASALAH SUKA HILANG TIBA-TIBA. KAKAK ITU…”
Mungkin sekitar lima menit Gisel memarahi dengan nada tinggi seperti itu. Aku hanya bisa diam mendengarkannya, menantinya capek sendiri.
“Sudah marahnya?” tanyaku pelan setelah ada jeda beberapa detik darinya.
“Belum, tapi Gisel capek, jadi berhenti dulu.”
“Kalau gitu gantian ya, Gisel yang dengerin kakak.”
Aku pun menceritakan apa adanya ke adik perempuan kesayanganku itu, menjelaskan situasi yang sebenarnya. Pada akhirnya, kemarahan Gisel pun bisa kuredam.
“Selama Gisel kuliah di luar, jangan bikin Gisel kepikiran dong kak. Nanti makin lama lulusnya Gisel, padahal udah kangen sama Indonesia. Makanya kakak cepet nikah biar ada yang ngurusin kakak, calon juga udah ada juga.”
“Duh, calon bu dosen ini jadi makin galak ya. Iya, maafkan kakak, tapi Gisel pasti tahu kenapa kakak bisa sampai seperti ini.”
“Iya Gisel paham, tapi kan bisa ngerem dikit, enggak grusa-grusu seperti ini. Terus Kak Zane di mana sekarang?”
“Masih di dalam, ngobrol sama petugas.”
“Ya udah kalau gitu, kakak jaga kesehatan, jangan telat makan. Kakak tugasnya ngobatin orang, jangan sampai diri sendiri enggak keurus.”
“Iya iya, Gisel juga ya, jaga kondisi di sana. Jepang habis gempa bumi yang lumayan besar, kan? Peringatan tsunami juga muncul.”
“Iya kak, tenang, kampusnya Gisel jauh dari pesisir kok. Ya udah, Gisel mau lanjut ngerjakan disertasi, papai kakak.”
Aku pun mematikan telepon dan segera melamun. Mungkin memang semuanya telah ditakdirkan seperti ini. Wijaya diberi hidup sampai bertemu denganku, anak dari korban yang telah ia habisi karena mengusik bisnisnya. Kalau saja aku tidak merasakan tepukan itu, mungkin aku akan melanjutkan niat membunuhku.
Sentuhan tangan siapa kah itu? Aku merasa itu sentuhan tangan dari Kenji, kawan lamaku yang telah lama tiada. Sama sepertiku, ia juga merupakan anak dari korban Wijaya. Beda denganku, ia tak pernah menyimpan dendam. Ia membantuku mengusut kasus Wijaya, tapi tak pernah terucap dari mulutnya kalau ia menginginkan kematian Wijaya sebagai bayarannya. Seandainya dia masih hidup, mungkin dia akan memintaku untuk memaafkan Wijaya karena alasan kemanusiaan.
Sudah berapa lama aku kehilangan Kenji? Lima belas tahun? Entahlah, aku tak bisa mengingatnya dengan pasti. Hanya dua tahun kami saling mengenal, tapi rasanya sudah kenal seumur hidup. Selama di SMA, ia lah yang menuntunku ke jalan yang lebih baik. Bahkan setelah kepergiannya, aku masih merasa kalau Kenji ada di sekitarku. Kasus Wijaya ini menjadi salah satu buktinya, walau sebenarnya aku tidak terlalu percaya dengan hal yang berbau mistis. Orang yang meninggal akan hidup di alam lain yang berbeda dimensi dengan kita.
Ataukah sebenarnya energinya masih ada di dunia ini, berusaha mencegahku untuk melakukan hal-hal bodoh seperti tadi?
TAMAT
Leon dan Kenji (Buku 2)
Chapter 90 Menemukan Arah
Published
4 tahun agoon
29 Desember 2020By
Fanandi
Lima belas tahun berlalu begitu saja. Lebih dari setengahnya kuhabiskan untuk belajar mati-matian di universitas agar bisa segera lulus dan menjadi seorang dokter. Aku kerap mendapatkan sorotan berkat berbagai prestasi akademik yang pernah kuraih. Aku berhasil menjadi lulusan sarjana terbaik dengan waktu tercepat. Program profesi dokter dan ujian sertifikasi kulibas dalam waktu kurang dari satu setengah tahun. Magang juga kulalui dengan lancar hingga aku berhasil mendapatkan izin praktik. Aku tidak berhenti di situ. Aku mengambil program profesi spesialis paru-paru dan berhasil kuselesaikan dalam waktu empat tahun. Begitu semua kuselesaikan, aku kembali Malang dan menekuni profesi ini secara profesional.
Harga yang kubayar untuk bisa mendapatkan itu semua tidaklah murah. Aku sama sekali tidak pernah ikut kegiatan kampus yang bersifat non-akademik. Kepanitiaan apapun tidak pernah menarik minatku. Teman seperti masa-masa SMA? Hampir tidak ada. Sampai-sampai aku mendapatkan julukan robot karena rutinitasku yang selalu berulang-ulang. Aku mengetahui ini dari Rachel, yang kebetulan menjadi adik tingkatku karena ia mengambil jurusan yang sama di kampus yang sama. Aku tidak terlalu memedulikan hal tersebut. Aku harus fokus dengan tujuanku.
Karena keseriusanku di masa-masa kuliah, karirku dengan cepat melambung. Namaku terkenal sebagai salah satu dokter paru-paru terbaik. Banyak rumah sakit besar dari luar daerah yang berusaha meyakinkan aku untuk pindah, namun aku memutuskan untuk bertahan di rumah sakit ini, rumah sakit yang menjadi saksi kepergian Jessica dan Kenji.
***
Aku mendengar kematian Kenji dari Rika, ketika aku sedang disibukkan dengan berbagai kegiatan OSPEK yang bagiku cukup menjemukan. Diawali dengan isak tangis, Rika memberitahu kabar duka tersebut dengan suara terpatah-patah.
“Kenji Le… Kenji meninggal. Penyakit paru-parunya ditambah kompilasi penyakit lain membuatnya enggak ketolong.”
Handphoneku langsung tergelincir jatuh begitu saja ke lantai kamar asramaku. Aku yang sedang melakukan persiapan untuk acara kampus besok langsung terduduk di atas tempat tidur. Aku masih tidak percaya dengan kabar yang baru kudengar. Perlahan, air mataku tumpah tanpa bersuara. Aku menangis dalam sunyi. Aku tak menyangka, aku harus kehilangan sahabat terbaikku ketika aku harus jauh darinya. Ketakutan terbesarku benar-benar terjadi.
Entah berapa lama aku terjebak dalam perasaan sedih ini. Omongan-omongan kakak tingkat yang menyakitkan sama sekali tidak kudengarkan. Beberapa kali mendengar teguran hanya kudengarkan dengan tatapan kosong. Menyadari ada yang ganjil dari diriku, aku dipanggil oleh pihak kampus. Di hadapanku, terlihat seorang wanita berusia 30-an dengan rambut sebahu.
“Ah, kamu Leon, kan? Silakan masuk. Saya sudah nunggu kamu.”
Perasaan dipanggil ini sama seperti waktu aku pertama kali masuk ke SMA, di mana aku dipanggil oleh guru BP. Kesan awalnya pun sama, pribadi yang ramah namun menyimpan belati tajam di belakang punggungnya.
“Saya dapat beberapa laporan dari katingmu, katanya akhir-akhir ini kamu seperti kurang fokus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Kamu ada masalah?”
Aku memutuskan untuk bercerita apa adanya, berharap hal tersebut bisa membantuku merasa lebih baik.
“Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan kabar kalau sahabat yang sudah seperti saudara saya sendiri meninggal karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Saya minta maaf, karena itu saya sering tidak fokus.”
Mendengar kabar tersebut, wanita tersebut memberikan pandangan penuh simpati. Ketulusan terpancar dari kedua bola matanya.
“Kamu harusnya bilang agar mendapatkan izin untuk pulang. Rumah kamu di mana?”
“Malang.”
“Setidaknya ambil izin tiga sampai empat hari, saya sarankan naik pesawat supaya lebih cepat.”
“Tidak perlu bu.”
“Kamu enggak mau melayat sahabatmu itu? Mau gimanapun, kehilangan orang yang berharga itu menyakitkan, loh.”
Aku mengambil jeda sejenak sebelum merespon pertanyaan tersebut.
“Saya mau membuat sumpah untuk tidak kembali ke Malang sebelum berhasil menjadi dokter. Mau sepuluh tahun pun akan saya jalani. Saya harus segera lulus demi dia, demi mereka.”
Wanita tersebut nampaknya berusaha memahami posisiku. Ia terlihat sedang menuliskan semacam catatan di atas meja kerjanya.
“Ibu hargai jika keputusanmu seperti itu. Setidaknya, kamu bisa absen beberapa hari untuk menenangkan diri. Ibu akan kirim memo kepada katingmu yang jadi panitia. Tiga hari cukup?”
Aku menganggukkan kepala, meskipun tahu tiga hari tidak akan cukup untuk membuatku merasa lebih baik.
***
Setelah mendapatkan telepon dari Rika, handphoneku kubiarkan mati selama berhari-hari. Aku sadar tindakan tersebut sangat egois karena pasti banyak yang mengkhawatirkan diriku. Orang pertama yang kuhubungi adalah ayah.
“Leon? Kamu kok baru bisa dihubungi sekarang? Semuanya kepikiran sama kamu, paman bahkan bilang kalau Sabtu besok ini mau ke Jakarta lihat kamu.”
“Gisel mana?” tanyaku tanpa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan. Ayah pun memutuskan untuk tidak mendebatku dan segera memanggil Gisel.
“KAKAK! Kakak ke mana aja? Gisel kepikiran kakak terus gara-gara…” Gisel tidak bisa melanjutkan kalimatnya karena ia mulai menangis. Aku pun semakin merasa bersalah karena sudah menyusahkan orang lain seperti ini.
“Maafkan kakak, Gisel. Kakak butuh waktu buat menenangkan diri.”
“Iya sih Gisel tahu, tapi tetap aja Gisel panik. Gisel takut kakak kenapa-napa.”
“Kakak enggak apa-apa Gisel, kakak minta maaf, ya. Kakak sudah bikin kamu kepikiran. Padahal Gisel lagi seneng-senengnya karena masuk SMP, kan?”
Rekomendasi langsung naik ke kelas enam yang diterima Gisel tahun kemarin membuatnya tahun ini bisa masuk ke SMP. Nilai ujiannya menjadi yang tertinggi, hampir sempurna. Di antara teman-teman SMP-nya, Gisel pasti menjadi yang paling muda.
“Gimana mau seneng kak kalau Kak Kenji…” sekali lagi Gisel tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Aku pun berusaha menenangkannya sebisa mungkin. Sama sekali tidak kuungkit masalah rencanaku untuk tidak pulang sebelum lulus. Hal tersebut bisa dibicarakan lain waktu.
Setelah Gisel, orang berikutnya yang kuhubungi adalah paman. Rencananya untuk ke Jakarta harus dibatalkan. Begitu telepon tersambung, aku segera dicecar oleh berbagai pertanyaan. Aku pun mengatakan kalau aku baik-baik saja walau sempat terguncang hebat. Setelah mendengarkan berbagai nasihat, aku mengakhiri telepon.
Orang terakhir yang kuhubungi adalah Rika. Aku yakin kalau diriku akan mendengar omelan yang lebih pedas dari dua telepon sebelumnya.
“Halo, Ri…”
Belum berakhir sempurna pertanyaanku, Rika sudah mengeluarkan kalimat-kalimat dengan cepatnya. Suaranya benar-benar mengandung emosi yang bercampur aduk. Aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyelanya. Dengan sabar, aku menantinya selesai bicara.
“Kamu itu egois banget Leon, enggak mikirin orang-orang yang ada di sini,” akhirnya Rika selesai berbicara.
“Iya, maaf Rika. Aku memang salah.”
“Kamu enggak pulang?”
“Kayaknya enggak Rika. Aku…”
Kalimatku kubiarkan menggantung. Aku belum siap memberitahunya. Berbeda dengan paman dan Gisel yang bisa datang berkunjung ke Jakarta, Rika belum tentu punya kesempatan untuk itu.
“Aku tahu Le, kamu pasti sangat terpukul dengan kepergian Kenji. Tapi kamu harus tahu kalau kami semua juga ikut terpukul. Kenji itu figur penting di kelas kita, bahkan di sekolah kita. Kemarin waktu pemakamannya banyak yang datang.”
Mendengar cerita pemakaman Kenji, aku menjadi terdiam. Rika menyadari kesalahannya berusaha meminta maaf dengan sedikit panik.
“Iya, enggak apa-apa Rika, tapi maaf, aku benar-benar belum bisa pulang sekarang. Suatu saat, aku akan kasih tahu kamu alasannya.”
“Iya Leon, aku mengerti.”
Telepon berakhir. Aku kembali disibukkan oleh berbagai pikiran tentang Kenji dan mengingat-ingat berbagai momen yang pernah kami lalui bersama.
***
Setelah aku mulai berkuliah di Jakarta, Zane dan timnya mulai berhasil membongkar banyak kejahatan yang dilakukan oleh Wijaya dan kroninya. Banyak orang yang berhasil ditangkap dengan berbagai tuduhan. Perusahaannya banyak yang dinyatakan bangkrut atau setidaknya diakuisisi oleh pihak lain. Sayang, Wijaya tetap tak tersentuh. Petunjuk seputar di mana ia berada benar-benar minim. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak mengetahui pasti keberadaannya. Awalnya aku sulit menerima kenyataan ini, tapi aku memutuskan untuk berusaha mengikhlaskannya. Siapa tahun ia telah mati, dan aku harap ia mati dengan mengenaskan.
Aku tetap tidak mengetahui keberadaan orangtua kandungku atau setidaknya makam mereka. Daftar orang-orang Peretas yang hilang juga tidak ada satupun yang berhasil ditemukan. Semuanya tetap menjadi misteri.
Walaupun begitu, aku selalu teringat kata-kata Kenji. Semua yang aku alami ini membuatku bisa menemukan arah yang selama ini kucari. Kematian Sica, lalu disusul kematian Kenji sendiri, membuatku termotivasi untuk menjadi dokter spesialis paru-paru. Setelah tahun-tahun penuh perjuangan dan pengorbanan, aku berhasil mencapainya. Aku bisa menolong orang lain dengan kemampuan yang kumiliki. Ketika melihat pasienku bisa kembali hidup normal, aku merasa bahagia. Aku merasa kehidupanku memiliki manfaat untuk orang lain.
***
Kembali ke masa kini. Aku sedang bersiap untuk melayani seorang pasien yang sudah cukup tua. Kata asistenku, usia pasien ini sudah lebih dari 90 tahun. Kompilasi penyakit yang diderita cukup banyak, namun yang paling vital adalah paru-parunya. Oleh karena itu, keluarganya memutuskan untuk membawanya untuk diperiksa olehku. Aku memintanya untuk memasukkan pasien tersebut ke ruang praktikku. Pihak keluarga hanya boleh menunggu di luar karena aku akan melakukan pemeriksaan secara mendalam.
Sepuluh menit kemudian, aku berjalan ke ruang praktik. Aku sempat bertemu dengan pihak keluarganya, mungkin anak dan cucunya. Aku menyempatkan diri untuk sedikit berbasa-basi dengan mereka agar mengetahui riwayat penyakitnya. Mereka mengatakan kalau selama ini mereka tinggal di luar negeri. Sang pasien selama ini bisa menjaga pola hidup yang sehat sehingga bisa berusia panjang. Karena masalah ekonomi, mereka memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berusaha hidup dengan tenang.
Setelah itu, aku memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan untuk segera memeriksan sang pasien. Di dalam, ia ditemani oleh asistenku. Aku pun menghampiri sang pasien dan berusaha beramah-tamah seperti biasanya. Namun, ketika memperhatikan wajahnya secara saksama, aku merasa mengenali wajah itu. Aku berusaha mengorek ingatanku dalam-dalam untuk mengetahui siapa yang ada di hadapanku ini.
Aku ingat siapa dia.
“Flo, bisa tinggalkan kami berdua?”
Asistenku yang bernama Florence itu mematuhi permintaanku tanpa banyak tanya. Setelah ia menutup pintu dengan pelan-pelan, aku segera menatap mata sang pasien.
“Wijaya Hardikusuma.”
Reaksi yang ia tunjukkan benar-benar sesuai dugaanku. Sangat terkejut. Aku tahu ia telah mengubah identitas dirinya agar tidak tersentuh hukum. Tapi aku ingat segala lekuk wajah Wijaya dari foto yang pernah ditunjukkan oleh Zane. Meskipun usianya di foto dengan yang sekarang terpaut cukup jauh, aku masih bisa mengenalinya berkat daya ingat otakku yang luar biasa.
“Si…siapa kamu?” tanya Wijaya dengan gemetar.
“Well, nama saya adalah Alexander Napoleon Caesar dan saya adalah dokter yang akan segera memerika Anda. Tapi apakah Anda merasa pernah mengenal saya?”
Ia menggelengkan kepala dengan lemah.
“Tentu saja Anda tidak kenal saya karena kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Tapi saya tahu semua kejahatan yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Ingat dengan kelompok Pembela Rakyat Tertindas yang sangat menentang proyek-proyek Anda?”
Tatapannya memancarkan ketakutan. Ia pasti tak menyangka akan bertemu dengan orang yang memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.
“Saya adalah anak dari Ratih dan Bambang, ingat dengan nama itu? Mungkin tidak mengingat banyak sekali orang yang Anda hilangkan. Ingat Dewi? Dia juga anggota kelompok itu dan dengan baik hati mau mengadopsi saya sebagai anak setelah orangtua kandung saya dihilangkan oleh Anda. Tapi beberapa tahun kemudian ketika saya baru masuk SMP, saya menemukan ibu angkat saya gantung diri. Ketika SMA, saya mengetahui fakta kalau kematiannya ternyata rekayasa yang direncanakan oleh anak buahmu. Pasti Anda tahu Markus, bukan? Ia sudah mengakui semuanya, sebelum akhirnya ia meninggal di dalam penjara.”
Aku berjalan mendekati lemari buku yang ada di dekat meja kerjaku. Aku selalu menyimpan beberapa novel Agatha Christie sebagai hiburan ketika merasa penat. Aku mengambil satu secara acak dan kembali menghampiri Wijaya yang masih di dalam posisi berbaring.
“Ibu saya sangat menyukai novel-novel detektif seperti ini, bahkan ia menggunakannya sebagai petunjuk untuk membongkar kebusukanmu. Kesukaannya itu menurun kepada saya. Entah sudah berapa ratus judul yang sudah saya baca. Dari sana, saya mengetahui beberapa trik pembunuhan yang tidak akan ketahuan. Menurut Anda, bagaimana jika saya mempraktekkan beberapa di antaranya kepada Anda?”
“Tolong, tolong ampuni saya…” pinta Wijaya dengan suaranya yang lemah.
“Bertahun-tahun saya hidup menderita karena perbuatan Anda. Lantas, Tuhan membuat kita bisa bertemu dalam kondisi seperti ini, saat Anda tidak berdaya. Menurut Anda, saya akan melepaskan kesempatan terbaik untuk balas dendam begitu saja?”
Tubuh Wijaya makin bergetar tak karuan. Kata-kata ampun dan maaf terus keluar dari mulutnya. Untunglah ia terlalu lemah untuk berteriak sehingga keluarganya yang sedang menanti di luar tidak akan mendengar suaranya.
Apakah aku benar-benar serius ingin membunuhnya sekarang? Oh ya, aku sangat serius. Bahkan aku sudah mempertimbangkan beberapa cara untuk membuatnya mati di tanganku. Menutup kepalanya dengan bantal hingga ia tak bisa bernapas? Menyuntikkan cairan tak terdeteksi yang akan memperparah sakit di tubuhnya? Berbagai cara melintas di kepalaku sembari mataku menatapnya dengan penuh dendam. Sama sekali tidak ada belas kasihan yang muncul dari diriku. Siapa yang menyangka keputusanku untuk menjadi dokter spesialis paru-paru akan membuatku bertemu dengannya.
Aku terus memadanginya, memandanginya dengan tatapan penuh kebencian. Kenji, balas dendam kita akan tuntas hari ini. Orang yang selama ini membuat hidup kita menderita akhirnya akan mendapatkan pembalasan.
Aku masih terus memandanginya tanpa bersuara sedikitpun.
Leon dan Kenji (Buku 2)
Chapter 89 Keberangkatan
Published
4 tahun agoon
7 Desember 2020By
Fanandi
Aku mendapati diriku sedang berada di ruang serba putih yang sama seperti waktu aku bertemu dengan ibu. Meskipun kepalaku terasa sedikit sakit, aku memutuskan untuk berdiri dan mulai mencari seseorang di ruangan ini. Semoga saja aku bertemu dengan ibu lagi. Sejak kunjunganku terakhir ke sini, ada banyak kejadian yang telah terjadi. Aku ingin menceritakan semuanya agar merasa lega.
Tiga puluh menit aku berjalan tanpa arah, tak kutemukan seorang pun di sini. Aku pun menjadi khawatir, apakah aku berada di ruangan lain? Apakah aku tak akan bertemu dengan seorang pun di sini?
Di saat aku mulai merasa putus asa, aku melihat siluet seorang wanita dari kejauhan. Dari postur tubuhnya, dia jelas bukan ibuku. Aku memutuskan untuk menghampirinya. Ketika jarak kami tinggal tiga meter, aku menyadari siapa pemiliki siluet tersebut.
“Sica.”
Mendengar namanya dipanggil, ia menoleh ke arahku. Benar, ia adalah Sica. Lututku langsung lemas dan akupun jatuh bersimpuh di hadapannya. Ia terkejut melihatku dan segera berusaha menolongku untuk berdiri kembali.
“Leon? Enggak apa-apa? Sakit loh jatuh seperti itu.”
Mendengar suaranya, air mataku tumpah begitu saja. Sica dengan sabar menungguku selesai.
“Aku enggak nyangka Le kita bisa ketemu di sini. Aku sendiri kurang tahu ini di mana.”
Aku sama sekali tidak memberikan respon. Aku sibuk menguasai diri yang begitu terkejut bertemu dengan seorang wanita yang berpengaruh besar di dalam kehidupanku.
“Kita jalan dikit yuk, tadi di sana aku lihat ada kayak bangku taman gitu. Kita ngobrol di sana aja.”
Kami berdua pun berjalan beriringan dalam diam hingga sampai di bangku yang ia maksud. Kami duduk di atasnya dan saling menanti saat yang tepat untuk memulai percakapan.
“Udah satu tahun ya Le kita enggak ketemu? Ada cerita apa aja?”
Aku sudah mulai bisa menguasai diri. Aku pun memutuskan untuk menceritakan semua kejadian semenjak hari kematiannya, mulai dari kedatangan ayahku yang tiba-tiba, kedekatanku dengan Rika, hubungan antara ibuku dengan ibunya Kenji, fakta kalau selama ini aku tinggal bersama orangtua angkat, hingga kasus masa lalu yang sedang aku hadapi. Sica mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa berusaha menyela sedikitpun.
“Dan kini Kenji sedang terbaring di rumah sakit. Sama sepertimu, penyakit paru-paru. Belum diketahui kapan ia bisa keluar,” aku mengakhiri ceritaku.
“Aku turut sedih mendengarnya, Le. Kamu udah mengalami berbagai kejadian yang belum tentu bisa dihadapi oleh orang biasa. Kamu hebat Le bisa melalui ini semua.”
“Terima kasih Sica.”
Tidak ada lagi kalimat yang meluncur dari bibir kami berdua, seolah kami sedang menikmati sunyi yang ada di sekeliling kami. Aku tahu ini hanya mimpi, sama seperti sebelumnya. Tapi mimpi seperti ini selalu terasa sangat nyata.
“Aku yakin semua yang kamu alami itu punya hikmahnya masing-masing, Le. Aku yakin semua tidak terjadi secara percuma,” kata Sica pada akhirnya.
“Iya, terima kasih.”
“Kamu lanjut kuliah di mana?”
“UI, jurusan Kedokteran.”
“Wah, keren. Saingannya dari seluruh negeri loh itu.”
“Aku mengambil jurusan tersebut juga karena kau, Sica.”
“Iya, aku paham. Ingin membuktikan diri lebih hebat dari dokter sombong yang waktu itu merawatku, kan?”
Aku menganggukkan kepala.
“Kamu menemukan arah hidupmu setelah kematianku. Pertemuan dengan ayahmu membuatmu dekat dengan Rika. Rika jugalah yang banyak membantumu menguak misteri dari masa lalu orangtuamu. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut, Le.”
“Aku takut Sica.”
“Takut apa?”
“Aku takut kehilangan Kenji, seperti aku kehilanganmu.”
Sica terdiam mendengar kalimatku. Ia membuang pandangannya dan memain-mainkan kakinya.
“Umur enggak ada yang tahu, Le. Udah diatur sama Tuhan.”
Mendengar kalimat itu, aku menutup mukaku dengan kedua tangan. Aku kembali menangis, kali ini lebih keras. Sica berusaha menenangkan diriku dengan memegang pundakku.
“Takut kehilangan itu sangat manusiawi kok, Le. Apalagi hubunganmu dengan Kenji sudah seperti keluarga sendiri. Percaya semua akan baik-baik aja. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik untukmu.”
Pegangan Sica tiba-tiba tak terasa. Ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihatnya mulai memudar seperti yang terjadi pada ibu waktu itu. Sica akan lenyap dari hadapanku dan aku akan kembali ke dunia nyata.
“Aku setuju kamu sama Rika, Le. Kalian berdua cocok satu sama lain karena bisa saling melengkapi,” kata Sica sebelum benar-benar menghilang. Setelah itu, semuanya gelap.
***
Hari demi hari berlalu dengan cepat, hingga tak terasa hari keberangkatanku ke Jakarta telah tiba. Selama itu pula, Kenji masih berada di rumah sakit tanpa tahu kapan bisa keluar. Kasus yang sedang diusut Zane mengalami perkembangan yang lambat. Hanya ada beberapa nama yang mulai diselidiki, sedangkan Wijaya benar-benar tak tersentuh. Aku mulai merasa kalau penyelidikan yang selama ini kulakukan menjadi percuma, meskipun aku jadi mengetahui banyak cerita tentang orangtuaku.
Aku menyetujui usul paman, Gisel akan kembali tinggal bersama ayah selama aku studi di Jakarta. Kemarin, ia datang membawa satu tas koper yang berisikan barang pribadinya.
“Besok kita semua akan antar kamu ke bandara ya, Le. Nanti di Jakarta ada teman paman yang bakal jemput kamu dan untuk sementara kamu tinggal di rumahnya. Enggak usah merasa sungkan, teman paman itu udah kayak saudara sendiri,” kata paman kemarin sore sewaktu kami berkumpul di ruang keluarga. Ayah juga ada di sana, wajahnya tak sesuram biasanya. Justru Gisel yang terus memasang wajah murung, membayangkan dirinya akan berpisah dengan kakak tersayangnya.
Aku sadar kalau aku butuh bicara dengan Gisel empat mata. Malamnya, aku datang ke kamarnya. Ia sedang meringkuk di atas tempat tidur, tapi aku tahu ia tidak bisa tidur. Aku pun duduk di dekatnya.
“Gisel, besok kakak berangkat ya. Gisel jaga diri sama ayah. Kalau ada apa-apa, jangan ragu buat telepon kakak.”
Tidak ada tanggapan dari Gisel.
“Kakak tahu Gisel pasti sedih karena harus pisah sama kakak untuk waktu yang lama, tapi Gisel harus percaya kalau kakak pasti kembali untuk Gisel.”
Masih belum ada tanggapan.
“Gisel, kakak makin enggak tega buat ninggal kamu kalau kamu terus kayak gini. Kakak butuh Gisel melepas kakak dengan ikhlas. Kakak enggak bakal bisa fokus belajar kalau Gisel seperti ini.”
Akhirnya Gisel bangun dan menatap wajahku. Ternyata, dari tadi air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Melihat itu, aku segera merangkul Gisel dan melepaskan segala bentuk emosi yang ada di dalam diriku. Gisel tetap tidak memberikan tanggapan apapun, tapi aku mengerti kalau ia pelan-pelan berusaha melepas kepergianku.
***
Keesokan paginya, aku mendapatkan kejutan. Semua teman kelasku, kecuali Kenji yang masih di rumah sakit, datang berkunjung. Ternyata mereka semua ingin memberikan semacam salam perpisahan. Aku pun meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, kami bercerita banyak sekali hal. Mereka berusaha membuat suasana tetap ceria meskipun di dalam hati ada perasaan sedih yang sedang disembunyikan. Hanya Rika yang dari tadi diam walau sesekali berusaha membuat senyum di bibirnya.
“Rika,” panggilku ketika yang lain sedang asyik bercanda. Kebetulan, ia duduk di sebelahku.
“Iya Le.”
“Jangan sedih ya, kita masih bisa sering kontakan kok. Kita pasti akan ketemu lagi.”
“Iya Le.”
Aku pun membelai lembut rambutnya. Tangis yang berusaha ia tahan dari tadi akhirnya tumpah. Teman-teman lain seperti Rena dan Sarah berusaha menenangkan Rika. Sama seperti Gisel, aku juga sangat berat meninggalkan Rika, wanita hebat yang selama ini telah sabar berada di sisiku melewati berbagai macam ujian yang kuhadapi.
***
Diantar oleh paman, aku menjenguk Kenji untuk terakhir kalinya sebelum berangkat ke bandara. Aku harus berpamitan dengan kawan terbaikku itu.
“Kenji, gimana kondisimu?” tanya paman yang baru kali ini menjenguknya.
“Makin hari makin baik kok paman, terima kasih,” jawab Kenji dengan ceria seperti biasa.
“Hari ini Leon berangkat ke Jakarta, jadi dia mau pamitan sama kamu.”
Setelah itu. paman meninggalkan kami berdua. Aku mengambil posisi duduk di sebelahnya. Wajahnya terlihat sangat tegar, meskipun aku tahu ia juga merasa berat harus berpisah denganku untuk jangka waktu yang lama.
“Sudah waktunya ya, Le?”
“Iya Kenji.”
“Sukses terus ya, semoga kamu bisa menyelesaikan studi dengan cepat. Tahu sendiri kan kalau jurusan Kedokteran menjadi salah satu yang paling sulit untuk lulus? Tapi dengan kemampuanmu, aku yakin kamu bisa lulus cepat.”
“Iya Kenji, terima kasih.”
“Waktu berlalu begitu cepat ya. Kayaknya baru kemarin aku menyapamu di hari pertama MOS. Sekarang kita semua udah lulus dan akan berusaha menggapai impiannya masing-masing. Aku pengen cepet-cepet keluar dari rumah sakit, pengen segera mulai bikin tempat kursus! Hahaha.”
“Iya Kenji, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa.”
Setelah itu, hening menghampiri kami. Aku sadar dari tadi, Kenji sedang mengenakan topeng untuk menyembunyikan perasaannya. Meskipun wajahnya terlihat ceria, ada campuran antara perasaan cemas dan takut di dalam hatinya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
“Kau harus melihatku berhasil menjadi dokter, Ken. Harus,” kataku pada akhirnya.
“Semoga Le, aku pun ingin melihat kamu di puncak kesuksesan. Wah, aku sudah bisa membayangkan kamu mengenakan pakaian dokter, pasti terlihat keren. Sungguh Le, aku ingin melihatnya.”
Lagi-lagi air mataku menetes begitu saja. Perpisahan dengan Kenji ini entah mengapa terasa begitu berat. Ada banyak sekali yang ingin kusampaikan kepadanya, dan mungkin ini kesempatan terakhirku sebelum aku pergi merantau.
“Aku ingin berterima kasih untuk semuanya, Ken. Entah berapa banyak jasamu di dalam kehidupanku. Kau sudah mengeluarkanku dari neraka itu dan menuntunku menjalani hidup yang lebih baik. Aku benar-benar berhutang banyak padamu, dan aku belum pernah sempat membayar hutang tersebut.”
“Ah, jangan dipikirkan Le. Yang namanya saudara memang seperti itu, bukan? Aku sama sekali tidak pernah mengharapkan timbal balik dalam bentuk apapun Le, kamu pun sudah banyak membantuku. Kamu sudah membuatku merasa memiliki keluarga, kamu membuatku tahu lebih banyak tentang ibuku. Jadi, anggap aja kita impas, ya?”
Aku menganggukkan kepala. Lantas, paman kembali masuk ke dalam ruangan dan memberitahuku kalau sebentar lagi waktunya berangkat. Aku menarik napas panjang dan bangkit dari kursiku. Aku menggenggam tangan Kenji dengan kedua tanganku.
“Kenji, aku berangkat ke Jakarta. Semoga kau lekas sembuh dan bisa memulai impianmu membuka tempat kursus. Aku yakin, kau akan melihatku menjadi seorang dokter yang handal. Aku ingin kau percaya denganku.”
“Aku selalu percaya kamu kok, Leon,” kata Kenji sambil memberikan senyuman khasnya, senyum terakhir yang aku lihat dari dirinya.
***
Tiga minggu kemudian, di saat aku disibukkan dengan berbagai kegiatan OSPEK kampus, aku mendengar kabar kalau Kenji, sahabat sekaligus saudara terbaikku, pergi untuk selamanya.

Ketika Pengakuan Sosial Menjadi Kebutuhan Pokok

Cara Saya Hilangkan Kebiasaan Buruk Dikit-Dikit Cek HP

Kemenangan Perdana yang Awkward Bagi Oscar Piastri di Formula 1

Yu-Gi-Oh!: Komik, Duel Kartu, dan Nostalgianya

Koleksi Board Game #21: Century: Spice Road

Koleksi Board Game #14: Kakartu Se-kata

Asa Leverkusen untuk Mengejar Status Invincibles Sempurna

Badai Cedera Manchester United yang Tak Kunjung Berlalu

[REVIEW] Setelah Membaca Twenty-Four Eyes: Dua Belas Pasang Mata

Artikel pada Tulisan Ini Dibuat Menggunakan AI (ChatGPT)
Tag
Fanandi's Choice
-
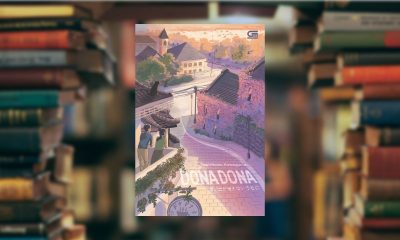
 Buku4 bulan ago
Buku4 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Dona Dona
-

 Fiksi3 bulan ago
Fiksi3 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Keajaiban Toko Kelontong Namiya
-

 Permainan3 bulan ago
Permainan3 bulan agoKoleksi Board Game #14: Kakartu Se-kata
-

 Permainan4 bulan ago
Permainan4 bulan agoKoleksi Board Game #13: Coup
-

 Olahraga4 bulan ago
Olahraga4 bulan agoKenapa Fans Manchester United Banyak yang Sombong?
-

 Anime & Komik5 bulan ago
Anime & Komik5 bulan agoTerima Kasih, Akira Toriyama, Selamat Jalan
-

 Anime & Komik4 bulan ago
Anime & Komik4 bulan agoBagaimana Mr. Satan (Benar-Benar) Menyelamatkan Dunia Dua Kali
-

 Musik5 bulan ago
Musik5 bulan agoBagaimana Algoritma YouTube Music Membuat Saya Menyelami K-Pop
