Setelah bersiap diri dan mempersiapkan Gisel yang juga sangat antusias untuk mengunjungi “kakak cantik”, kami berdua berjalan menuju rumah sakit yang merawat Sica. Sebelum pulang sekolah tadi, aku sudah bertanya kepada Gita di mana rumah sakitnya dan bagaimana caranya ke sana. Gita berkata kami hanya perlu naik angkutan umum sekitar 5 menit, lalu bilang supirnya berhenti di rumah sakit Lawang. Perlu diketahui, ini adalah pertama kalinya aku, dan mungkin Gisel, naik kendaraan umum yang disingkat angkot ini.
Melalui terowongan kecil tadi, kami sudah berada di pinggir jalan raya. Aku perhatikan orang-orang yang nampaknya juga menunggu kendaraan ini. Setelah dari jarak 100 meter terlihat ada kendaraan butut berwarna hijau, beberapa dari mereka melambai-lambaikan tangan ke depan. Mungkin itu caranya mencegat angkot ini.
Setelah berhenti, kami pun turut masuk ke dalam kendaraan hijau ini. Ternyata, di dalam angkot kami akan duduk dengan saling berhadap-hadapan. Selain itu, terasa sekali sempitnya jika penumpang penuh. Angkot yang kunaiki ini sudah terisi tujuh orang belum termasuk diriku, sehingga aku duduk dengan posisi memangku Gisel dan menghadap belakang.
“Adiknya kelas berapa nak?” salah satu ibu-ibu yang duduk di sebelah kiriku bertanya, dan aku pun bingung bagaimana menjawabnya. Melihat aku tidak segera menjawab, Gisel mengambil inisiatif.
“Gisel belum sekolah bu, Gisel dulu ditolak sama pihak sekolah.”
Seketika, sorot mata itu muncul lagi, sorot mata yang kubenci. Sorot mata yang meremehkan, sorot mata yang menusuk, sorot mata yang menghina. Meskpiun hanya dalam sekejap mereka ganti dengan senyum manis palsu yang mengeluarkan suara-suara penghiburan, aku tidak akan melupakan sorot-sorot memuakkan itu. Aku yakin, ketika kami nanti turun dari angkot, mereka akan membicarakan keburukan ini. Dasar munafik.
Aku terlalu sibuk dengan kebencian terhadap sorot mata itu, hingga aku lupa bilang ke supir di mana akan berhenti.
“Rumah sakit Lawang pak.” kataku dengan menoleh sedikit ke supir.
“Lah, wes lewat le. Berhenti di depan ya, nanti naik angkutan yang ke arah sebaliknya.”
Sial, gara-gara para ibu-ibu ini, aku jadi rugi sekian rupiah.
***
Setelah naik angkot lagi dan tidak lupa menyampaikan tujuan ketika duduk, akhirnya aku sampai ke tujuan. Rumah sakit yang bagus, aku suka dengan desainnya, mungkin mahal jika ingin berobat disini. Kutanya kepada security yang sedang bertugas di pos satpam, di mana jika aku ingin bertanya tentang ruangan pasien. Ia menjawab langsung saja masuk ke dalam, tanya ke resepsionis. Maka masuklah aku ke dalam rumah sakit.
Aku merasa sedikit dejavu ketika berdiri di depan rumah sakit ini, dan dejavu tersebut semakin terasa ketika aku memasuki lobi. Aku merasa sangat yakin, bahwa aku pernah mengunjungi rumah sakit ini, namun aku tidak ingat kapan dan mengapa. Gisel menarik-narik tanganku agar tidak bengong di depan pintu lobi.
Kudapatkan informasi dimana Sica dirawat, di ruang Sakura 2. Nama yang indah untuk sebuah kamar rumah sakit. Setelah tanya kesana kemari, akhirnya kutemukan juga. Dengan mengetuk pintu, aku masuk ke dalam Sakura 2.
Kamar ini ternyata tidak hanya berisikan Sica, karena terdapat 4 ranjang, dimana dua di sisi kananku dan dua di sisi kiriku. Kutengok satu persatu untuk mencari Sica, dan ternyata ia ada di ranjang kedua di sisi kanan.
Sica tidak sendirian, ia ditemani oleh seorang ibu yang seolah-seolah beliau adalah Sica dari masa depan. Ternyata kecantikan Sica menurun dari ibunya. Dan yang lebih membahagiakan lagi, Sica sudah sadar. Ketika ia menyadari kehadiranku, ia tersenyum lemah memandangku. Entah kelihatan atau tidak, aku merasa bergetar begitu kencangnya seolah-olah sedang berdiri diatas alat pijat refleksi. Aku tidak tahu mengapa aku bergetar demikian kencangnya, antara senang melihat senyumnya atau karena sedih melihat kondisi Sica yang menyedihkan.
Ibunda Sica yang turut sadar akan kehadiranku langsung berdiri mengulurkan tangannya. Sebagai anak yang sedang berusaha untuk sopan, aku meraih tangannya dan melakukan salim, begitu pula Gisel. Setelah perkenalan singkat, kami pun mulai bercakap-cakap.
“Mulai lahir, Sica memang ada sedikit kelainan di paru-parunya. Karena itu pula, ia memiliki asma, dan apabila ia terlalu menguras tenaga, ia bisa batuk berdarah dan kehilangan kesadaran. Ibu langsung panik begitu mendengar kabar dari sekolah, untung saja sekolah bertindak cepat dengan membawanya ke UGD. Dulu sebelum ini Sica juga pernah pingsan sewaktu menjadi panitia di SMPnya dulu.”
“Tapi sekarang Sica sudah tidak apa-apa kan bu?”
“Puji Tuhan sudah baikan, kemarin malam sudah sadar. Sekarang cuma butuh istirahat saja sebelum kembali bersekolah.”
“Tapi kak Sica meskipun sakit tetep cantik kok tante.” Gisel dengan polosnya ikut dalam pembicaraan. Kami pun hanya tertawa kecil mendengar Gisel. Kulirik Sica, ia juga sedang tersenyum. Sayangnya, itu adalah senyum yang mengandung kepedihan.
Tiba-tiba terdengar dering handphone berbunyi, yang ternyata berasal dari handphone milik ibunda Sica. Dengan permisi, ia bangkit untuk mengangkat telepon, meninggalkan kami bertiga. Aku memutuskan duduk di kursi tadi untuk bercakap dengan Sica.
“Hai Sica, gimana keadaanmu?”
Dengan suara lirih, Sica mencoba menjawab sebisanya.
“Baik Le, cuma butuh istirahat aja.”
“Kemarin anak-anak kesini, tapi sayangnya kau masih belum sadarkan diri.”
“Oh iya? Sayang sekali. Apa kamu juga ke sini kemarin Le?”
“Tidak Sica, aku tidak ikut.”
“Mana Kenji? Biasanya kalian selalu berdua.”
Aku terdiam mendengarkan pertanyaan Sica. Apakah aku harus menutup-nutupi hilangnya Kenji, atau jujur apa adanya? Akhirnya, hatiku memilih untuk berkata jujur karena yakin Sica kuat untuk menghadapi kenyataan.
“Sebenarnya, Kenji menghilang sejak kau pingsan Sica. Begitupula Sarah. Kami satu kelas sudah berusaha mengumpulkan informasi, namun hasilnya masih nihil.”
Sica memandangku dengan tatapan paling merana yang pernah kulihat darinya. Aku tidak sanggup untuk menerima tatapan itu, maka kupalingkan mukaku ke Gisel. Gisel membalas tatapanku dengan wajah simpati.
“Sarah pasti merasa bersalah ya Le.” Sica berusaha berbicara agar aku menatap wajahnya kembali.
“Buat apa kau pedulikan perempuan itu. Ia yang menyebabkan dirimu seperti ini.”
“Kamu salah Le. Aku begini karena aku sendiri, karena kesalahanku sendiri. Aku berusaha melindungi harga diri kelas dengan menerima tantangannya, lalu kalah dengan memalukan hanya karena aku kelewat khawatir. Artinya aku kalah karena kekhawatiranku sendiri. Aku minta maaf Le.”
Sica mulai tersedu, air matanya yang bening mengalir melewati pipi indahnya. Gisel yang tersentuh melihat keadaan ini, memegang tangan Sica dan mengusap-ngusapnya.
“Kakak cantik jangan sedih ya, meskipun kakak tetap cantik ketika sedih.” hibur Gisel.
Sica tertawa kecil mendengar Gisel, ganti mengelus tangan Gisel. Aku, laki-laki yang berhati baja ini hampir saja larut terbawa emosi. Sayang, aku gengsi untuk ikut menumpahkan air mata.
“Kau tidak perlu minta maaf Sica. Tidak ada yang salah. Menurut analisa Juna, Kenji sedang mengejar Sarah untuk menyadarkannya.” aku bersuara untuk menghilangkan perasaan sendu di dalam jiwa.
“Juna?” Sica keheranan, tetap dalam keadaan berlinang air mata.
“Iya, aku secara tidak sengaja menemukan cara untuk berkomunikasi dengannya. Dan ternyata, aku sadar bahwa ia anak yang cerdas, pantas saja ia bisa mendapat nilai setinggi itu.”
“Jangan bicara nilai dulu Le, aku masih trauma, hehehe.” Sica sudah mulai kembali ceria.
“Oh maaf Sica.” kataku sembari menoleh ke arah meja disamping ranjang. Di saat itulah aku tersadar ketika melihat berbagai bunga dan roti serta susu yang tersedia di meja. Aku kemari tanpa membawa apa-apa!
“Ah Sica, aku lupa tidak membelikan apapun untukmu. Aku minta maaf.” kataku sambil menundukkan kepala karena malu.
“Tidak apa-apa kok Le, ini juga sudah terlampau banyak, nanti justru tidak termakan. Mama cerita kalau yang besar itu dari teman-teman sekelas, jadi anggap aja kamu termasuk di bingkisan itu.”
Itulah Sica yang kukenal, Sica yang sangat baik, yang sangat mempedulikan perasaan temannya. Aku jadi semakin heran, mengapa ia tidak memiliki teman perempuan yang dekat dengannya di kelas.
“Sica, siapa teman terdekatmu di kelas?”
“Kenapa kamu tanya itu Le?”
“Karena…karena aku jarang melihatmu berkumpul dengan teman-teman wanita yang lain.”
“Ternyata kamu diam-diam memperhatikan diriku ya Le.”
Pasti, aku yakin, pipiku berubah menjadi semerah bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya. Pernyataan blak-blakan dari Sica benar-benar tepat sasaran. Aku sampai tidak bisa menjawab apa-apa.
“Bisa dibilang, mungkin kamu Le teman terdekatku di kelas. Entah mengapa, aku sangat susah untuk bergaul dengan teman-teman perempuan. Bukan berarti kami saling membenci, aku pun sampai sekarang belum bisa menemukan alasannya.”
Bisa jadi mukaku meledak karena tingkat kemerahan yang berlebihan. Hanya saja karena dalam ilmu biologi tidak ada hal yang bisa menjelaskan mengapa wajah bisa meledak karena malu, hal itu tidak akan terjadi. Aku tidak boleh terlihat seperti orang yang tersipu, aku harus berbicara.
“Merupakan sebuah kehormatan bila aku kamu anggap sebagai teman terdekatmu.”
“Tumben Le kamu memanggil orang lain dengan kamu?”
Sekali lagi Sica membuatku terdiam. Aku yang selalu menggunakan kau untuk memanggil orang lain, entah mengapa tiba-tiba terselip menjadi kamu. Salah tingkahlah aku dibuatnya.
“Aku juga sering memperhatikanmu kok Le.”
Setelah Sica berkata demikian, ia membuang muka ke sisi lainnya. Mungkin aku salah, tapi aku yakin ia merasa malu setelah berkata demikian. Aku diperhatikan Sica? Rasanya ingin aku lompat dari jendela rumah sakit ini untuk melampiaskan kesenangan yang kurasakan. Untuk aku ingat, kamar Sica ini berada di lantai satu, percuma saja melopat. Aku hanya akan berakhir diantara semak-semak berduri.
“Ini imajinasinya Gisel aja, atau memang di ruangan ini sedang ada banyak sekali bentuk hati yang melayang diantara kakak sama kakak cantik?”
Responku adalah langsung menutup Gisel dengan tanganku, sementara Sica tertawa dengan terkikik hingga terbatuk-batuk. Aku segera mengambilkan segelas air yang ada di dalam meja, dan membantunya untuk meminum air tersebut.
“Terima kasih Le, adikmu benar-benar menggemaskan.”
“Gisel kalau ngomong memang sering tidak dipikir terlebih dahulu.”
“Ih kakak, Gisel kan cuma ngomong apa adanya.”
Aku tatap Gisel dengan tatapan yang mengisyaratkan “diamlah”. Gisel membalas dengan tatapan “emang takut”. Kubalas lagi dengan tatapan “lihat saja nanti di rumah”. Berhasil, Gisel berhenti menatap diriku dan menjadi lebih tenang.
“Kalian berdua lucu ya, sayang aku anak tunggal, jadi tidak tahu rasanya memiliki saudara.” Sica memberi komentarnya setelah melihat adu tatap kami.
“Gisel mau kok jadi adiknya kakak cantik.”
“Kakak juga mau jadi kakaknya adik cantik.” Sica membalas pernyataan Gisel.
“Kalau kakak mau enggak jadi, emmm, apanya kak Sica ya.” Gisel bertanya kepada dirinya sendiri.
Namun kalimat polos itu berhasil membuatku dan Sica kembali bertatap mata, kali ini tatapan yang, apa ya, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mata hitamnya begitu jernih, menunjukkan kecerdasan di baliknya, garis senyumnya menunjukkan kebaikan di dalam hatinya. Aku merasa berada di dalam ruang waktu yang berjalan dengan lambatnya, seolah jauh dari gravitasi. Kami saling berpandangan, hingga aku mengeluarkan kata-kata yang cukup membuatku bunuh diri karena malu.
“Kakak ingin menjadi orang yang selalu berada di samping Sica untuk selamanya.”

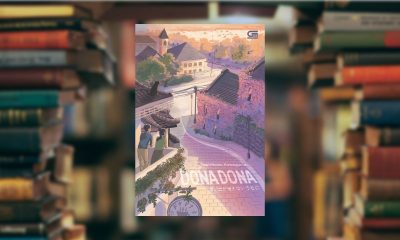
 Buku4 bulan ago
Buku4 bulan ago
 Fiksi3 bulan ago
Fiksi3 bulan ago
 Permainan3 bulan ago
Permainan3 bulan ago
 Permainan4 bulan ago
Permainan4 bulan ago
 Olahraga4 bulan ago
Olahraga4 bulan ago
 Anime & Komik5 bulan ago
Anime & Komik5 bulan ago
 Anime & Komik4 bulan ago
Anime & Komik4 bulan ago
 Musik5 bulan ago
Musik5 bulan ago

























You must be logged in to post a comment Login