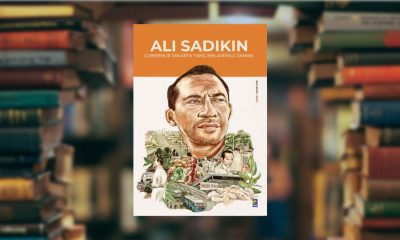Sosial Budaya
Gue, Lu, dan Jakarta Sentris
Published
4 tahun agoon
By
Fanandi
Sejak zaman masih bocah, Penulis sudah mengetahui kalau kosa kata gue lo itu identik dengan Jakarta. Maka di dalam mindset Penulis, kata tersebut hanya digunakan oleh orang-orang Jakarta.
Kenyataannya tidak seperti itu lagi. Banyak orang daerah yang notabene bukan orang Jakarta atau tidak tinggal/sedang di Jakarta menggunakan kata tersebut.
Fenomena ini menggelitik Penulis untuk mencari tahu apa penyebab dan latar belakangnya. Apalagi, banyak orang-orang terdekat di sekitar Penulis yang menunjukkan hal tersebut.
Jakarta Sentris dalam Bahasa
Mengapa anak yang berada di Sulawesi bisa mengetahui seperti apa orang Jakarta berbicara? Kalau zaman dulu jawabannya mudah, melalui saluran televisi ataupun radio.
Sejak dulu, tayangan-tayangan yang ada di televisi terlihat sangat Jakarta Sentris. Istilah ini pertama kali Penulis ketahui dari Pakde Penulis melalui sebuah diskusi.

Terpengaruh dari Tayangan TV (IDN Times)
Mau sinetron, kuis, bahkan tayangan berita pun berpusat di Jakarta. Lihat saja kantor pusat stasiun televisi, semuanya berlokasi di Jakarta. Mereka hanya punya kantor cabang di daerah.
Akhirnya, logat-logat Jakarta yang mendominasi di televisi pun menjadi konsumsi seluruh orang di Indonesia. Tidak sedikit yang merasa ingin menirunya, entah apa motivasinya.
Bagaimana dengan sekarang? Lebih parah dengan kehadiran media sosial. Mau orang Jakarta ataupun Malang, kebanyakan akan mengirim tweet atau status dengan menggunakan kata gue atau w, bukan aku atau saya.
Ada banyak alasannya, mulai dari ingin terlihat gaul, tidak ingin merasa ketinggalan, meningkatkan kepercayaan diri, meniru idola, hingga agar tidak dinilai kampungan oleh netizen lainnya.
Proses ini terjadi secara alamiah. Kalau tidak salah slangnya adalah Monkey See Monkey Do. Manusia meniru tindakan manusia lain tanpa benar-benar memahami esensinya.
Apakah ini salah? Tentu tidak. Orang bebas mengekspresikan dirinya dengan bahasa yang ia nyaman gunakan. Hanya saja, ada sisi negatif yang membuat Penulis cukup merasa prihatin.
Superioritas Bahasa
Orang yang menggunakan logat Jakarta biasanya akan merasa lebih keren dan prestise. Akibatnya, bahasa daerah bahkan Bahasa Indonesia yang baku akan terlihat inferior.
Mayoritas manusia tidak ingin terlihat inferior, sehingga mereka memutuskan untuk ikut menggunakan bahasa yang dianggap superior agar tidak merasa kecil dan lebih percaya diri.

Mengancam Bahasa Indonesia? (Dream)
Apalagi, orang yang menggunakan bahasa daerah kerap mendapatkan label buruk seperti kampungan dan norak. Akibatnya jelas, orang akan merasa malu untuk menggunakannya.
Tidak heran kalau hegemoni logat-logat Jakarta (tidak hanya gue lu) tumbuh subur di tengah-tengah kita, terutama generasi milenial yang sangat dekat dengan media sosial.
Bahkan ada yang menganggap kalau bahasa gaul Jakarta ini berpotensi merusak Bahasa Indonesia sekaligus menggerus bahasa-bahasa daerah yang makin ditinggalkan.
Apa artinya orang daerah tidak boleh menggunakan logat Jakarta? Tentu saja boleh, apalagi yang sedang merantau atau sedang di Jakarta sebagai proses adaptasi. Kata teman Penulis, menyesuaikan diri dengan di mana kita berada.
Penulis terkadang merasa inferior ketika mengobrol dengan teman-temannya yang memang orang Jakarta. Demi adaptasi, Penulis mencoba meniru gaya mereka berbicara. Tapi, hasilnya lucu.
Gue dan Lu untuk Lidah Penulis
Pada penerbangan Surabaya-Jakarta pada awal tahun 2020, Penulis tanpa sengaja bertemu dengan teman SMA yang sudah tidak bertemu semenjak kelulusan. Ia kuliah di Bandung dan merintis karir di Jakarta.
Iseng Penulis bercerita, kalau Penulis masih kesulitan untuk menggunakan kata gue lo. Ternyata, teman Penulis yang sudah 3 tahun di Jakarta ini juga masih menggunakan aku kamu.

Saling Menghargai Saja (Vecteezy)
Penulis sudah hampir 2 tahun di Jakarta. Selama itu pula, Penulis terus mengalami kesusahan untuk mengucapkan kata gue. Selain karena tidak terbiasa, lidah Jawa Penulis membuatnya terdengar aneh. G-terlalu tebal dan ue-nya terlalu mantul.
Daripada ditertawakan karena terlalu memaksa, Penulis pun lebih sering menggunakan kata aku kamu. Kalau menggunakan lu, Penulis masih bisa karena tingkat kemudahannya.
Tapi jadinya lucu, karena Penulis sering mengombinasikan aku dan lu. Agak enggak nyambung, sehingga seringkali Penulis mengganti lu dengan kata dirimu yang lebih netral. Untungnya, teman-teman di sini yang asli Jakarta mau memahami ini.
Tidak hanya itu, Penulis juga mengalami kesulitan menghafal istilah uang seperti ceban, goceng, gocap, dan lain sebagainya. Sangat sering Penulis tertukar-tukar, sehingga sering bertanya terlebih dahulu sebelum mengatakannya.
Karena merasa lidahnya tidak cocok dengan logat Jakarta, Penulis mencoba untuk lebih percaya diri menggunakan bahasa yang dikuasai. Bahkan, tak jarang Penulis menggunakan Bahasa Jawa ketika mengobrol dengan teman yang juga bisa berbahasa Jawa.
Mungkin tidak semua seperti Penulis. Pasti ada banyak orang daerah yang bisa langsung lancar berlogat Jakarta dan terdengar natural. Rasanya Penulis butuh latihan yang insentif agar lidahnya bisa lebih luwes.
Dengan demikian, Penulis bisa mengucapkan gue lu tanpa terdengar ganjil.
Penutup
Menggunakan bahasa apapun pada dasarnya adalah hak manusia. Hanya saja jika alasannya karena merasa inferior, rasanya kurang baik, seolah kita memaksa diri untuk menjadi orang lain.
Kita mungkin bisa mencontoh bagaimana orang Osaka bangga akan aksennya dan tidak malu jika sedang berbicara dengan orang Tokyo yang notabene ibukota Jepang.
Hal ini Penulis ketahui dari komik Detective Conan, sehingga mohon maaf jika kenyataannya seperti itu. Tapi mengingat orang Jepang bangga dengan bahasa mereka, Penulis yakin memang seperti itu.
Bisakah kita lebih percaya diri dengan bahasa kita sendiri dan tidak terpengaruh fenomena Jakarta Sentris dalam bahasa? Penulis serahkan jawabannya ke pembaca sekalian.
Sumber Artikel: Kumparan, Tirto, Wikipedia
Kebayoran Lama, 19 April 2020, terinspirasi dari orang-orang di sekitar Penulis yang menggunakan gue/lu yang padahal bukan orang Jakarta dan tidak pernah tidak tinggal di Jakarta
Foto: YouTube
You may like
Sosial Budaya
Ketika Pengakuan Sosial Menjadi Kebutuhan Pokok
Published
4 hari agoon
23 Juli 2024By
Fanandi
Jika menengok ke beberapa peristiwa yang sempat menjadi perbincangan netizen, Penulis menemukan sebuah pola di mana hidup di era sekarang terkesan membutuhkan pengakuan sosial sebanyak mungkin.
Bahkan, banyak hal yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan pengakukan sosial tersebut, termasuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Kebutuhan untuk diakui dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain seolah mengalahkan kebutuhan hidup lainnya.
Fenomena ini pun berhasil menarik perhatian Penulis. Berhubung banyak momen yang berhubungan dengan hal ini belum pernah Penulis bahas, Penulis ingin merangkum semuanya di sini.

Berbagai Cara untuk Dapatkan Pengakuan Sosial

Hal yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu adalah adanya joki Strava. Awalnya, Penulis tidak mengetahui apa itu Strava, hingga akhirnya menemukan fakta kalau itu merupakan sebuah aplikasi yang akan melacak aktivitas olahraga kita seperti lari atau bersepeda.
Tampaknya Strava ini menjadi gaya hidup yang sedang hype, di mana pengguna akan membagikan hasil olahraganya ke media sosial. Masalahnya ada saja orang yang enggan berolahraga, tapi tidak ingin ketinggalan dengan tren ini.
Alhasil, muncullah joki Strava. Mereka akan beraktivitas sesuai permintaan, lantas melakukan screenshot ke aplikasi Strava untuk dikirimkan ke klien. Nanti, klien bisa mengunggahnya ke media sosial seolah ia yang telah melakukannya.
Jika mundur lagi ke belakang, salah satu hal yang ramai dibicarakan ketika bulan puasa adalah adanya jasa sewa lanyard untuk digunakan ketika ikut buka puasa bersama (bukber). Lanyard tersebut seolah menjadi semacam medali yang bisa dibanggakan kepada teman-temannya, walau kenyataannya ia berbohong (di bulan puasa lagi).
Bicara tentang sewa, ada juga jasa sewa iPhone. Ponsel buatan Apple ini memang seolah telah beralih fungsi menjadi penanda status sosial. Bahkan, katanya kalau tidak menggunakan iPhone, maka kita tidak akan bisa masuk ke circle pertemanan!
Masih ada banyak contoh bagaimana kita seolah haus akan pengakuan sosial, termasuk memaksa orang lain memanggil kita haji. Namun, rasanya contoh-contoh di atas sudah cukup untuk menggambarkan fenomena ini.
Mengapa Kita Begitu Haus dengan Pengakuan Sosial?

Rasanya manusiawi jika kita merasa insecure dengan orang lain, apalagi jika kita merasa belum bisa sesukses orang lain. Namun, hal tersebut menjadi masalah apabila kita menggunakan jalan pintas untuk menutupi rasa insecure tersebut.
Dari contoh yang sudah Penulis sebutkan, kita rela mengeluarkan uang (yang Penulis yakin tidak sedikit) untuk membohongi orang lain. Padahal tidak olahraga, update Strava. Tidak kerja di BUMN, pakai lanyard BUMN. Punyanya ponsel Android murah, malah sewa iPhone.
Tidak hanya membohongi orang lain, hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai membohongi diri sendiri. Hanya demi pengakuan sosial dan tidak direndahkan oleh orang lain, kita rela untuk melakukan hal-hal semu tersebut.
Penulis pernah mendapatkan cerita dari adik tentang temannya yang dari luar terlihat hidup glamor. Pakaiannya modish, ponselnya iPhone, dan lain sebagainya. Kenyataannya, ia hidup dengan meminjam uang dari teman-temannya demi memenuhi gaya hidupnya tersebut.
Kita menemukan satu alasan untuk mengapa kita rela membohongi dirinya sendiri: demi menuruti gengsi dan gaya hidup. Demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, utang ke banyak orang hingga tidak punya teman pun akan dilakukan.
Cerita lain adalah bagaimana adik Penulis, yang ponselnya hanya Samsung biasa, seolah mendapatkan diskriminasi dari teman-temannya yang pada menggunakan iPhone. Ribet karena tidak bisa AirDrop, kata mereka.
Cerita-cerita tersebut menjelaskan alasan lain mengapa orang rela membohongi dirinya sendiri: karena terkadang lingkungan yang menuntut mereka seperti itu. Kondisi ini diperparah dengan media sosial yang kerap menunjukkan gaya hidup konsuntif.
Padahal, sebenarnya orang lain tidak peduli-peduli amat sama kita. Lantas, mengapa kita menjadi begitu bingung agar dipedulikan oleh mereka? Mengapa harus membohongi diri sendiri dan orang lain untuk itu? Penulis masih tidak habis pikir hingga sekarang.
Penutup
Bertahun-tahun yang lalu, ayah Penulis memberikan nasehat kalau kita sebagai manusia tidak membutuhkan pengakuan orang lain. Siapa yang menyangka, nasehat tersebut masih sangat relevan hingga sekarang, bahkan terlalu relevan.
Terkadang kita memang membutuhkan validasi dari orang lain, terutama saat kita sedang down. Namun, validasi yang paling penting datang dari diri sendiri. Mau siapa pun memberi validasi, kalau kita tidak mampu memvalidasi diri sendiri, ya percuma.
Jadi, menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan validasi dari orang lain ya percuma, karena di lubuk hati terdalam kita tahu kalau kita sedang membohongi diri kita sendiri. Jalan pintas tersebut cuma menjadi topeng demi menutupi kenyataan hidup yang ada.
Daripada terus membohongi diri sendiri dan orang lain demi pengakuan sosial, lebih baik kita fokuskan diri untuk berbenah. Daripada terus mencari pengakukan sosial, lebih baik kita terus memperbaiki diri agar kita bisa mendapatkan pengakuan dari diri sendiri.
Tingkatkan skill dan value diri agar bisa beneran kerja di kantor yang prestise dan bisa beli ponsel impian. Lawan rasa malas dan mulai berolahraga. Itu memang pilihan yang lebih sulit, tapi itu merupakan jalan benar, bukan jalan pintas yang sesat.
Lawang, 21 Juli 2024, terinspirasi setelah melihat fenomena joki strava dan kejadian-kejadian lainnya
Foto Featured Image: SIROKO
Sosial Budaya
Korea Selatan dan Reality Show: Sarana Promosi Negara ke Dunia
Published
1 bulan agoon
19 Juni 2024By
Fanandi
Seperti yang pernah Penulis bahas dalam tulisan-tulisan sebelumnya, belakangan ini Penulis kembali mengikuti dunia per-K-Pop-an sejak berkenalan dengan Twice. Bahkan, yang kali ini bisa dibilang lebih intens berkat algoritma yang dimiliki oleh YouTube Music.
Meskipun menikmati musiknya, sebenarnya Penulis tidak terlalu suka menonton video performance atau konser mereka. Penulis justru lebih tertarik menonton berbagai acara reality show maupun talkshow yang melibatkan mereka.
Oleh karena itu, Penulis juga jadi sering menonton acara yang melibatkan para idol girlband yang musiknya Penulis dengarkan, terutama Runningman dan Weekly Idol. Apalagi, banyak dari mereka yang memiliki acaranya sendiri, seperti Time to Twice dan 1, 2, 3 IVE.

Saat menonton acara-acara tersebut, Penulis pun jadi sadar akan sesuatu. Hampir di semua episode reality show tersebut, terselip berbagai hal yang terkesan “mempromosikan” Korea Selatan kepada dunia. Reality show digunakan untuk mempromosikan negaranya.
Bagaimana Reality Show Korea Selatan Menjadi Sarana Promosi

Sebelum bersentuhan dengan dunia K-Pop, yang Penulis ketahui tentang Korea Selatan hanya mereka pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Selain itu, yang Penulis tahu lagi tentu Park Ji-sung, pemain sepak bola top yang pernah berseragam Manchester United.
Setelah berkenalan dengan K-Pop, Penulis jadi mulai mengenal Korea Selatan lebih luas. Selain dari segi musik dan persaingan industri yang keras, Penulis juga jadi banyak mengenal banyak hal mulai dari bahasa, budaya, hingga makanan.
Salah satu yang “berjasa” untuk hal tersebut bagi Penulis adalah Runningman. Acara yang sudah berjalan ratusan episode tersebut kerap diadakan di berbagai tempat di Korea Selatan, yang secara tak langsung menjadi sarana promosi wisata untuk menarik wisatawan.
Meskipun acaranya “kejar-kejaran” (setidaknya di episode-episode awal), selalu ada saja B-roll yang memperlihatkan keindahan lokasi yang digunakan untuk syuting, entah itu di pusat kota Seoul hingga tempat yang jauh seperti Jeju Islands.
Tidak hanya tempat wisata yang ditonjolkan, banyak episode Runningman yang juga menonjolkan kuliner asli Korea Selatan. Selalu ada shot di mana para member dan bintang tamu terlihat sangat menikmati hidangan yang ada.
Pola ini juga Penulis temukan di reality show lainnya yang Penulis tonton seperti Time to Twice dan 1, 2, 3 IVE. Bahkan salah satu member dari IVE, Rei, memiliki kanal YouTube sendiri bernama 따라해볼레이 by섭씨쉽도 (Follow Rei) dan memiliki pola yang serupa.
Contoh di episode 27 ketika acara tersebut mengundang member IVE lainnya, Leeseo. Pada episode tersebut, Rei dan Leeseo melakukan piknik di pinggir sungai Han yang terkenal sembari menikmati berbagai makanan Korea Selatan.
Selain itu, bahasa yang digunakan sudah pasti menggunakan bahasa Korea. Sama seperti penonton anime, penonton reality show Korea Selatan pun jadi termotivasi untuk bisa memahami bahasa Korea Selatan agar tidak perlu menggunakan subtitle lagi untuk menonton.
Bagaimana Indonesia (Harusnya) Bisa Mengadopsi Strategi Reality Show Korea Selatan

Tentu Korea Selatan tidak hanya memanfaatkan K-Pop dan reality show untuk menyebarkan berbagai budaya dan mempromosikan pariwisata serta makanannya. Drama dan film Korea Selatan pun sudah sangat mendunia.
Namun, menurut Penulis memanfaatkan reality show sebagai sarana promosi negara adalah ide yang cerdik. Berbeda dengan K-Pop dan drama yang mungkin cukup segmented, reality show cenderung bisa lebih dinikmati oleh orang banyak.
Contoh, Penulis biasanya mengajak ibunya untuk menonton acara-acara reality show Korea Selatan, tentu yang sekiranya bisa masuk dan dipahami oleh beliau. Walau kadang lebih banyak berkomentar mengenai “operasi plastik,” ibu Penulis ternyata bisa menikmati reality show tersebut.
Salah satu alasannya adalah reality show dikemas dalam bentuk hiburan, sehingga terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati. Kita tidak perlu mengikuti alur cerita atau memiliki selera musik tertentu, karena reality show memang dibuat agar mudah dipahami.
Karena perannya untuk menghibur, tentu penonton akan sering tertawa ketika menontonnya. Oleh karena itu, penonton pun tak keberatan (dan mungkin tidak sadar) jika di dalam acara tersebut terselip promo-promo terselubung, entah dari segi pariwisata, budaya, maupun makanan.
Konsep inilah yang menurut Penulis perlu Indonesia tiru, bagaimana cara mempromosikan negara kita tercinta ini melalui acara reality show yang bisa diterima oleh banyak orang secara global. Menurut Penulis, peluang ini masih belum sering kita eksplorasi.
Mungkin permasalahan utamanya adalah belum terlalu mendunianya para public figure kita jika dibandingkan dengan public figure Korea Selatan. Penulis sendiri menonton reality show Twice dan IVE karena itu acara mereka. Jika yang melakukan orang lain, mungkin Penulis tidak akan menontonnya, tak peduli mau semenarik apapun acaranya.
Memang sudah banyak sekali public figure kita yang mendunia, entah dari dunia musik, film, dan lainnya. Namun, Penulis cukup ragu kalau nama mereka sampai digila-gilai oleh orang dari negara lain seperti mereka menggilai idol K-Pop.
Kalaupun belum bisa mengglobal karena alasan tersebut, menyasar pasar lokal dulu pun tidak masalah. Kalau menargetkan masyarakat kita sendiri, tentu tujuannya adalah meningkatkan pariwisata domestik sekaligus memberikan edukasi.
Contoh yang baru saja Penulis temukan adalah seri Kisarasa di YouTube. Dipandu oleh Chef Renata dan Chef Juna, acara ini mampu membalut acara kuliner secara unik, di mana sinematografi dan narasinya berbeda dengan kebanyakan kanal kuliner lainnya.
Kisarasa seolah dibuat untuk melestarikan makanan-makanan khas nusantara, dengan menayangkannya kepada penonton. Dengan melihat episode-episodenya, pengetahuan kita akan kuliner menjadi meningkat, sekaligus menimbulkan keinginan untuk membeli makanan tersebut.
Namun, Kisarasa lebih cocok disebut sebagai dokumenter daripada reality show karena tidak memiliki unsur hiburan. Penulis merasa konten-konten berkualitas seperti acara ini kurang bisa diterima oleh mayoritas penonton Indonesia, apalagi jika melihat jumlah view video-videonya yang kebanyakan hanya berkisar di angka ratusan ribu hingga satu jutaan.
Penulis membayangkan ada sebuah konsep acara hiburan dengan kualitas seperti Kisarasa, tapi dibuat lebih ringan, penuh candaan, dan diselipi oleh berbagai promosi budaya, wisata, makanan, hingga bahasa daerah. Bahkan, kalau bisa acara tersebut dinikmati hingga penonton di luar Indonesia.
Semoga saja sebenarnya sudah ada, Penulis saja yang belum mengetahuinya.
Lawang, 19 Juni 2024, terinspirasi setelah menyadari kalau Korea Selatan memanfaatkan variety show sebagai media promosi wisata, budaya, hingga makanannya
Foto Feature Image: YouTube
Sosial Budaya
Layakkah Pemain Judi Online Dianggap Korban dan Mendapatkan Bansos?
Published
1 bulan agoon
17 Juni 2024By
Fanandi
Belakangan ini masyrakat heboh dengan pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Pasalnya, ia menyebutkan kalau korban judi online (judol) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos)!
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyetujui wacana tersebut. Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa para korban judol tidak akan mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah.
Yang jelas, hal ini memicu emosi dari sebagian masyarakat yang menganggap kalau korban judol tidak layak untuk mendapatkan bansos. Muhadjir sendiri akhirnya merevisi ucapannya dengan mengatakan bansos yang dimaksud diperuntukkan untuk keluarga korban judol.
Pertanyaannya, apakah pantas pemain judol (yang kalah, tentu saja) pantas dianggap sebagai korban?

Pemain Judol yang Tak Sadar sedang Diakali Sistem

Sewaktu kecil, Penulis pernah membaca komik (lupa judulnya) yang bercerita tentang seorang pebisnis besar yang ingin mewariskan perusahaannya secara terbuka. Siapapun yang merasa layak, boleh mencoba mendaftar dan nanti akan mengikuti beberapa ujian.
Menariknya, salah satu ujiannya adalah bermain judi berbagai jenis, mulai poker sampai roulette. Dari komik tersebut, Penulis baru tahu kalau hasil dari judi tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan bandar.
Awalnya logika Penulis menganggap kalau hal tersebut hanya terjadi di komik untuk memberikan kesan dramatis. Ternyata, setelah melihat beberapa konten di media sosial, di dunia asli pun ada banyak manipulasi seperti yang diceritakan di komik tersebut.
Nah, kalau yang offline dan dilihat banyak orang saja manipulasi banyak dilakukan, apalagi judi online yang menggunakan sistem komputer yang tak terlihat? Ada banyak sekali celah untuk memanipulasi pemain agar terus bermain.
Di game Borderlands 3 yang sedang Penulis mainkan, ada fitur permainan slot yang menggunakan uang in-game (bukan uang asli) untuk mendapatkan item-item tertentu seperti senjata. Itu saja lebih sering zonk-nya, sangat jarang ada item bagus yang bisa didapatkan.
Mirip dengan judi di Casino, tentu pemain baru akan dikasih menang dulu agar memberikan efek dopamin dan membuat mereka terus melakukan deposit. Setelah itu, kekalahan demi kekalahan akan mereka terima. Kalaupun menang, tentu hasilnya sedikit.
Karena merasa yakin permainan berikutnya akan menang, maka mereka akan terus melakukan deposit. Tak jarang jika mereka menggunakan uang dari berbagai sumber, termasuk memanfaatkan jasa pinjam online (pinjol) yang tentu akan menimbulkan masalah baru.
Pemain Judol Dikasih Bansos, Layak atau Tidak?

Mungkin akan ada yang berargumen kalau mereka bermain judol untuk sekadar have fun, bukan untuk meraih kekayaan instan. Nah, dari sini pola pikirnya sudah salah karena judinya sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh agama mana pun.
Mau sedikit, mau banyak, kalau salah ya tetap salah. Apapun alasannya, kalau hal buruk ya jangan dilakukan. Begal yang melakukan pencurian motor (hal buruk) demi menghidupi keluarganya (niat baik) juga tidak akan kita benarkan, bukan?
Apalagi, banyak pemain judol yang sampai habis miliaran. Bayangkan dari Perwira TNI hingga anggota DPR pun ada yang terseret judol. Ini menunjukkan kalau pemainnya bukan dari kalangan miskin saja. Masa iya main judol miliaran layak dapat bansos?
Penulis kerap mendapatkan cerita dari teman-temannya bagaimana para pemain judol ini sudah begitu kecanduan sehingga sama sekali tidak bisa dinasehati, entah itu untuk have fun atapun mau dapat uang instan.
Mereka tidak sadar kalau dirinya sedang diakali dan dibodohi oleh sistem. Logikanya, mana ada bandar judi yang mau rugi? Pasti mereka mau meraup keuntungan sebesar-besarnya dari hasil deposit para pemain. Apalagi, manipulasi di judol lebih mudah dan tak terlihat.
Oleh karena itu, Penulis sama sekali tidak setuju jika para pemain judol dianggap sebagai “korban” dan butuh mendapatkan bansos. Mereka adalah korban dari kelakukan buruk mereka sendiri dan harus menanggung konsekuensinya. Mereka tidak layak mendapatkan bansos.
Penulis justru khawatir kalau bansos yang diberikan, jika berupa uang, akan digunakan untuk deposit. Meskipun diberi ke keluarganya sekalipun, potensi untuk salah digunakan sangat besar mengingat tabiat mayoritas dari pemain judol.
Pemberian bansos juga membuat mereka tidak akan merasa jera bermain judol. Pikir mereka, “Tenang aja, walau boncos tetap dapet bansos.” Tentu hal ini terasa tidak adil bagi masyarakat yang mungkin pas-pasan tapi tidak kebagian jatah bansos karena dianggap kurang miskin.
Jika pemerintah memang mau memberikan bantuan kepada pemain judol, lakukan saja rehabilitasi untuk menghilangkan kecanduan judol. Walau belum tentu berhasil, setidaknya itu lebih baik dibandingkan memberi mereka “insentif.”
Penutup
Judol adalah salah satu permasalahan terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Bayangkan saja, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat trasaksi judol mencapai Rp600 triliun.
Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya tidak diam saja melihat hal ini. Presiden Joko Widodo telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas judol yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim telah menutup jutaan situs judol, walaupun situs judol ini mati satu tumbuh seribu. Menkominfo juga melakukan SMS Blast yang efeknya sebenarnya sama dengan peringatan kematian di bungkus rokok, alias ga ngefek.
Masyarakat jelas menuntut pemerintah untuk menghadirkan solusi-solusi lain yang lebih konkrit untuk memberantas judol yang kian meresahkan ini, bukan justru memberi bansos kepada para pemainnya. Penulis rasa semua yang masih waras akan menentang ide ini.
Lawang, 17 Juni 2024, setelah muncul wacana mengenai pemain judol yang akan mendapatkan bansos
Foto Featured Image: LinkedIn
Sumber Artikel:
- Muhadjir Luruskan ‘Korban Judol Dapat Bansos’: Yang Terima Keluarganya (detik.com)
- Menko Airlangga Tegaskan, Bansos Untuk Korban Judol Tak Ada di APBN – Kedai Pena
- Jadi Miskin karena Main Judi Online Bisa Dapat Bansos, Begini Penjelasannya kata DPR (tvonenews.com)
- 7 Fakta Terbaru Judi Online RI: Transaksi Rp600 T-Bakal Dapat Bansos (cnnindonesia.com)

Ketika Pengakuan Sosial Menjadi Kebutuhan Pokok

Cara Saya Hilangkan Kebiasaan Buruk Dikit-Dikit Cek HP

Kemenangan Perdana yang Awkward Bagi Oscar Piastri di Formula 1

Yu-Gi-Oh!: Komik, Duel Kartu, dan Nostalgianya

Koleksi Board Game #21: Century: Spice Road

Koleksi Board Game #14: Kakartu Se-kata

Asa Leverkusen untuk Mengejar Status Invincibles Sempurna

Badai Cedera Manchester United yang Tak Kunjung Berlalu

[REVIEW] Setelah Membaca Twenty-Four Eyes: Dua Belas Pasang Mata

Artikel pada Tulisan Ini Dibuat Menggunakan AI (ChatGPT)
Tag
Fanandi's Choice
-
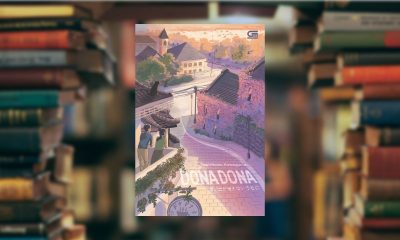
 Buku4 bulan ago
Buku4 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Dona Dona
-

 Fiksi3 bulan ago
Fiksi3 bulan ago[REVIEW] Setelah Membaca Keajaiban Toko Kelontong Namiya
-

 Permainan3 bulan ago
Permainan3 bulan agoKoleksi Board Game #14: Kakartu Se-kata
-

 Permainan4 bulan ago
Permainan4 bulan agoKoleksi Board Game #13: Coup
-

 Olahraga4 bulan ago
Olahraga4 bulan agoKenapa Fans Manchester United Banyak yang Sombong?
-

 Anime & Komik5 bulan ago
Anime & Komik5 bulan agoTerima Kasih, Akira Toriyama, Selamat Jalan
-

 Anime & Komik4 bulan ago
Anime & Komik4 bulan agoBagaimana Mr. Satan (Benar-Benar) Menyelamatkan Dunia Dua Kali
-

 Musik5 bulan ago
Musik5 bulan agoBagaimana Algoritma YouTube Music Membuat Saya Menyelami K-Pop